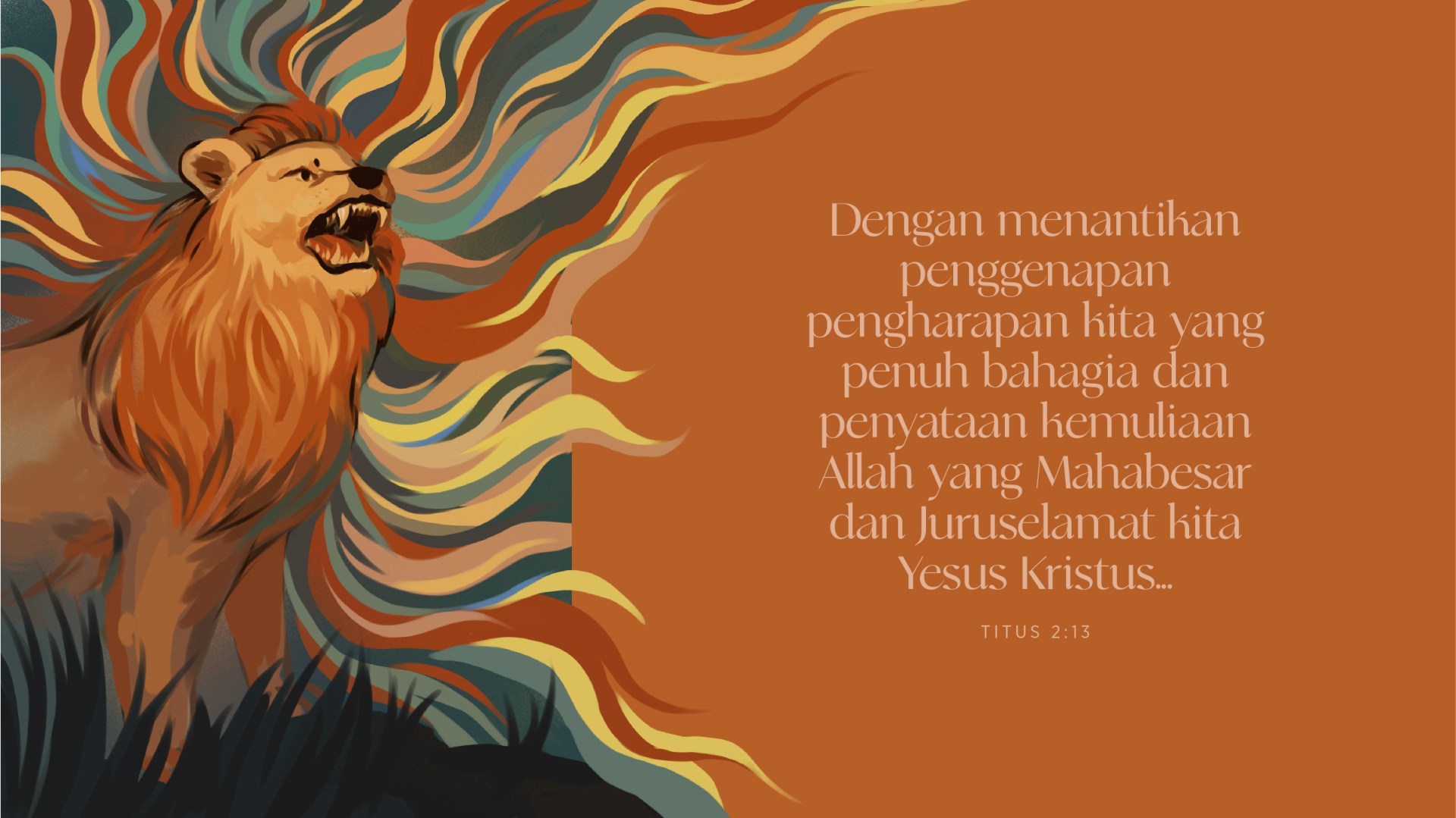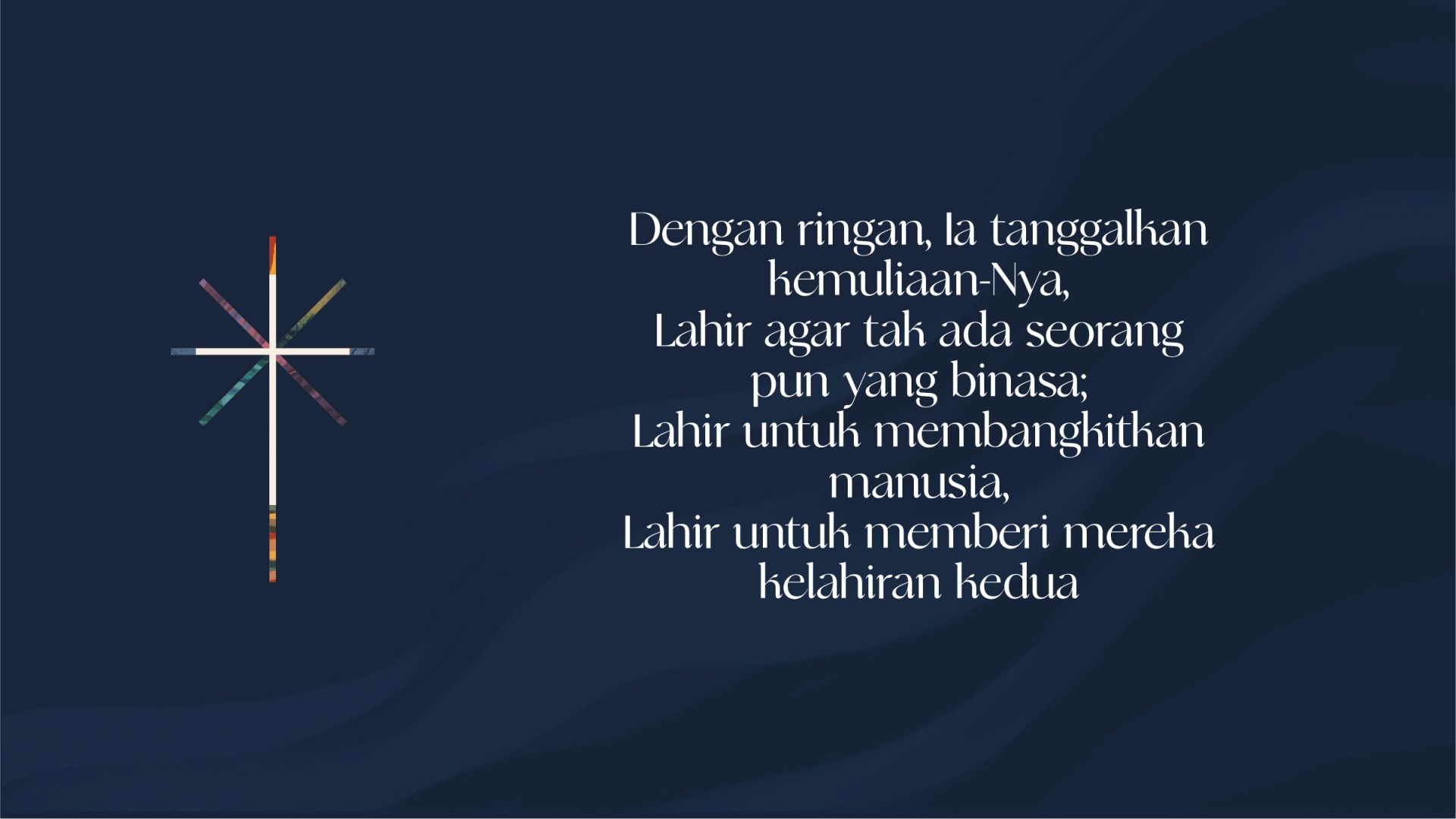Di sini Anda akan menemukan semua bacaan renungan harian kami yang akan membantu Anda mempersiapkan diri untuk Natal selama masa Adven ini.
Minggu Adven 1: Kembalinya Kristus dan Pemerintahan Kekal
Minggu Adven 2: Dosa & Penebusan
Minggu Adven 3: Pengorbanan & Keselamatan
Minggu Adven 4: Inkarnasi & Kelahiran
Epifani
Untuk mengunduh kumpulan renungan “Berita Injil di Masa Adven,” klik di sini.