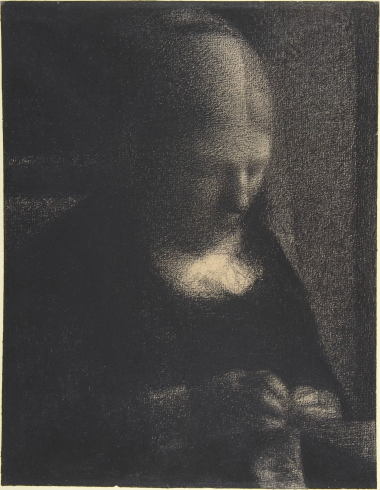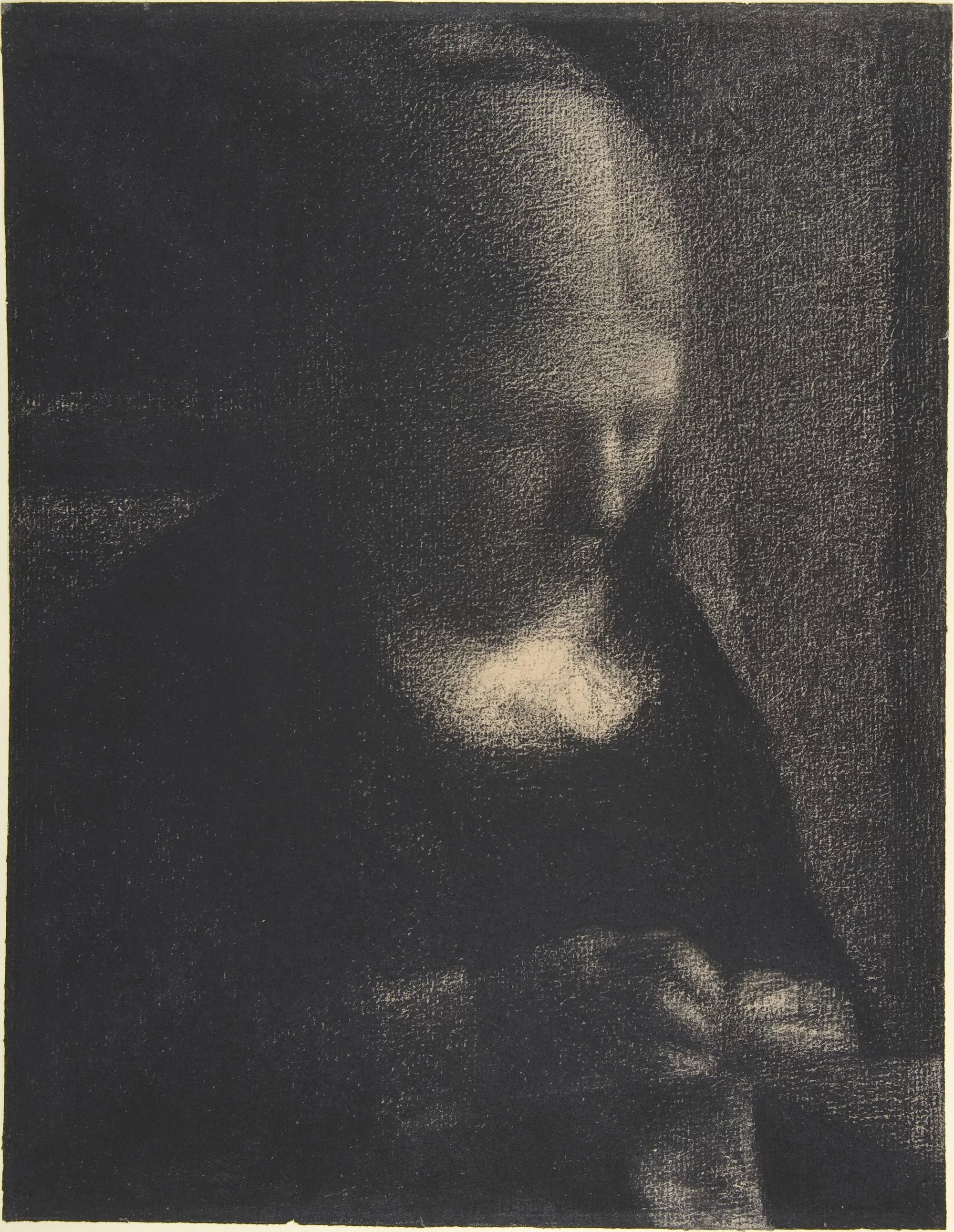Unduh Renungan Prapaskah
Apakah kita telah menyia-nyiakan hidup kita? Itulah pertanyaan yang baru-baru ini berkelana di benak saya sebelum menikmati kopi di pagi hari. Saat bangun tidur, saya terjebak dalam lumpur keputusasaan terkait gereja, yang terkadang menimpa siapa pun yang terlibat dalam pelayanan—atau yang menikahi seorang hamba Tuhan.
Ada banyak tahun yang telah berlalu dalam pelayanan di gereja ketimbang yang tersisa di masa yang akan datang. Meski demikian, untuk hal ini saya tidak bersedih. Kesedihan mungkin akan datang nanti ketika suami saya, Brent, tak lagi naik mimbar dan harus menyimpan collar kependetaannya. Namun, pagi itu, saya mempertanyakan apa yang perlu kami perlihatkan terkait 30 tahun pelayanan selama ini, dengan 11 gereja yang telah kami layani, dan semua awal yang baru dengan berbagai ucapan perpisahan dan penyambutan yang ada?
Ada banyak hal yang baik dan benar tentang kehidupan dan gereja ini; kami telah digerakkan oleh kasih Yesus serta bagaimana umat-Nya menghangatkan satu sama lain dan juga dunia ini dengan jenis kasih yang merupakan dari keajaiban gereja; kasih yang begitu indah bagi seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, kami telah menjadi bagian dari jemaat yang berbagi kehangatan kasih ini melalui proyek renovasi rumah gratis, ceramah parenting, berbagai kegiatan bersama para anak muda, drama dan konser, penjualan dan simfoni, dukungan bagi para pengungsi, makan malam di hari Jumat, makan siang sup, kalkun panggang di atas piring pada hari Natal, program Alpha dalam segala bentuknya, ibadah tradisional dan musik kontemporer serta berbagai hal lainnya, semuanya diimpikan demi komunitas tertentu di tempat kami berada.
Pada sebagian besar waktu tersebut (menurut saya), gereja menawarkan kasihnya tanpa pamrih. Tangan yang penuh kasih dan terbuka lebar, sangat ingin berbagi. Namun terkadang di bawah lapisan kasih tersebut—setidaknya bagi saya—terdapat keinginan yang nyaris kelihatan untuk menjangkau lebih banyak orang sehingga gereja kami bisa menjadi lebih besar dan karena itu menjadi lebih baik, dan karena semakin baik maka akan menjadi lebih besar. Menjadi gereja itu. Untuk menjadi sukses dalam kreativitas dan jumlah jemaat serta persembahan dan dampak. Untuk membusungkan dada dan melebarkan sayap kita.
Dalam hal ini, saya harus bertobat. Inilah yang harus saya lepaskan. Evaluasi jujur apa pun tentang mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan sekarang, hampir selalu membawa kita pada semacam pertobatan. Saya memandang sekeliling altar ini dan melihat bahwa saya tidak sedang berlutut sendirian. Mengenai hal ini kita pasti dapat bertobat, bukan dari pertumbuhan itu sendiri, melainkan dari pertumbuhan demi pertumbuhan.
Ketika sarapan di gereja baru-baru ini, saya mengagumi kalung dari seorang jemaat wanita. Perhiasan tersebut terbuat dari manik-manik kayu dengan ukiran gajah kecil. Sepertinya kalung ini telah dipilih dengan cermat di kios cendera mata yang penuh dengan ukiran dan batik, sebagai kenangan akan perjalanan yang indah. “Saya sangat menyukainya,” ucap saya kepadanya. “Terima kasih,” katanya, sambil menyentuh perhiasan itu. Saat dia membuka mulut untuk melanjutkan percakapan, teman saya, yang semakin rapuh seiring bertambahnya usia, mendapati dirinya bingung.
“Saya tidak ingat kata yang ingin saya sampaikan,” katanya sambil menepuk kepala salah satu gajah kecil itu.
“Apakah Anda ingin saya membantu Anda?” saya menawarkan.
“Tidak, terima kasih,” katanya. “Saya lebih suka berusaha sendiri.” Dengan seekor gajah kecil di antara jari-jemarinya, teman saya mengobrak-abrik gudang pikirannya untuk mencari kata-kata yang hilang. Kami menunggu. Mungkin akan masuk akal jika saya mengubah topik pembicaraan, namun hal itu rasanya tidak menghormati usaha yang ia lakukan. Beberapa saat pun berlalu. Kami masih berdiri dalam keheningan. Akhirnya, kami dipanggil untuk makan. Kami saling tersenyum, mengangkat bahu, dan pergi untuk mengantre.
Percakapan kami tidak produktif. Kami tidak menyelesaikan satu hal pun. Kami berpisah dan saya pergi mencari croissant dan selai crabapple. Secara teknis, dan secara waktu, peristiwa yang terjadi itu bukanlah sebuah kesuksesan. Akan tetapi di gereja, waktu yang terbuang bisa menjadi sebuah karya kasih.
Beberapa minggu kemudian saya berdiri di belakang mimbar selama Perjamuan Kudus dan menyaksikan orang-orang datang dan pergi, seperti yang biasa saya suka lakukan. Orang-orang berjalan menyusuri lorong samping untuk menerima roti Perjamuan, dan kemudian kembali ke tempat duduk mereka melalui lorong tengah dengan sisa-sisa tanda x yang ditempel di karpet merah bekas pembatasan jarak di hari-hari sebelumnya.
Kemudian terlihatlah wanita tua itu, berjalan kembali ke kursinya di lorong tengah, memegang roti di tangan yang ditangkupkannya untuk dikonsumsi ketika dia kembali duduk, salah satu dari sedikit peraturan terkait COVID yang masih kami miliki saat itu. Di belakang wanita tersebut ada lusinan jemaat yang memperlambat langkah mereka untuk menyamai dia, agar tidak menyusulnya. Dia tidak terburu-buru. Dia tersenyum, sepertinya tidak menyadari kerumunan kecil yang ada di belakangnya. Ini adalah parade yang sangat lambat. Jemaat berjalan dengan perlahan di belakang dia, bagaikan sebuah iring-iringan suci. Hati saya terasa hangat dan saya tersenyum melihat hal itu.
Dalam pemandangan di hadapan saya itu, saya menyaksikan gereja berhasil dalam salah satu caranya yang terbaik dan kudus. Ada gereja yang indah dalam langkahnya yang lebih lambat dan sabar demi kasih semata. Gereja bukan saja dapat menawarkan pemberian langka ini kepada jemaatnya yang terkasih, tetapi juga kepada siapa pun yang kita temui dan gereja memiliki hak istimewa untuk berjalan di samping dan di belakang seseorang demi Yesus.
Setiap tahun, fajar Paskah mengingatkan kita bahwa apa yang mungkin dilihat dunia sebagai suatu kesia-siaan sebenarnya bisa menjadi sebuah keajaiban. Apa yang bagi orang lain tampak seperti seorang mesias yang gagal ternyata merupakan Mesias yang menggenapi perjalanan yang paling suci. Kematian adalah kehidupan, dan kubur yang kosong adalah penuh dengan janji yang akan mengubah segala sesuatu, dari dalam ke luar, dari bawah ke atas. Paskah adalah harapan yang paling cemerlang dan subversif, bagaikan seekor merak berkeliaran melewati jendela kami dalam hembusan angin di penghujung musim dingin di Kanada. Dari gereja di mana kami berada, Church Humble and Magnificent, kesuksesan terlihat berbeda dengan versi dunia.
Paskah membuktikan sekali dan selamanya bahwa Yesus bersama kita dalam perjalanan yang panjang, lambat, dan mungkin tidak terlihat sukses, tetapi sangat setia, dan, ya, sebuah iring-iringan yang suci.
Karen Stiller adalah penulis buku The Minister’s Wife: a memoir of faith, doubt, friendship, loneliness, forgiveness and more, dan editor majalah Faith Today. Ia tinggal di Ottawa bersama suaminya, Brent Stiller.
Artikel diterjemahkan oleh Timothy Daun.
Artikel ini merupakan bagian dari New Life Rising yang menampilkan artikel dan pendalaman Alkitab yang merefleksikan makna kematian dan kebangkitan Yesus. Terbitan khusus ini yang dapat digunakan selama masa Prapaskah, Paskah, atau kapan saja. Pelajari lebih lanjut di http://orderct.com/lent.