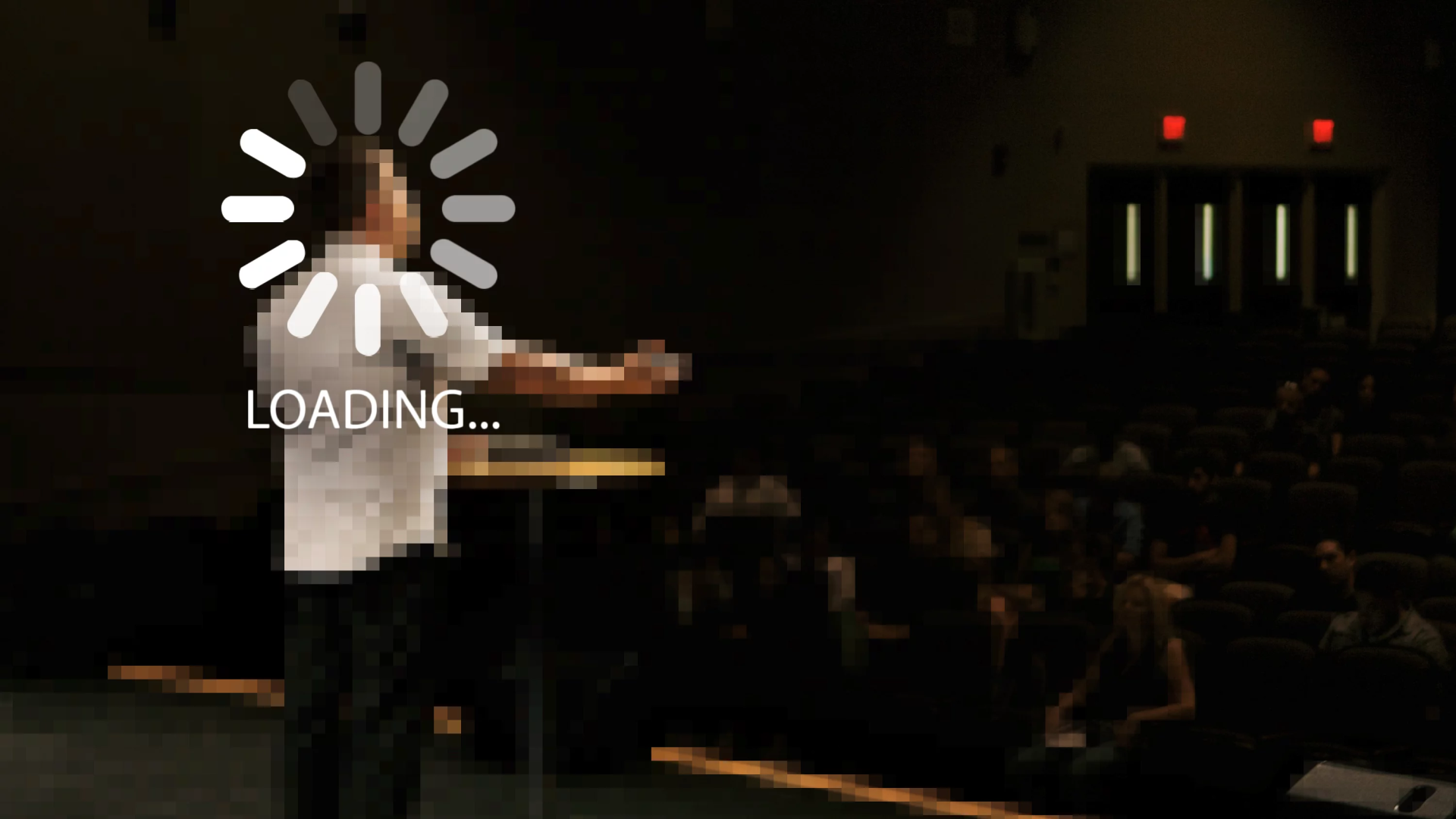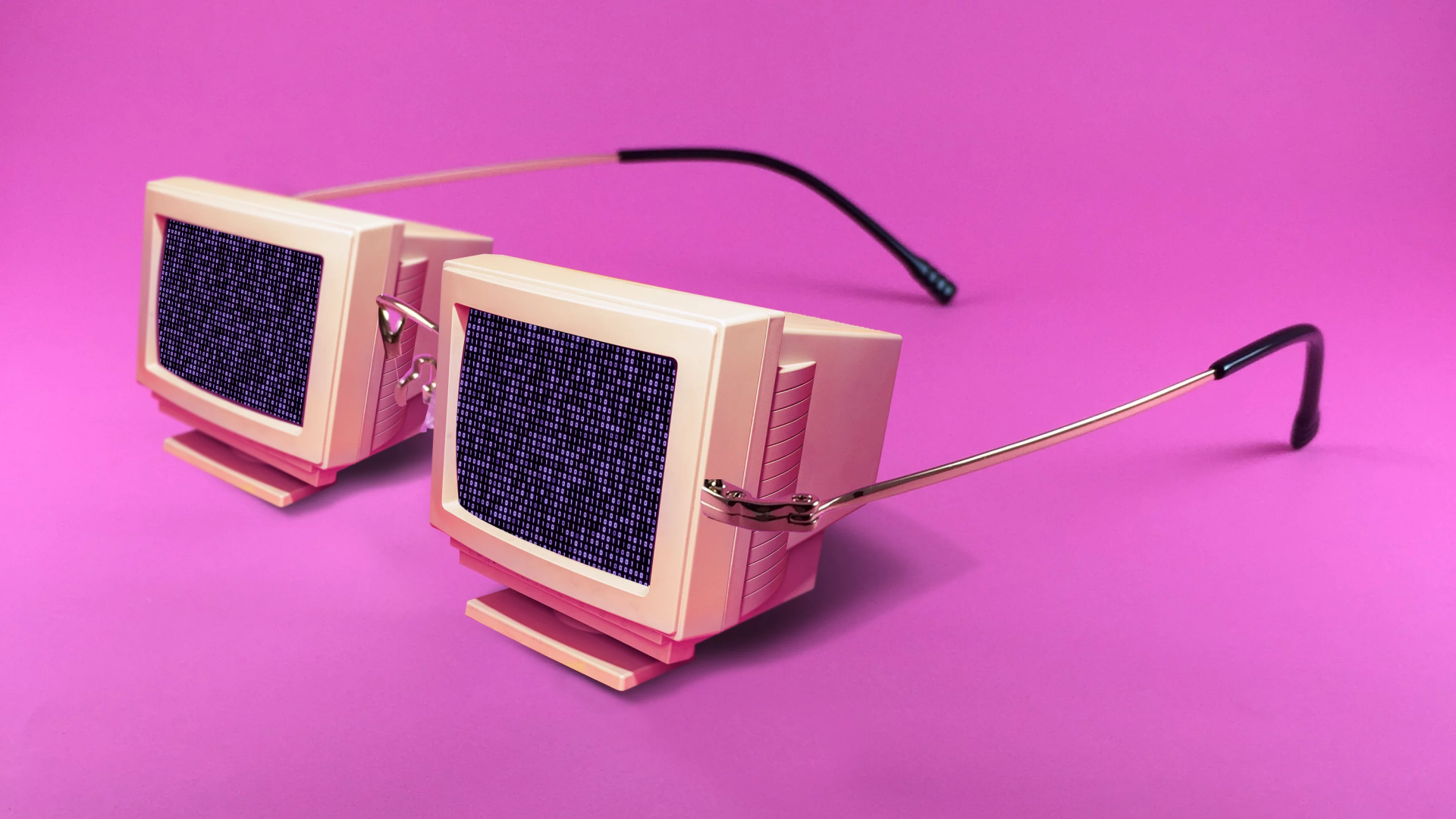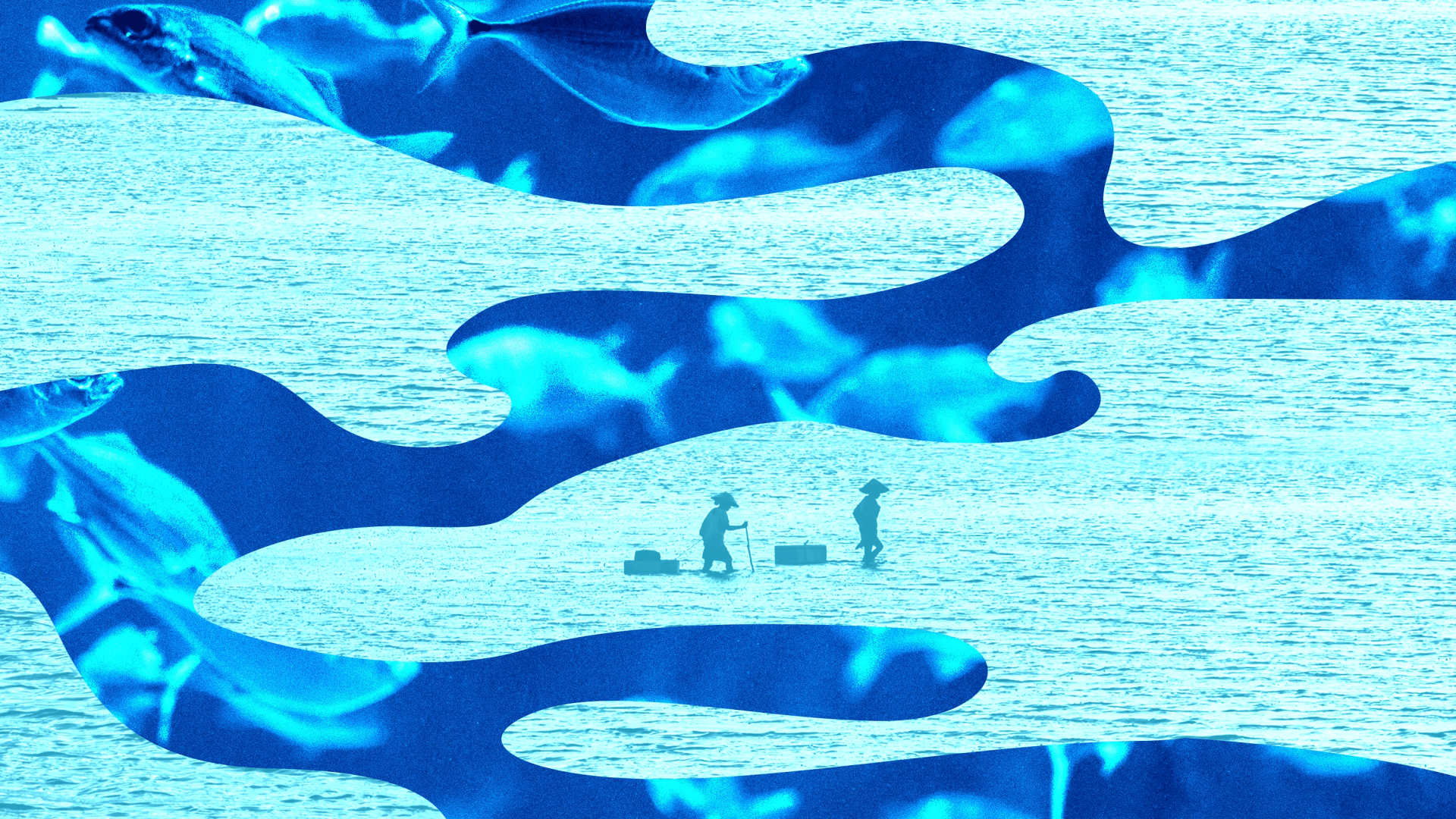Aryanna Schneeberg yang berusia delapan tahun sedang bermain di halaman belakang rumahnya ketika punggungnya terkena panah dari belakang. Seorang tetangga berusaha memanah seekor tupai, tetapi anak panahnya meleset dari sasaran dan malah menembus paru-paru, limpa, perut, dan hati anak tersebut. Meski berhasil selamat, ia harus menanggung bekas luka akibat kejadian tersebut. Kita perlu mengingat tentang Aryanna setiap kali kita mendengar seorang pengkhotbah menjelaskan kata Yunani untuk dosa, yaitu hamartia, yang berarti “meleset dari sasaran.”
Seperti berbagai hal klise di mimbar, kata yang satu ini mengacu kepada sesuatu yang sebagian benar. Namun masalahnya adalah imajinasi sebagian besar orang Kristen Barat, dipengaruhi oleh kisah Robin Hood, melebihi pengalaman mereka yang sebenarnya dalam memanah. Kita membayangkan suasana pedesaan di mana kita menembakkan anak panah ke arah sasaran di atas tumpukan jerami. Metafora ini lumayan menghibur: Kita melihat diri kita bukan sebagai penjahat atau pemberontak, tetapi sebagai orang yang sesekali keluar dari jalur. Lalu kita merogoh ke dalam tabung anak panah kita agar mendapatkan satu kesempatan lagi untuk melakukannya dengan benar.
Akan tetapi, bukan seperti itu cara Alkitab menggambarkan dosa. Alkitab mengatakan bahwa dosa adalah pelanggaran hukum (1Yoh. 3:4). Ketika mengategorikan dosa, Alkitab secara konsisten melakukannya dengan istilah-istilah yang menyiratkan baik pelaku maupun korban: permusuhan, pertikaian, penindasan terhadap anak yatim dan janda, perzinahan, ketamakan.
Dalam hal ini, dosa tidak seperti latihan memanah di suatu tempat yang terpencil, melainkan lebih seperti melepaskan anak panah di trotoar kota di tengah kerumunan orang banyak. Di sekeliling kita ada banyak tubuh yang menggeliat atau mati, terkena anak panah kita yang salah sasaran.
Dalam sebuah khotbah tentang dosa, seorang pengkhotbah mungkin juga mengutip John Owen dari kalangan Puritan: “Matikanlah dosa atau dosa akan mematikanmu.” Hal itu juga benar. Namun, itu belum cukup menjelaskan: Dosa kita mungkin juga mematikan orang-orang di sekitar kita. “Upah dosa adalah maut,” demikian Alkitab mengatakan kepada kita (Rm. 6:23). Kematian itu mungkin bukan hanya kematian diri sendiri, melainkan juga kematian sesama kita.
Kitab Wahyu adalah sebuah surat edaran kepada jemaat-jemaat yang sangat berbeda-beda. Beberapa jemaat tersebut secara aktif dianiaya oleh Roma, dan beberapa jemaat lainnya merasa nyaman dan tunduk kepada Roma. Dosa dan pencobaannya berbeda-beda, tetapi janji Tuhan sama: Allah akan menghakimi. Bagian selanjutnya dari kitab ini menunjukkan bagaimana penghakiman itu ditimpakan ke atas dunia, yang digambarkan sebagai Babel. Namun hal ini dimulai dari gereja. Pertanyaannya bagi umat Tuhan adalah apakah kita akan menjadi pratinjau dari Babel atau Yerusalem Baru?
Salah satu alasan mengapa kitab Wahyu tampak begitu asing bagi banyak orang adalah karena penggambarannya yang sering kali samar-seekor binatang buas keluar dari laut, seorang perempuan pelacur duduk di atas tujuh gunung (13:1; 17:9). Namun yang paling misterius, bukankah kitab ini menggambarkan dilema yang dihadapi oleh kita semua saat ini?
Roma-kota tujuh gunung-pada saat itu adalah kota yang mewah, kaya, dan penuh penyembahan berhala, yang menunggangi seekor binatang buas yang mengerikan dan berkuasa-sebuah kekaisaran yang luas dan mendominasi. Binatang buas itu mengendalikan dengan memanfaatkan rasa takut akan penderitaan. Si Pelacur mengendalikan dengan rayuan akan kemewahan dan kenyamanan. Binatang buas itu berkata, “Bergabunglah denganku dan aku akan memberimu akses menuju kekuasaan.” Pelacur itu berkata, _“Bergabunglah denganku dan aku akan memberimu akses menuju kesenangan.” Namun, di balik semua itu, terdapat kepalsuan. Binatang buas itu berupaya untuk meniru Anak Domba yang terluka, yang menaklukkan, dan menandai suatu bangsa bagi diri-Nya sendiri. Babel adalah distorsi dari kerajaan Allah.
Bukan hanya kekaisaran secara harfiah yang bisa menjadi binatang buas. Pelayanan juga bisa. Kita mungkin berpikir bahwa kita sedang menunjuk kepada Anak Domba, padahal kita hanya sedang mengulangi cara-cara binatang buas itu. Kita mungkin berpikir bahwa kita sedang melayani Kerajaan Allah, padahal sebenarnya kita hanya sedang membangun Babel yang akan runtuh dalam satu jam (Why. 17:12).
Yang harus kita kenali dan cabut bukan hanya satu berhala saja-ikonoklasme seksual atau supremasi kulit putih atau nasionalisme Kristen atau sinkretisme agama atau hanya iri hati, persaingan, dan keserakahan-melainkan semuanya. Kita seharusnya tidak boleh membagi diri kita di antara mereka yang membenarkan dosa-dosa “pribadi” dan mereka yang membenarkan dosa-dosa “sosial.”
Apakah kita sungguh percaya bahwa dosa kita benar-benar menyakiti orang lain? Apakah kita percaya bahwa pelayanan kita dapat, dan telah, benar-benar menyakiti orang lain? Jika ya, mari kita ingat kembali apa yang membuat kita menjadi kaum “Injili” sejak awal. Kita adalah orang-orang yang berkata kepada dunia, dan kepada diri kita sendiri, bukan hanya “Percayalah pada Kabar Baik itu” melainkan “Bertobatlah dan percayalah pada Kabar Baik itu.”
Allah adalah Allah yang penuh kasih karunia, Allah yang mengampuni kita orang berdosa melalui darah Anak-Nya. Namun, Ia juga adalah Allah yang menghakimi—yang dapat membedakan antara Yerusalem dan Babel, antara Anak Domba dan binatang buas. Pada masa penyingkapan ini, kita harus mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan kepada gereja-gereja, bahkan ketika metafora kita meleset dari sasaran.
Ted Olsen adalah editor eksekutif di CT.
Diterjemahkan oleh Helen Emely.