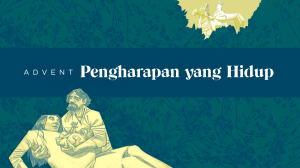In this series

Melompat ke bacaan harian: Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu
Minggu: Masa Antara
Bacaan Hari Ini: Wahyu 1:4–9; 19:11–16; 21:1–5, 22–27; 22:1–5
Dengan segera, pasal pertama surat Wahyu membawa kita memandang kemuliaan besar yang jauh melampaui keberadaan kita di bumi ini. “Aku adalah Alfa dan Omega … yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang” (1:8). Juruselamat “yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita” akan datang kembali, “Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia” (1:5, 7). Yohanes melanjutkan suratnya dengan menggambarkan sebuah penglihatan luar biasa tentang Kristus sendiri—sebuah perjumpaan yang begitu menakjubkan sampai-sampai Yohanes “tersungkur … sama seperti orang yang mati” (ay.17).
Namun, tepat di tengah kedua bagian yang menggambarkan kemuliaan itu ada sebaris kalimat yang mungkin mudah kita lewatkan: gambaran singkat Yohanes tentang kehidupannya dan kehidupan para pembaca suratnya. Yohanes menulis bahwa ia adalah “saudara dan sekutu … dalam kesusahan, dalam Kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus” (ay.9). Yohanes menulis surat Wahyu saat sedang berada di tempat pembuangan. Surat ini disirkulasikan di antara jemaat yang sedang menderita, menghadapi tekanan dan penganiayaan yang terus memburuk hingga beberapa dekade berikutnya. Penerima mula-mula kitab Wahyu hidup di tengah dua realita yang saling tumpang tindih. Pertama, mereka memiliki jaminan dalam pemerintahan Kristus yang berdaulat serta kedatangan kembali Kristus yang mulia. Kedua, mereka masih berada di bumi, setiap hari mengalami yang namanya menanti dan menderita.
Kurang lebih dua ribu tahun kemudian, kita pun masih hidup di tengah dua realita yang saling tumpang tindih ini. Di antara kedatangan pertama Kristus dan kedatangan-Nya kembali dalam kemuliaan, kehidupan kita mungkin juga terasa seperti percampuran dua dunia. Di satu sisi ada Kerajaan (Allah) dan keyakinan yang pasti. Di sisi lain ada penantian dan penderitaan.
Tak heran apabila penuturan jujur Yohanes tentang kesusahan dan perlunya bertekun dengan sabar dirangkai di dalam dan di antara penglihatannya tentang kemuliaan (Allah). Penglihatan tentang apa yang akan datang itulah yang memberikan kekuatan dan keberanian untuk bertekun. Perhatikan beberapa realita yang dipotret dalam akhir nan megah kitab Wahyu: Kristus yang menang mengendarai seekor kuda putih dan mengalahkan si jahat, langit dan bumi yang baru tanpa dukacita atau kematian, kemah kediaman Allah ada di tengah-tengah umat-Nya (21:1, 3), serta sebuah kota yang kudus tempat orang-orang dari segala bangsa berkumpul di dalam terang kemuliaan Allah. Saat kita bisa melihat realita-realita yang akan datang ini, situasi kita di dunia yang sementara ini—separah apa pun itu—terasa tidak lagi terlalu penting.
Perlunya bertekun dengan sabar diulangi beberapa kali dalam Wahyu 1-3, seringkali dipasangkan dengan ungkapan tentang kemenangan dan keberhasilan menaklukkan. Bertekun tidak hanya berarti sabar, tetapi juga teguh, berani, dan kuat. Inilah yang diberikan Allah kepada setiap kita yang hidup di masa antara. Dalam Kristus,—seperti yang dikatakan dalam lirik sebuah lagu—kita menemukan “kekuatan dan pengharapan tiap hari”.
Kelli B. Trujillo
Senin: Memberitakan Pengharapan
Bacaan Hari Ini: Zakharia 9:9–17; Roma 5:3–5, 8:18–30
“Pengharapan dimulai dalam gelap …” perkataan Anne Lamott dalam bukunya Bird by Bird ini tidak bisa saya sanggah. Apa yang ia sampaikan belakangan telah menjadi salah satu tema dalam hidup saya—bukan sebagai suatu pemikiran belaka, tetapi sebagai sesuatu yang nyata dijalani, suatu pergumulan, suatu komitmen, suatu disiplin.
Menurut ahli teologi Jürgen Moltmann, pengharapan itu berakar pada kebangkitan Yesus dan upaya nyata untuk mengubah keadaan. Adakalanya pengharapan menjadi satu-satunya bahasa yang cukup kuat untuk melawan keputusasaan. Dalam bahasa Lamott, (pengharapan) itu adalah sejenis “kesabaran yang revolusioner”.
Apa pun (definisi) pengharapan, sesuatu di dalam jiwa kita menyuarakannya. Terkadang terdengar kecil, seperti sebuah bisikan, tetapi suara itu ada di sana. Pengharapan terpancar dari kedalaman jiwa, dan seringkali lahir dari situasi yang kelam. Saat situasi serba kacau dan membingungkan, pengharapan muncul.
Di hari-hari tertentu, rasanya kita masih berada di bawah mendung pekat yang menyelimuti bumi saat Yesus disalib. Beratnya kehidupan di dunia ini terasa seperti kegelapan. Elie Wiesel, saat menceritakan tentang kengerian (kamp konsentrasi) Auschwitz dan (peristiwa) Holocaust, hanya bisa menyebut kegelapan itu sebagai “Malam”. Penderitaan adalah sebuah kenyataan yang harus kita akui. Dalam pengharapan pun, kita bisa menderita.
Saya duduk bersama nenek saya beberapa waktu lalu dan minta ia menceritakan tentang kehidupannya. Awalnya ia tidak mau. Tak terbayangkan bekas luka apa saja yang telah ditanggung jiwanya selama lebih dari 80 tahun. Ia telah menjalani kehidupan yang keras. Sulit untuk menggambarkan bagaimana ia hidup di wilayah Selatan sebagai seorang perempuan berkulit hitam. Ada satu kata yang tampak menggambarkan keberaniannya untuk bertahan di tengah dunia yang kejam: cinta. “Tuhan belum pernah mengecewakan saya,” katanya.
Cinta yang radikal, mengubahkan hidup, mengubahkan komunitas, mengubahkan dunia, adalah cara hidup Yesus. Ia telah datang untuk memberitakan kabar baik Kerajaan Allah serta menyembuhkan segala macam penyakit dan penderitaan. Memberitakan pengharapan adalah sebuah cinta yang berbahaya.
Martin Luther King Jr. berkata, “Kekuasaan terbaik adalah cinta yang mengimplementasikan tuntutan keadilan, dan keadilan terbaik adalah cinta yang mengoreksi segala sesuatu yang bertentangan dengan cinta.” Inilah artinya menjadi orang yang berdiri di dunia ini untuk memberitakan cinta, kuasa, dan keadilan, atau dalam bahasa nabi Zakharia, menjadi “orang tahanan yang penuh harapan” (9:12). Seseorang pernah menulis kalimat berikut: “Ku tak tau kan hari esok, tetapi aku tahu siapa yang pegang hari esok”. Esok hari akan datang, tetapi hari ini, aku akan memberitakan pengharapan.
Dante Stewart
Renungan ini diadaptasi dari artikel berjudul “Why We Still Prophesy Hope,”, diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2019, di situs web ChristianityToday.com.
Selasa: Datanglah Tuhan Yesus
Bacaan Hari Ini: Yohanes 1:1–5, 14; Wahyu 22:12–13, 20
Dalam Injil yang ditulisnya, Yohanes berkata, “Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. … Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita” (1:1, 14). Kita memiliki Allah yang telah datang. Dia datang untuk membuat apa yang tidak bisa disentuh menjadi bisa disentuh, dan apa yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Dia datang menyatakan diri-Nya untuk bisa kita kenal. Namun, kita memiliki pengharapan bukan hanya karena Dia sudah datang, melainkan juga karena Dia akan datang.
Dia akan datang kembali. Janji inilah yang bisa membuat kita menemukan makna dalam penderitaan dan frustrasi kita di dunia. Saat Dia datang kembali, orang benar akan dibuktikan benar. Saat Dia datang kembali, Dia akan membawa keadilan atas olok-olok yang Anda hadapi karena percaya kepada Allah yang tidak terlihat. Saat Dia datang kembali, orang-orang yang berusaha mengangkat diri mereka sendiri sebagai penguasa akan dilengserkan, dan kita akan melihat bahwa sebenarnya hanya ada satu Penguasa dan Raja yang sejati. Dalam sekejap, apa yang selama ini kita imani, akan kita saksikan di depan mata. Pribadi yang selama ini kita kenal dalam doa dan yang kita beritakan, akan kita lihat secara langsung.
Dalam Wahyu 22, Yesus berkata, “Sesungguhnya Aku datang segera dan Aku membawa upah-Ku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, Yang Pertama dan Yang Terkemudian, Yang Awal dan Yang Akhir” (ay.12–13). Yohanes mencatat, “Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, ‘Ya, Aku datang segera!’” (ay.20). Seakan-akan tidak punya kata lain untuk menutup suratnya, Yohanes menulis, “Amin, datanglah Tuhan Yesus!” (ay.20).
Menatap masa depan, mungkin ada hal-hal yang tidak kita kehendaki terjadi atas bangsa kita. Mungkin ekonomi tidak berkembang sebagaimana yang kita harapkan. Mungkin ada lebih banyak anak yang disakiti di jalanan, baik oleh senjata, oleh perdagangan manusia, atau oleh obat-obatan yang disalahgunakan. Banyak pernikahan mungkin penuh pergumulan. Kita mungkin menderita sakit-penyakit. Kita mungkin khawatir akan anak-cucu kita. Dalam semua yang kita alami, perkataan ini memberi pengharapan: Datanglah Tuhan Yesus.
Apa pun yang kita hadapi, kita tahu bahwa Dia akan datang kembali. Suatu hari, langit akan terbuka, malaikat akan meniup sangkakala, dan seluruh dunia akan melihat-Nya bersama-sama. Segenap ciptaan akan merespons saat Tuhan kita melangkah turun dari surga untuk berkata, “Sekarang Aku telah datang untuk menebus umat-Ku”. Amin. Datanglah, Tuhan Yesus.
Charlie Dates
Artikel ini diadaptasi dari khotbah Charlie Dates tanggal 22 Desember 2019. Digunakan dengan izin.
Rabu: Adven and Akhir Zaman
Bacaan Hari Ini: Markus 13:24–37; Lukas 21:25–28
Selama masa Adven, kita mendengar pembacaan bagian-bagian Kitab Suci yang berbicara tentang kegelapan, kesusahan, dan akhir zaman. Matius, Markus, dan Lukas, masing-masing punya satu pasal yang berbicara khusus tentang akhir zaman. Dalam Markus 13, Yesus berkata, “… bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan” (ay.8). Bagian selanjutnya dari pasal itu menggambarkan situasi yang makin kelam, “… pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang” (ay.24-25).
Mengapa Yesus justru berbicara tentang kematian dan kehancuran, bukan tentang domba, gembala, dan bala tentara surga?
Dalam Kitab Suci, tulisan tentang akhir zaman lahir pada masa kesusahan. Israel adalah umat pilihan, Allah telah menjanjikan kepada mereka masa depan yang aman dan sejahtera. Namun, kemudian, mereka ditaklukkan dan diangkut ke pembuangan di kerajaan Babel. Dalam pandangan manusia, tidak ada pengharapan bagi mereka. Saat umat Israel mengalami krisis, mereka ada dalam situasi “darurat teologis.” Dalam masa darurat inilah pemikiran baru tentang akhir zaman terbentuk. Dimulai dari bagian kedua kitab Yesaya (pasal 40-55)—ditulis pada masa pembuangan di Babel saat pengharapan sepertinya sudah tidak ada lagi—dan terus berkembang dari sana. Pada zaman Yesus, pembicaraan tentang akhir zaman sudah ada di mana-mana.
Yang terpenting dari teologi akhir zaman adalah teologi pengharapan—dan pengharapan adalah kutub yang berlawanan dengan optimisme. Optimisme bisa sirna ditelan kegelapan, kontras dengan pengharapan, yang ditemukan dalam sesuatu yang melampaui gelapnya sejarah manusia. Pengharapan ditemukan di dalam Allah yang berinkarnasi.
Injil Lukas mencatat, saat Yesus bicara tentang akhir zaman, tentang “tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang” dan bagaimana “bangsa-bangsa akan takut dan bingung”, Dia mengakhirinya dengan mengatakan bahwa manusia “akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya” (21:25–27). Yesus sedang bicara tentang kedatangan-Nya yang kedua kali. Dia sedang mengatakan bahwa pengharapan besar kita datang bukan melalui kemajuan peradaban umat manusia, melainkan melalui diri-Nya. Dia berdaulat, memiliki kuasa atas segala sesuatu, dan tidak bergantung pada sejarah manusia. Sekalipun kegelapan begitu nyata, Allah dalam Kristus sedang membentuk sejarah kita sesuai dengan tujuan-Nya yang ilahi.
Masa Adven menyatakan bahwa kita dapat menghadapi kegelapan, apa pun nama kegelapan itu. Namun, ceritanya tidak berakhir di sana. Yesus berkata, “bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat.”
Fleming Rutledge
Artikel ini diadaptasi dari artikel “Why Apocalypse Is Essential to Advent,” diterbitkan tanggal 18 Desember 2018 di situs web ChristianityToday.com.
Kamis: Sebuah Pertanyaan yang Lebih Penting
Bacaan Hari Ini: 2 Petrus 3:8–15
Mengapa begitu lama? Mengapa Yesus belum juga kembali seperti yang Dia janjikan? Hal-hal ini mungkin pernah ditanyakan oleh para penerima surat kedua Petrus—pertanyaan-pertanyaan yang terus menggema sampai hari ini. Petrus menjawab mereka dengan jaminan yang aneh: Pertama, bahwa waktu Allah merefleksikan kesabaran dan kasih-Nya yang menyelamatkan (3:8-9). Kedua, bahwa hari Tuhan itu menakutkan dan akan melibatkan kehancuran dengan api.
Bahasa akhir zaman seperti yang dipakai Petrus (mirip yang dipakai Yesus di Markus 13 dan Lukas 21) tentunya membuat kita berpikir sejenak. Apa maksudnya dengan “hangus dalam nyala api” dan “langit akan binasa dalam api”? Apakah ini sesuatu yang harus kita takutkan?
Ayat-ayat sebelumnya dalam 2 Petrus menyediakan perspektif untuk memahami bahasa kehancuran yang dipakai di pasal 3. Dalam pasal 2:5, kita membaca tentang situasi serupa pada zaman Nuh, saat Allah menghancurkan bumi dengan air bah. Penghakiman di masa itu tidak berarti Allah menyapu bersih semua ciptaan-Nya. Penghakiman terakhir dengan api kemungkinan juga demikian, Allah tidak akan menghanguskan seisi bumi untuk mendatangkan langit dan bumi yang baru. Sebagaimana yang digambarkan Petrus dalam Kisah Para Rasul, Kristus tinggal di surga “sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabi-Nya yang kudus di zaman dahulu” (3:21). Dunia yang baru akan datang melalui pemulihan besar dari Allah dan desain ulang dunia yang kita miliki sekarang.
Terangkai dalam bagian ini, Petrus memberikan satu pertanyaan penting yang sepatutnya kita perhatikan lebih daripada pertanyaan tentang kapan dan seperti apa kedatangan kembali Kristus itu. Mengetahui bahwa hari kedatangan Tuhan akan segera tiba, Petrus bertanya, “bagaimana seharusnya kalian hidup” (2Ptr. 3:11 BIS). Petrus mendorong pembaca suratnya untuk hidup kudus dan saleh, “menantikan” langit dan bumi yang baru dengan penuh pengharapan (ay.11-14). Kita melihat tema yang sama ditekankan dalam surat Petrus yang pertama, saat ia sungguh-sungguh mendorong orang percaya untuk hidup dengan penuh keyakinan, sukacita dan kewaspadaan, berfokus penuh pengharapan pada kedatangan Kristus (1Ptr 1:3-5, 13).
Kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan, sama seperti orang yang sudah diberi bocoran tentang akhir sebuah novel yang penuh dengan drama tak terduga. Kita tahu akhir ceritanya. Pengetahuan tentang akhir luar biasa yang menanti kita itu dapat mempengaruhi bagaimana kita menghadapi situasi sekarang. Kita mungkin tidak bisa tahu kapan atau bagaimana itu akan terjadi, tetapi kita dapat percaya bahwa pada akhir zaman akan ada penghakiman, sekaligus pembenaran bagi umat Allah. Bagaimana berita tentang penghakiman terakhir bisa membuat kita terhibur dan bukannya takut? Allah akan membuat bagian-bagian terbaik dunia ini menjadi makin baik, lebih dari yang bisa kita bayangkan. Penghakiman, pembenaran, dan transformasi akan datang. Tanah Perjanjian sejati menanti.
Vincent Bacote
Jumat: Menanti Pestanya Dimulai
Bacaan Hari Ini: 1 Tesalonika 4:13–5:11
Salah satu hal yang suka saya lakukan sebagai seorang profesor adalah memutarkan film-film yang mungkin dilabeli orang sebagai “film akhir zaman”. Banyak film dalam ketegori ini berfokus pada momen Pengangkatan, sebuah penafsiran 1 Tesalonika 4:17, yang memahami frasa “akan diangkat” sebagai gambaran kedatangan kembali Kristus yang tidak kelihatan untuk membawa umat-Nya ke surga bersama-Nya sebelum masa Kesusahan Besar tiba. Film-film ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran bahwa Yesus bisa datang kapan saja.
Ada banyak pendapat tentang Pengangkatan dan isu-isu akhir zaman lainnya. Saat membaca 1 Tesalonika 4-5, kita bisa dengan mudah berfokus hanya pada bagian yang membicarakan hal tersebut. Namun, ada banyak poin penting lain tentang kedatangan kembali Kristus, yang juga patut mendapat perhatian kita, termasuk apa yang tampaknya menjadi penekanan Paulus di sini: bagaimana menghibur orang-orang Kristen yang masih hidup, terkait status orang-orang percaya yang sudah meninggal. Apakah mereka (yang sudah meninggal) akan “ketinggalan” dan tidak mengalami kedatangan Yesus kembali?
Inilah penghiburan Paulus untuk jemaat di Tesalonika (dan juga kita): kita tidak perlu khawatir Allah akan melupakan mereka yang sudah meninggal. Kebangkitan Kristus adalah sebuah jaminan bahwa kematian tidak akan menghalangi mereka untuk ikut masuk ke dalam dunia baru yang akan tiba bersamaan dengan kedatangan Kristus yang kedua. Baik kita masih hidup atau sudah meninggal, relasi kita dengan Kristus adalah satu-satunya yang diperlukan untuk kita bisa terdaftar sebagai tamu undangan saat hari kedatangan Tuhan itu tiba.
Saat Kristus datang, akan ada pembukaan yang megah, lengkap dengan musik yang meriah. Trompet Allah akan berbunyi (4:16 BIS)—gambaran yang tentunya dipahami jemaat di Tesalonika sebagai kembalinya seorang pemimpin terhebat yang telah menang. Tidak seperti bunyi trompet lain, trompet ini akan membangkitkan orang-orang yang mati dalam Kristus untuk menyambut kedatangan Kristus, bersama-sama dengan mereka yang masih hidup.
Gambaran serupa bisa kita baca dalam surat pertama Paulus kepada jemaat di Korintus. Di sana juga dibahas tentang kematian, “musuh terakhir” yang akan dihancurkan Kristus (15:26). Paulus meyakinkan jemaat di Korintus bahwa “pada waktu terdengar bunyi trompet itu, orang-orang mati akan dihidupkan kembali dengan tubuh yang abadi, dan kita semuanya akan diubah” (15:52 BIS). Sengat maut kehilangan kuasanya karena kemenangan Kristus yang sempurna.
Sembari menantikan hari itu, kita dipanggil untuk mempersiapkan diri: “berbajuzirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan” (1Tes 5:8). Kedatangan yang seperti “pencuri di waktu malam” ini akan sangat mengejutkan, karena hanya Allah sendiri yang tahu kapan hari tersebut akan tiba—tetapi hari itu akan menjadi pesta kejutan terbesar yang pernah ada bagi setiap kita yang menanti-nantikan kedatangan-Nya.
Vincent Bacote
Sabtu: Pengharapan Bagi Yang Disfungsi
Bacaan Hari Ini: 1 Korintus 1:1–9
Saat kita membaca tentang kedatangan kembali Kristus dalam 1 Korintus, penting untuk mengingat konteks surat Paulus ini. Jemaat di Korintus adalah sebuah komunitas yang penuh dengan masalah. Ada perpecahan dalam jemaat yang mendukung pemimpin mereka masing-masing, ada skandal seksual, ada kontroversi tentang daging persembahan untuk berhala, dan banyak lagi. Meskipun komunitas Kristen ini mengalami banyak disfungsi, dalam 1 Korintus 1:1-9, Paulus menyebut mereka sebagai orang-orang yang dikuduskan (“saints” atau orang-orang suci dalam terjemahan King James). Paulus kemudian mengingatkan bahwa Allah telah begitu bermurah hati kepada mereka dengan menyediakan karunia-karunia rohani dan menggambarkan mereka sebagai umat yang “menantikan” kedatangan Kristus kembali. Paulus menekankan kasih karunia Allah (ay. 4) dan komitmen-Nya bagi mereka: “Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya” (ay.8). Sekalipun iman mereka lemah sebagaimana tampak dalam perilaku dan sikap mereka yang berdosa, kesetiaan Allah kepada mereka (dan juga kita) meliputi komitmen-Nya untuk menolong umat-Nya bertumbuh dan diubahkan makin serupa Kristus.
Sementara pasal 1 menekankan bahwa Allah, dengan kasih karunia-Nya akan meneguhkan jemaat di Korintus sampai kepada kesudahannya, dalam surat yang sama Paulus menggambarkan kedatangan Kristus dan mendesak jemaat di Korintus, “Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah” (15:58, penekanan dengan huruf miring ditambahkan). Paulus memanggil mereka untuk memiliki keteguhan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penantian akan kedatangan Kristus kembali. Terlepas dari banyaknya kesalahan dan kegagalan mereka, Paulus memanggil mereka untuk mengalami transformasi dan memiliki determinasi.
Kita melihat gambaran keteguhan serupa dalam surat Paulus yang lain: “Sementara kita “menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Mahabesar dan Juruselamat kita Yesus Kristus,” kasih karunia Allah “mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi” (Titus 2:11–14).
Membaca 1 Korintus atau surat-surat Paulus lainnya, mau tidak mau kita akan memperhatikan betapa kuatnya Paulus membahas soal dosa dan disfungsi. Namun, sebagaimana yang ditunjukkan dalam 1 Korintus 1:8-9, tanggapan Paulus terhadap masalah-masalah yang besar itu selalu dilatarbelakangi dengan pengharapan yang besar. Kita dipanggil untuk melakukan bagian kita, sementara Allah, dalam kasih karunia-Nya, juga terus melakukan pekerjaan-Nya dalam hidup kita.
Jemaat di Korintus adalah sebuah contoh, sekaligus sebuah penghiburan bagi kita. Kebanyakan kita mungkin pernah mengalami momen disfungsi rohani kita masing-masing, tetapi kegagalan kita tak seharusnya menjadi fokus utama kita. Sebaliknya, kita dapat melihat kepada Yesus, yang tidak hanya membuat rekonsiliasi dengan Allah menjadi mungkin, tetapi yang juga berkomitmen menolong kita supaya kita dapat menghadap Allah dengan tidak bercacat saat kerajaan-Nya tiba. Puji Tuhan, kesetiaan-Nya lebih besar daripada disfungsi kita.
Vincent Bacote
Kontributor:

Vincent Bacote adalah lektor kepala bidang teologi di Wheaton College. Beliau adalah penulis buku The Political Disciple: A Theology of Public Life.
Charlie Dates adalah gembala sidang di Chicago's Progressive Baptist Church. Beliau meraih gelar PhD dalam Teologi Historis dari Trinity Evangelical Divinity School.
Fleming Rutledge, seorang pendeta gereja episkopal, melayani selama 21 tahun di gereja lokal sebelum kemudian menjadi seorang dosen, penulis, dan guru dari banyak pengkhotbah lainnya. Beliau adalah penulis buku The Crucifixion.
Danté Stewart adalah seorang penulis dan pengkhotbah yang belajar di Fakultas Teologi Candler di Universitas Emory.
Diterjemahkan oleh: Echa Puspita
–