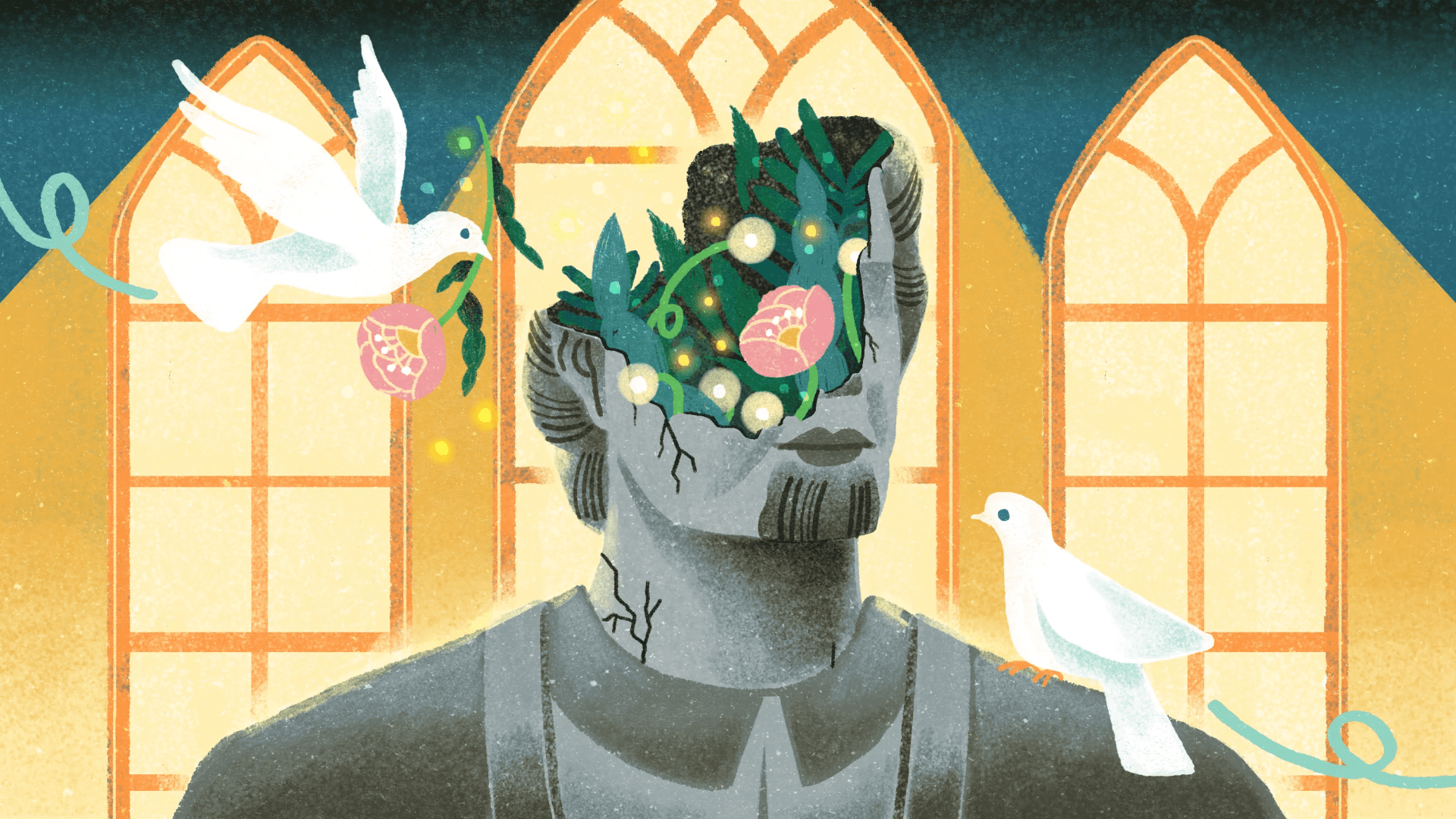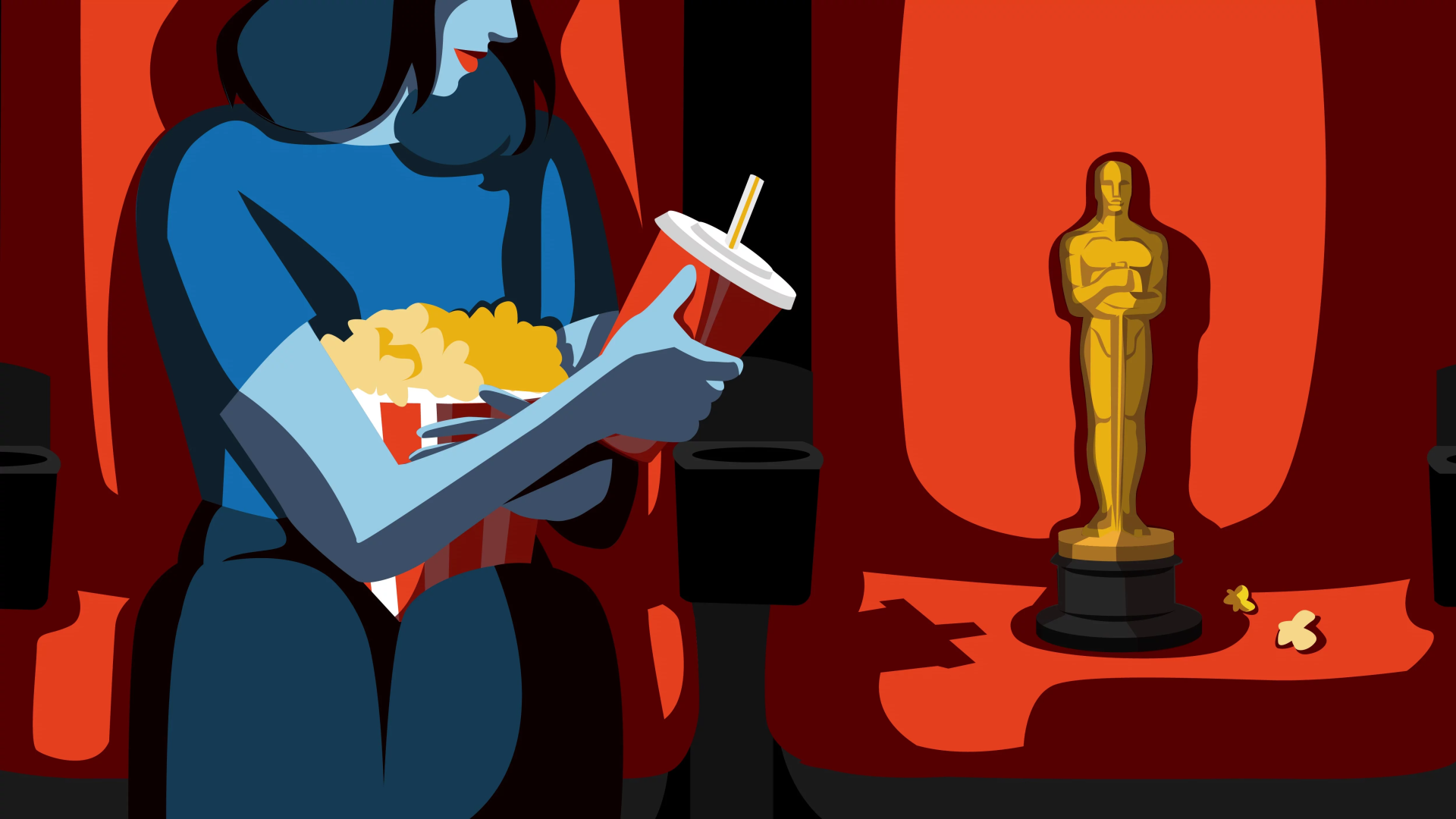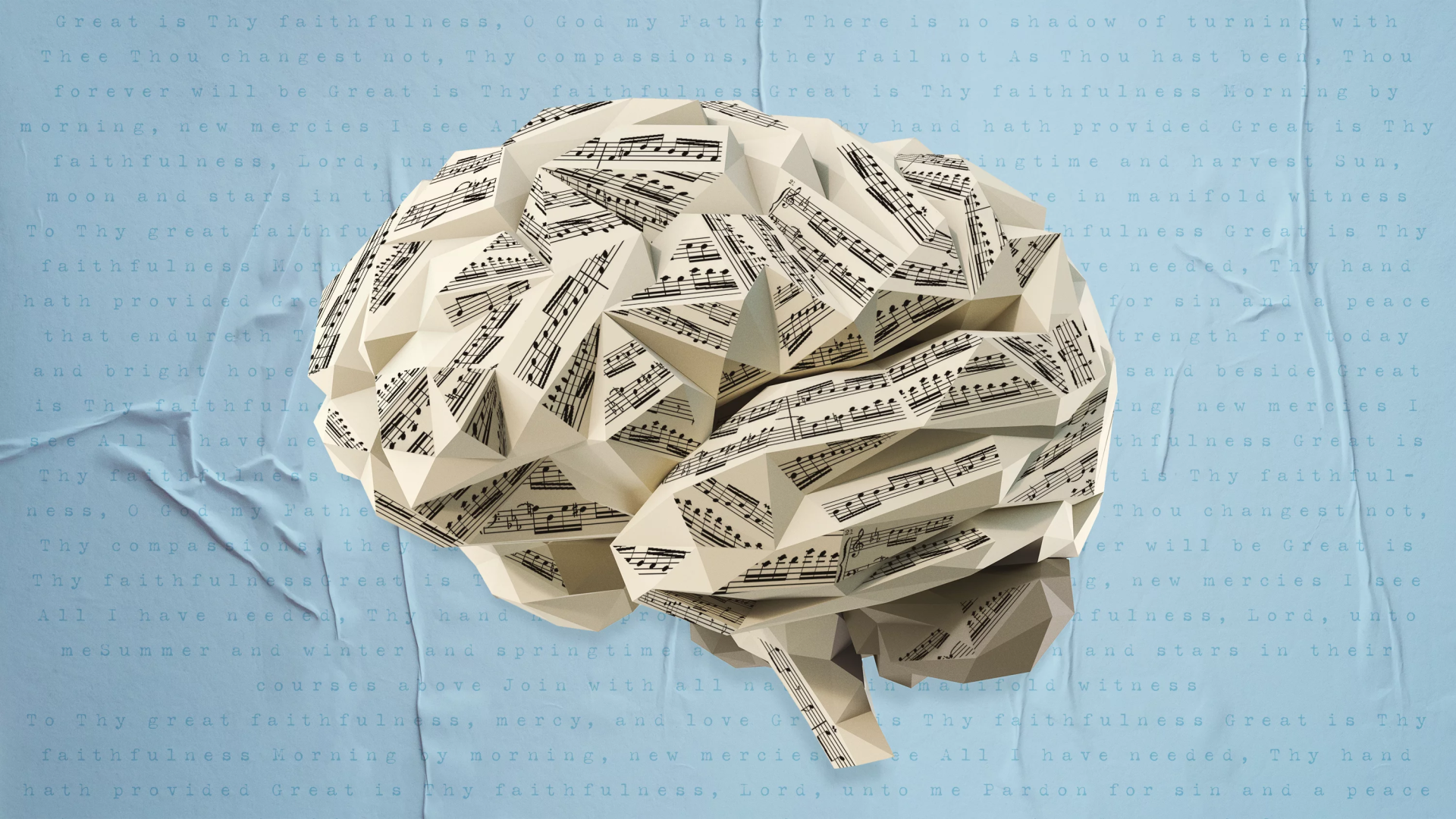Untuk waktu yang lama, saya tidak pernah benar-benar memahami Kenaikan Yesus.
Bagi saya, pertanyaan para murid dalam Kisah Para Rasul 1:6 tampak sangat masuk akal. Mengapa Yesus harus pergi? Mengapa tidak membawa kepenuhan Kerajaan Allah saat itu juga, dan mulai membenahi semuanya? Jika Yesus masih ada di dunia, bukankah itu akan menjadi aset yang besar bagi pelayanan kita di dalam misi dan apologetika?
Sebagaimana yang ditunjukkannya, Kenaikan Yesus mempertontonkan langsung keraguan tergelap para skeptis tentang narasi Injil. Betapa nyamannya, Mesias yang telah bangkit itu menghilang tanpa menunjukkan diri-Nya kepada siapa pun selain kepada teman-teman dan keluarga-Nya!
Meski demikian, Alkitab dengan gigih menolak untuk setuju terhadap sensibilitas saya. Bukannya memperlakukan Kenaikan Yesus sebagai sebuah kepergian yang janggal untuk menjelaskan mengapa Yesus tidak ada lagi, Kitab Suci justru membicarakannya sebagai bagian penting dari rencana Allah. Hal itu bukan hanya perlu, melainkan bahkan para murid menyebutnya sebagai sebuah bukti yang primer dari identitas kemesiasan Yesus.
Alih-alih mencoba menjelaskan ketidakhadiran-Nya, mereka malah menggembar-gemborkannya dengan penuh semangat. Kenaikan Yesus berdiri pada pijakan yang sama dengan Penyaliban dan Kebangkitan dalam pernyataan Injil yang paling awal (Kis. 2:33–36; 3:18–21; 5:30–31).
Bahkan Yesus sendiri menghubungkan Kenaikan-Nya dengan karya kematian dan kebangkitan-Nya. Ketika Maria Magdalena melihat Dia di taman setelah kebangkitan-Nya, Dia tidak berjalan-jalan saja, menikmati kenyataan bahwa semuanya telah tercapai. Tidak, Dia adalah seorang pria yang sedang dalam misi, dan masih ada yang lain: “Janganlah engkau memegang Aku, sebab Aku belum pergi kepada Bapa” (Yoh. 20:17).
Namun dalam pengalaman saya di gereja-gereja Injili, saya jarang mendengar Kenaikan Yesus dikhotbahkan dengan penekanan yang hampir sama dengan Salib atau kubur yang kosong.
Dalam mencoba menjelaskan Kenaikan Yesus, para teolog dengan cepat menunjukkan hal-hal yang dilakukan Yesus sesudahnya: ini adalah pintu gerbang menuju tugas keimaman-Nya untuk bersyafaat, suatu prasyarat untuk mengirim Roh Kudus-Nya, dan permulaan pemerintahan surgawi-Nya. Itu semua benar.
Namun, saya tidak pernah mengerti mengapa Yesus harus pergi untuk melakukan hal-hal itu. Bersyafaat, mencurahkan Roh, dan bahkan memerintah—semua ini dapat diwujudkan dalam pelayanan Mesias yang mulia dan benar itu di dunia. Jadi kenapa Dia harus pergi?
Teologi biblika menawarkan kepada kita jawaban yang sangat jelas untuk pertanyaan itu, jawaban yang memungkinkan kita untuk melihat Kenaikan Yesus dalam konteks yang tepat. Kenaikan Yesus bukanlah tindakan menghilang yang janggal yang dilakukan Yesus di bagian akhir—seperti seorang pesulap yang menyelesaikan pertunjukannya dalam kepulan asap—tetapi peristiwa ini merupakan batu penjuru dari semua yang telah Ia lakukan dalam kesengsaraan-Nya.
Kenaikan Yesus merupakan tindakan kemenangan yang memahkotai pelayanan Kerajaan dan keimaman Mesias: di mana keturunan Daud naik takhta untuk memerintah, dan sang imam besar agung menyelesaikan persembahan kurban pendamaian.
Pertama, pertimbangkan dari sisi kerajaan. Kenaikan Yesus tampaknya merupakan penggenapan yang tepat dari visi kenabian di Daniel 7:13-14. Dalam visi tersebut, Sang Anak Manusia, dikelilingi awan, mendekati takhta Yang Lanjut Usianya dan diberikan kekuasaan kerajaan yang kekal. Perhatikan bahwa nubuatan itu tidak menunjukkan pemerintahan Mesias dimulai dengan pemerintahan duniawi, melainkan secara khusus dimulai dengan pemerintahan surgawi.
Jika Yesus tetap tinggal di bumi dan mencoba untuk mengklaim kedudukan-Nya sebagai raja, maka Ia tidak mungkin adalah Mesias—karena Anak Manusia yang sejati telah dinubuatkan akan naik ke hadirat Allah, untuk diberikan pemerintahan-Nya.
Peristiwa Kenaikan adalah penobatan kemenangan raja mesianik. Yesus telah melakukan apa yang diharapkan untuk dilakukan oleh raja-raja yang baik di dunia zaman kuno: Dia telah menyelamatkan umat-Nya dari musuh-musuh mereka. Ia telah mengalahkan kuasa dosa, Iblis, dan maut, dan kini Dia naik ke atas takhta—sama seperti para raja keturunan Daud pada zaman dahulu yang kembali ke Yerusalem setelah kampanye militer yang sukses.
Setelah menyelesaikan tindakan rajawi ini, Yesus mendekati Yang Lanjut Usianya dan dimahkotai dengan kemegahan dan kehormatan. Dan meskipun kita masih menantikan kedatangan-Nya kembali, bersama dengan manifestasi yang penuh dan final dari pemerintahan-Nya, namun pemerintahan itu telah dimulai.
Sekarang Ia berada di atas takhta, duduk di sebelah kanan Bapa, dan tanda-tanda yang diharapkan dari zaman mesianik sedang digenapi di depan mata kita: Roh telah dicurahkan dan bangsa-bangsa mulai mengarahkan hati mereka pada penyembahan kepada Allah Israel.
Sederet gambaran alkitabiah yang lebih menarik bahkan menghubungkan Kenaikan Yesus dengan karya keimaman Sang Mesias. Orang Kristen mula-mula menganggap kematian Yesus di kayu salib sebagai pengorbanan untuk pendamaian (Rm. 3:25), suatu tindakan di mana dosa-dosa kita sepenuhnya dan akhirnya diampuni.
Namun, jika dilihat dari konteks budaya bait suci Israel, hal ini akan mengejutkan sebagian besar orang percaya Yahudi sebagai sesuatu yang tidak lengkap untuk mengatakan bahwa Salib adalah satu-satunya yang ada untuk ritual pengorbanan Yesus. Seperti yang diketahui siapa pun juga di zaman dunia kuno, pendosa yang bertobat membutuhkan langkah lebih lanjut dalam ritual pendamaian: kurban untuk dibunuh dan imam besar untuk membawa darah korban ke hadirat Allah.
Paralel yang paling jelas adalah ritual tahunan Hari Pendamaian, ketika kurban penebus dosa umat dibunuh di altar besar di luar pintu bait suci. Tetapi itu hanya bagian pertama dari ritual tersebut. Bagi telinga orang Yahudi, klaim bahwa hanya Penyaliban sajalah yang merupakan ritual kurban pendamaian akan terdengar seperti mengatakan bahwa kurban telah disembelih di atas mezbah dan tidak lebih dari itu.
Bagaimana dengan langkah selanjutnya dari ritual tersebut? Sang imam besar harus mengambil darah kurban itu dan menaiki tangga bait suci—untuk masuk ke tempat kudus Tuhan yang dikelilingi dengan asap ukupan yang mengepul (Im. 16:11-13).
Imam besar akan naik memasuki kepulan asap tersebut, menghilang dari pandangan orang banyak yang menyaksikan di pelataran bait suci, dan kemudian ia melanjutkan masuk ke Ruang Mahakudus. Di sana, di hadapan Tuhan, sang imam besar akan mempersembahkan darah korban, menyelesaikan ritual penebusan dosa dan bersyafaat bagi umat Allah. Kemudian ia akan muncul, turun kembali melewati kepulan asap ukupan itu, dengan cara yang sama seperti ia masuk dengan dilihat oleh orang banyak, dan membawa jaminan keselamatan kembali kepada umat Allah.
Inilah tepatnya yang terjadi dalam kenaikan Yesus ke surga, sebagaimana yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani. Ibrani 6–10 melukiskan gambaran peristiwa yang terjadi ketika Yesus masuk ke hadirat Allah, yang merupakan penggambaran pada Hari Pendamaian untuk memperlihatkan Yesus, baik sebagai kurban maupun sebagai yang mempersembahkan kurban. Sementara Ruang Mahakudus hanya menjadi representasi duniawi dari realitas surgawi, Yesus memasuki inti realitas itu—ke hadirat Bapa.
Implikasi teologisnya di sini adalah bahwa Kenaikan Yesus adalah langkah penting berikutnya dalam ritual pendamaian setelah Salib. Ini tidak menyiratkan kekurangan apa pun pada karya keselamatan yang Yesus lakukan di kayu salib—ini hanya menyiratkan bahwa pengorbanan yang telah selesai itu memang harus selalu diikuti dengan langkah lain dalam proses tersebut, yaitu membawa pengorbanan-Nya ke dalam Ruang Mahakudus yang sejati.
Bukan hanya orang Ibrani saja yang melukiskan gambaran ini. Jika Anda tahu apa yang Anda cari, Anda dapat melihat simetri keimaman di sebagian besar penggambaran tentang Kenaikan Yesus. Kenaikan Yesus didahului dengan periode 40 hari (Kis. 1:3), sama seperti Hari Pendamaian dalam tradisi kerabian Yahudi.
Sebelum Ia naik ke surga, Yesus mengangkat tangan-Nya untuk memberkati para murid-Nya, dan kemudian naik ke hadirat Allah (Luk. 24:50–51)—yang merupakan rangkaian tindakan yang sama yang dilakukan Harun sebelum memasuki tabernakel untuk menyelesaikan ritual pengorbanan agung yang pertama (Im. 9:22-23).
Penyebutan secara khusus tentang awan di mana Yesus menghilang (Kis. 1:9) menggemakan baik nubuatan Daniel tentang Anak Manusia maupun gambaran visual pada Hari Pendamaian. Jika Yesus adalah Imam Besar Agung yang mempersembahkan kurban di tabernakel surgawi, maka Ia harus naik ke surga untuk melakukan peran tersebut.
Perspektif ini menambahkan lapisan makna yang baru pada periode sejarah kita saat ini. Ritual Hari Pendamaian bukan hanya soal naik ke bait suci dan hadirat Tuhan, tetapi juga tentang datang kembali lagi. Karena itu, masa ketidakhadiran Yesus saat ini merupakan periode pelayanan imamat-Nya yang aktif, seiring Ia terus menjadi perantara bagi kita di hadirat Allah Bapa.
Demikian pula, janji kedatangan Yesus yang kedua kali bukanlah suatu peristiwa masa depan yang berdiri sendiri, melainkan peristiwa puncak yang telah lama dinantikan atas segala sesuatu yang telah Ia lakukan, seperti yang digambarkan dalam ritual keimaman zaman kuno (Ibr. 9:24-28 ). Dengan demikian, narasi menghilang-dan-datang kembali dari peristiwa Kenaikan dan Kedatangan Yesus yang kedua kali tidak lagi menjadi sesuatu yang janggal atau mengejutkan. Sebaliknya, dalam terang Kitab Suci, justru itulah yang diharapkan untuk dilakukan oleh Mesias.
Agar Yesus menjadi Raja mesianik sejati—yang dinubuatkan datang untuk mengalahkan musuh umat manusia dan kembali untuk mengklaim takhta-Nya seperti yang dijelaskan dalam Daniel 7—maka Ia harus naik. Agar Yesus menjadi Imam Besar Agung, yang digambarkan dalam ritual bait suci Israel, ia harus menyelesaikan ritual tersebut dengan membawa kurban-Nya ke hadirat Allah.
Kenaikan Yesus bukan sekadar catatan kaki bagi narasi Injil; peristiwa ini bukanlah ketidakhadiran yang janggal untuk dijelaskan. Kenaikan Yesus tidak kurang klimaks dari kesengsaraan Mesias—dan ini merupakan persiapan untuk akhir dari karya penebusan-Nya yang agung.
Matthew Burden adalah kandidat PhD dalam teologi dan penulis Who We Were Meant to Be dan Wings over the Wall. Ia menggembalakan sebuah gereja di Maine bagian timur, di mana dia tinggal bersama istri dan tiga anaknya.
Diterjemahkan oleh: Maria Fennita S.
–