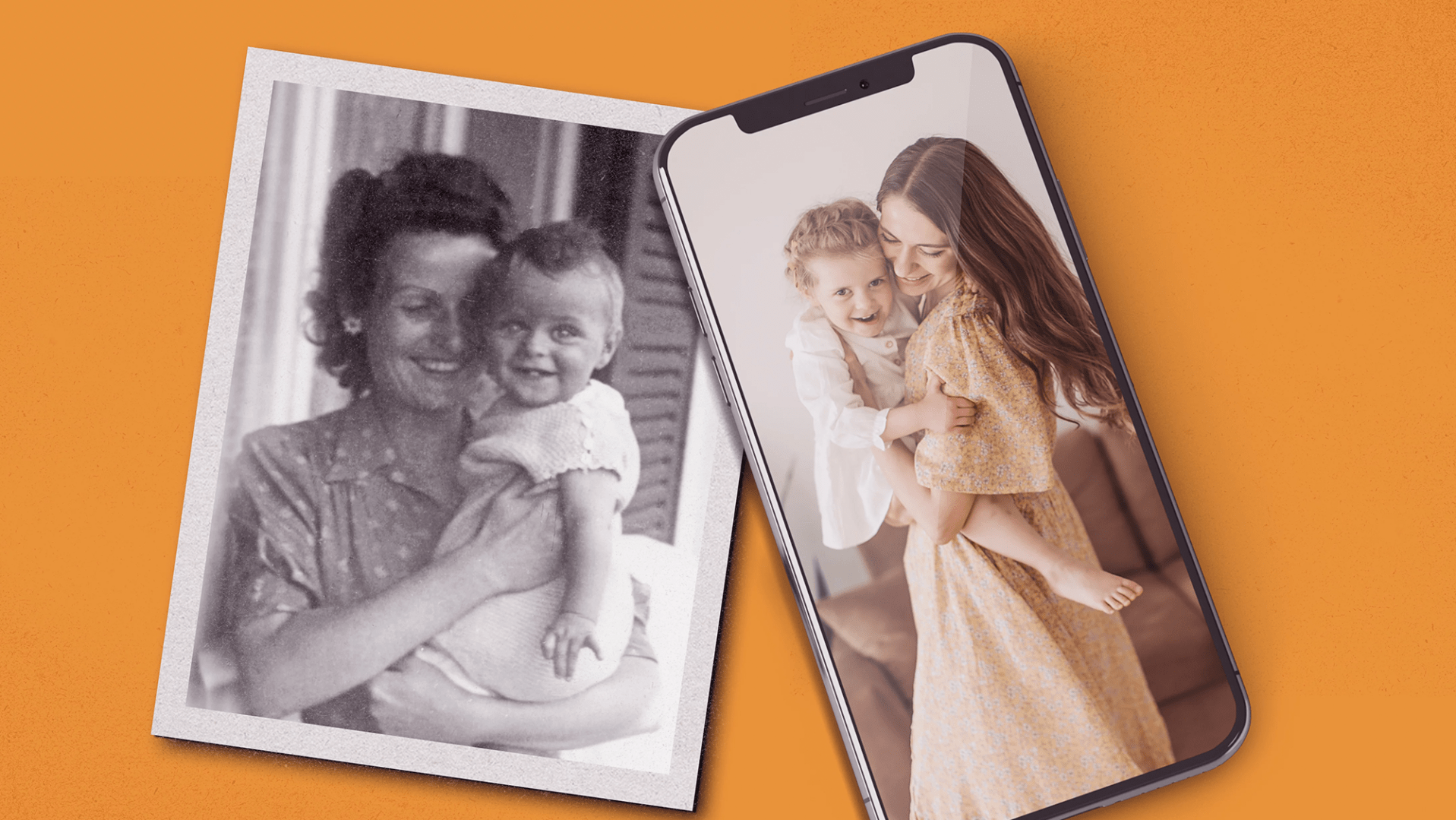Sejak awal Mei, lebih dari 180 orang tewas di negara bagian Manipur, India timur laut. Sebagian besar para korban adalah orang Kristen dari suku minoritas Kuki-Zo dan, akibatnya, ribuan orang dari komunitas ini telah melarikan diri dari kekerasan itu untuk berlindung di wilayah lain negara bagian tersebut atau India.
Manipur adalah negara bagian yang tertutup bukit dengan lembah subur di tengahnya. Orang Meitei menduduki distrik-distrik di lembah, sedangkan distrik perbukitan adalah rumah leluhur dari berbagai komunitas suku, sebelum pemerintahan kolonial Inggris. Baik distrik perbukitan maupun masyarakat suku dilindungi di bawah undang-undang khusus Konstitusi India yang membatasi kepemilikan tanah di wilayah suku.
Konflik yang baru-baru ini terjadi dimulai setelah adanya protes secara damai dari komunitas suku terhadap upaya orang-orang Meitei untuk menjadi “suku terjadwal,” atau suku asli yang dilindungi pemerintah (di mana hal ini juga akan memberi mereka akses ke tanah perbukitan tersebut). Protes itu ditanggapi dengan kekerasan oleh massa Meitei yang radikal. Kekerasan lebih lanjut dipicu oleh ledakan kebohongan yang disebarkan konon oleh komunitas Meitei sendiri, yang dengan cepat menyebar ke ibu kota negara bagian, Imphal. Massa yang kejam mulai merampok rumah-rumah suku, gereja, institusi pendidikan, dan rumah sakit, dan menyerang penduduk, termasuk wanita dan anak-anak.
Saya seorang pendeta di Evangelical Baptist Convention, dan berikut ini adalah kisah salah satu pendeta kami di Imphal yang berbagi dengan saya pengalamannya ketika kekerasan pertama kali terjadi.
-Chinkhengoupau Buansing
Catatan: Artikel ini menyertakan penyebutan peristiwa kekerasan.
Sore hari tanggal 3 Mei 2023, kami menerima berita tentang bentrokan antara masyarakat suku dan orang Meitei di sebuah desa sekitar 60 kilometer (sekitar 37 mil) di luar Imphal, kota tempat kami tinggal. Kami terkejut, tetapi kami tidak menyangka kekerasan akan meningkat begitu cepat. Sebaliknya, seperti Rabu malam lainnya, kami pergi ke gereja, di mana kami secara teratur berkumpul untuk berdoa bagi para misionaris kami dan ladang misi mereka.
Sekitar pukul 20.30, setelah kebaktian selesai, kami mendengar laporan bahwa beberapa gereja di Imphal telah dibakar. Ada dua tempat tinggal di dalam kompleks gereja kami—milik saya dan penjaga gereja. Kami segera mengumpulkan keluarga kami dan pindah dari sana ke tempat yang kami pikir akan menjadi tempat yang lebih aman. Namun tak lama kemudian kami mendengar massa berteriak dan rumah-rumah dibakar di luar. Kami menghabiskan malam dengan ketakutan bahwa mereka akan menemukan tempat kami bersembunyi.
Keesokan paginya, kami kembali bersama keluarga ke tempat tinggal kami di kompleks gereja dan sarapan. Namun pada pukul 10 pagi, kami mendengar orang-orang berteriak-teriak dan menghancurkan rumah lagi. Pada saat itu, kebanyakan orang suku di daerah kami telah meninggalkan rumah mereka. Beberapa sudah kehilangan nyawa mereka di tangan massa yang haus darah.
Kali ini kami memutuskan untuk menuju ke rumah salah satu anggota gereja kami, seorang pejabat terpilih dari majelis legislatif negara bagian (yang kami sebut “MLA”), berharap pasukan keamanan di sana akan melindungi kami. Akan tetapi di rumah MLA, kami mendapat kabar bahwa dia bahkan hampir dipukuli sampai mati.
Menyadari bahwa kami tidak akan menemukan keamanan di sana, kami berlari menuju kamp paramiliter terdekat—salah satu dari sekian banyak kamp di Imphal karena banyaknya kelompok pemberontak. Dalam perjalanan, kami melihat rumah dan mobil orang-orang suku yang Kristen dibakar dan dijarah, tidak berbeda dengan yang kami lihat terjadi di Ukraina. Belakangan kami menyadari bahwa rumah-rumah dan bahkan kantor-kantor pemerintahan tempat tinggal orang-orang suku telah ditandai dengan cat oleh komunitas Meitei beberapa bulan sebelum kekerasan meletus.
Beberapa dari mereka yang melarikan diri mengatakan kepada saya bahwa mereka menyaksikan seorang ibu dan anak laki-laki dalam perjalanan mereka menuju kamp yang sama, ditarik dari mobil mereka dan dibacok sampai mati. Mereka yang berada di depan tidak bisa menolong mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan neraka bermain di depan mata mereka.
Bahkan setelah kami tiba di kamp, gerombolan massa di luar terus mengganggu kami. Selama tujuh hari berikutnya, massa Meitei berkumpul di sekitar kamp, mengancam akan masuk dan membakar semuanya. Anak saya yang berusia tiga tahun sangat ketakutan sehingga dia tidak bergerak, bahkan ketika dia melihat nyamuk menggigit tangannya. Saya ingat seorang anggota gereja tidak dapat berbicara selama berhari-hari karena dia melihat seorang rekan Kristen dibacok sampai mati.
Saya kemudian diberi tahu bahwa ada sekitar 7.000 orang suku yang Kristen di kamp itu. Makanan harus dijatah dan bahkan kemudian, tidak cukup untuk kami semua. Mereka mulai menyajikan makan malam pada jam 4 sore dan kelompok terakhir akan mendapatkan makan malam mereka pada jam 10 malam. Piring dan sendok langka, dan beberapa dari kami harus makan dari kantong plastik. Saya percaya tidak ada dari kami yang mandi dengan layak selama kami tinggal.
Di tengah kengerian ini, selama kami tinggal di kamp, kami mengatur pertemuan doa dan mendorong satu sama lain untuk tetap kuat. Denominasi tidak memiliki arti di dalam kamp—kami semua adalah satu di bawah naungan Kristus.
Saya berharap saudara saudari kita yang Kristen di seluruh dunia setidaknya akan melihat sekilas situasi kami. Kami telah kehilangan banyak saudara saudari kami yang Kristen. Mereka ditarik keluar dari rumah mereka—ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dilempari batu sampai mati, dan ada yang dibiarkan mati di jalanan.
Saya dan banyak orang di komunitas kami percaya bahwa kami adalah korban dari upaya genosida yang disponsori negara untuk memusnahkan komunitas suku yang Kristen di Manipur. Kami diburu bukan karena kami adalah musuh negara atau karena keberadaan kami mengancam orang Meitei, tetapi karena mereka menginginkan lahan kepunyaan kami yang telah kami miliki selama beberapa generasi. (Ternyata tanah ini memiliki banyak mineral berharga). Sulit bagi saya untuk melihat kemungkinan kami hidup bersama dengan orang-orang lembah. Mereka telah menjelaskan bahwa mereka tidak ingin tinggal bersama kami. Garis telah ditarik dengan jelas dan pemisahan tampaknya menjadi satu-satunya pilihan logis bagi kami, jika kami ingin bertahan dan berkembang sebagai sebuah komunitas. Kami akan berdiri tegak sebagai orang Kristen dan hidup atau mati sebagai orang Kristen.
Waktu untuk bertobat?
Meskipun saya seorang pendeta, saya mengakui bahwa kadang-kadang saya berdoa agar para penindas kami dihancurkan. Saya senang ketika mendengar berita tentang para penindas ini ditembak mati.
Namun, seiring dengan saya berdoa tentang hal ini, saya dapat dengan yakin mengatakan bahwa saya tidak lagi menyimpan dendam ini. Keadilan akan ditegakkan dengan cara yang dianggap terbaik oleh Allah. Alkitab memberi tahu kita bahwa pembalasan adalah hak Allah (Rm. 12:19) dan saya tidak akan mengambil jalan lain.
Untuk itu, saya tidak terlalu peduli terhadap para penindas seperti halnya saya peduli terhadap anggota gereja saya. Saya telah menyaksikan iman jemaat gereja saya yang tak tergoyahkan kepada Yesus Kristus. Saya juga telah menyaksikan berbagai cara di mana Ia telah memimpin mereka melewati pencobaan berat ini. Akan tetapi saya juga yakin bahwa Tuhan meminta kami untuk mengubah jalan kami.
Sayangnya, di Manipur, orang-orang suku yang Kristen masih berjuang keras untuk mengutamakan integritas. Kami belum melindungi pemilu yang adil dan bebas di komunitas kami. Tidak dapat disangkali bahwa beberapa bukit kami dipenuhi dengan perkebunan opium dan bahkan beberapa dari kami menjadi pengedar narkoba.
Kami seharusnya tidak pernah memilih BJP, sebuah partai yang secara rutin memprioritaskan umat Hindu dengan mengorbankan agama lain, untuk memimpin negara kami. Akan tetapi karena ketergantungan negara bagian kami pada dana federal, dan hubungan dekat BJP Manipur dengan pemerintah nasional, maka kami mendukung mereka, meskipun sudah sangat jelas kami seharusnya tidak melakukannya.
Kami adalah komunitas Kristen dan seharusnya hidup seperti itu. Namun, sering kali kami memilih untuk mengabaikan Yesus dan lebih memilih untuk berteman dengan dunia.
Yang perlu kami lakukan adalah memandang kepada Bapa di surga, merendahkan diri kami di hadapan-Nya, mengubah apa yang perlu diubah, dan menantikan Dia. Seperti yang dikatakan 2 Tawarikh 7:14, “dan umat-Ku, yang atasnya nama-Ku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari surga, dan akan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka.” Saya merasa bahwa perikop ini paling relevan bagi kami saat ini.
Saya percaya bahwa Tuhan ingin kami bertobat dari semua cara di mana kami telah berbuat salah dan menyimpang dari jalan-Nya. Saya tidak menyalahkan komunitas kami dengan mengatakan ini. Sebaliknya, saya ingin kami, komunitas suku yang Kristen, keluar dari kesulitan ini dengan lebih kuat dan lebih bahagia di dalam Kristus.
Bait-bait Allah
Setelah beberapa hari di dalam kamp, sang komandan memberi tahu kami bahwa dia akan mengatur evakuasi untuk kami ke bandara. Saya mulai berhubungan dengan anggota gereja saya—beberapa dari kami berada di kamp yang sama, sementara yang lain melarikan diri ke kamp yang berbeda.
Setelah tiket penerbangan diatur untuk mereka yang berencana terbang keluar dari Manipur, saya pun memesan tiket untuk saya dan keluarga. Saat ini, sebagian besar dari kami telah menemukan rumah baru, sementara sebagian dari kami masih tinggal di dalam kamp-kamp yang dikelola oleh organisasi filantropi kesukuan.
Saya terus terkagum-kagum dengan kasih karunia dan pemeliharaan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Beberapa bulan yang lalu, kami melarikan diri demi hidup kami. Kami kehilangan semua harta benda kami dan beberapa dari kami bahkan kehilangan orang yang kami kasihi. Namun di sinilah kami sekarang, masih memuji Tuhan dan masih berharap untuk masa depan yang lebih baik. Kami telah kehilangan banyak, tetapi kami belum kehilangan semuanya.
Setahu saya, saat ini hanya ada sedikit gedung gereja yang masih berdiri di Imphal. Gereja kami masih berdiri, meskipun orang Meitei telah menjarahnya, mengubah bangunan menjadi pusat komunitas dan tempat tinggal pendeta menjadi kuil. Mereka telah memindahkan salib dari gedung gereja dan memasang bendera mereka sebagai gantinya.
Namun perbuatan yang membuat mereka merasa menang adalah perbuatan yang membuat kita umat kristiani menyadari bahwa kita tidak akan pernah bisa dikalahkan. Mereka menghancurkan bangunan-bangunan buatan manusia dan mengibarkan bendera mereka di atas bangunan-bangunan yang menurut mereka melambangkan iman kita.
Namun, andai saja mereka tahu apa yang Tuhan anggap sebagai bait-Nya. Kami meninggalkan rumah kami hanya dengan pakaian yang kami kenakan. Namun di sinilah kami, bait-Nya Allah, yang tetap menyembah Dia.
Diterjemahkan oleh Mellie Cynthia.