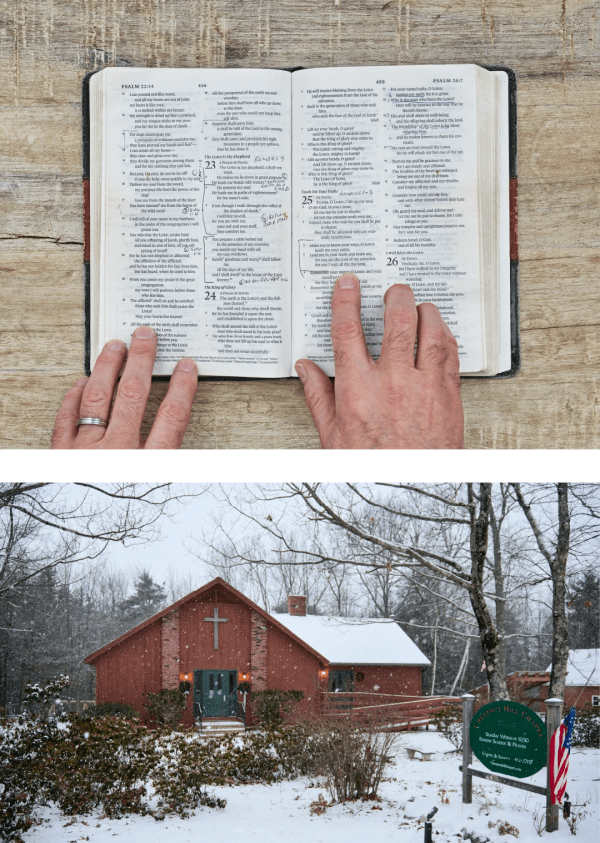Saya merasakan simpul kengerian dan ketidakpercayaan yang semakin besar dalam diri saya.
Teman di sebelah saya, pendeta muda di gereja kami, berbicara pelan di ponselnya saat taksi kami melaju melewati Sungai Han di Seoul. Air yang deras mengalir di antara tepian sungai yang hijau terawat. Melalui sambungan telepon itu, saya mendengar nada amarah si penelpon yang menggambarkan tuduhan dosa yang baru dilakukan oleh gembala kami.
Saat saya menguping, saya tidak tahu tentang pergolakan yang akan terjadi di masa mendatang: Ternyata beberapa bulan kemudian kami mengalami perpecahan gereja yang penuh kekerasan, penyelidikan formal atas tuduhan perundungan, dan kematian seorang wanita muda yang terkasih.
Kisah saya mengenai luka di gereja punya banyak petunjuk, tetapi belum tentu berisi jawaban. Saya tidak yakin apakah saya telah mempelajari apa yang seharusnya saya pelajari. Duka menancapkan akar yang mendalam dan menghasilkan buah yang aneh. Ini adalah sebuah kisah bagi orang-orang biasa di gereja-gereja lain di mana penyelidikan sedang dilakukan—yaitu orang-orang yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang harus dipercaya, dan bagaimana cara untuk terus berjalan di dalam kasih.
Kisah-kisah pelecehan rohani yang paling menonjol berpusat pada para pemimpin pelayanan yang besar, jadi kita mungkin berasumsi bahwa lingkungan seperti itulah yang mendorong dinamika kekuasaan yang tidak sehat. Namun gereja saya kecil, terkadang hanya 40 orang di hari Minggu atau mencapai 100 orang pada minggu-minggu yang sibuk.
Kami adalah jemaat yang beraneka ragam, yang sebagian besar merupakan ekspatriat. Selama tiga tahun kami makan bersama, menggendong bayi satu sama lain, berduka atas kehilangan satu sama lain, dan beribadah bersama dengan penuh sukacita.
Bagaimana kami bisa berpisah begitu cepat?
Dalam gereja yang seakrab ini, konflik memecah-belah keluarga-keluarga tepat di tengah. Dalam kasus kami, tidak ada penggelapan, perselingkuhan, atau ajaran sesat; yang ada hanyalah tuduhan bahwa gembala kami menyalahgunakan kekuasaannya—dan merebut lebih banyak lagi.
Dua faksi pun terbentuk. Jemaat yang percaya pada pendeta muda dan jemaat yang percaya pada gembala. Saya memiliki teman-teman baik di kedua kelompok ini. Ketika Anda memercayai orang-orang yang mengatakan hal-hal yang berlawanan dengan yang Anda ketahui, secara emosi kita langsung merasa itu mustahil dan secara moral kita merasa ada keharusan untuk memilih salah satu pihak. Saya bertanya-tanya, Cerita siapa yang harus saya percayai? Bagaimana jika saya membuat pilihan yang salah?
Sambil berbaring dengan mata terbuka, saya menelusuri rangkaian teks di ponsel atau memutar ulang percakapan di kepala saya, saya khawatir apakah saya telah mengatakan hal yang benar. Saya merasakan tekanan yang sangat besar untuk berjalan dengan sempurna melewati sebuah situasi yang hancur.
Pada saat yang sama, saya memperoleh suatu penghiburan yang aneh karena mengetahui bahwa Allah tidak terkejut dengan kehancuran yang kita alami. Perjanjian Baru menunjukkan para pemimpin agama yang sedang berebut kekuasaan, seperti orang-orang Farisi yang bersekutu dengan pemerintah Romawi, murid-murid Yesus yang berebut posisi, dan para pemimpin gereja mula-mula yang diperingatkan untuk tidak mendominasi jemaat mereka dalam Surat-surat dari para rasul.
Meski demikian, gambaran Tuhan tentang kepemimpinan tidak terlihat seperti cambuk penindas atau tempat parkir utama bagi bos. Gambaran Tuhan tentang kepemimpinan justru terlihat seperti gembala yang memberi makan kawanan dombanya (1Ptr. 5:2). Juga terlihat seperti halnya Yesus mengikatkan handuk pelayan di pinggang-Nya ketika Dia berlutut untuk membasuh kaki para pengikut-Nya (Yoh. 13:4-5). Lalu mengapa penyalahgunaan otoritas terus terjadi di dalam pelayanan?
Beberapa bukti menunjukkan bahwa kepemimpinan menarik orang-orang yang narsistik, dan dengan menempatkan para rohaniwan dan pendeta yang dianggap lebih penting dari yang lain, kita dapat menilai, dalam kata-kata profesor dan terapis Chuck DeGroat, “kompetensi eksternal melebihi karakter Kristen.”
Para pemimpin membutuhkan saudara-saudari di sekitar mereka, yang memiliki integritas dan hubungan baik yang dapat mengatakan, “Saya mengasihimu, sobat. Jadi sekarang berhentilah melakukan hal itu,” daripada menjadi jemaat yang hanya menurut saja. Perundungan pastoral terjadi dalam sistem yang dirancang tidak hanya untuk melindungi kepemimpinan yang tidak sehat melainkan juga untuk mempromosikannya.
Gembala kami bukanlah seorang selebriti, bahkan bukan pula seorang pemimpin yang sombong. Dia datang lebih awal untuk membersihkan toilet. Namun dia dapat berbicara tanpa berpikir panjang. Dia bisa bertindak impulsif. Dia murah hati, tetapi dia juga bisa membuat keputusan sepihak. Pendeta muda kami juga sama rumitnya. Dia bisa bersikap hangat kepada saya sambil menjelek-jelekkan orang lain. Dia meneguhkan karunia-karunia jemaat. Dia bisa menjadi pembela yang gigih. Namun menurut saya, dia juga bisa menjadi manipulatif.
Banyak hal yang bertentangan bisa dimiliki oleh seseorang dalam pribadi yang sama.
Ironisnya, gereja kami juga baru-baru ini bertumbuh secara jumlah karena masuknya anggota-anggota dari gereja terdekat yang dihancurkan oleh pelecehan rohani. Secara historis, organisasi-organisasi sangat rentan terhadap konflik pada saat terjadi perubahan. Sambil kami bertumbuh secara jumlah, sistem organisasi kami tidak dapat mengimbanginya. Para sukarelawan melihat pelayanan mereka digantikan oleh staf yang dibayar. Orang-orang merasa terlantar dan diremehkan, tanpa adanya mekanisme formal untuk menyampaikan keluhan.
Keadaan menjadi semakin buruk. Pendeta muda kami, pengerja magang kami, dan sekitar separuh dari teman-teman saya tidak lagi berbicara dengan gembala kami. Mereka menuduhnya melakukan misogini, berbohong, merundung, dan bahkan meninggalkan imannya. Mereka mengatakan bahwa hal itu persis seperti kasus Mars Hill. Semua keburukannya diungkapkan secara terbuka.
Gereja induk kami pun mengirimkan komite investigasi, yang sulit untuk dipandang sebagai pihak ketiga yang netral. Kesalahan klasik lainnya pun terjadi: Kami mendengar desakan yang biasa kita dengar untuk tunduk pada otoritas dan berhenti bergosip.
Semua ini terjadi selama pandemi COVID-19, dan isolasi yang menyertainya semakin memperburuk situasi. Pada tahun 2020, kebijakan Korea Selatan melarang pertemuan sosial atau makan bersama. Kesalahpahaman yang mungkin bisa diselesaikan dengan semangkuk bibimbap, malah membusuk selama berbulan-bulan.
Keheningan yang lama membeku berubah menjadi surat terbuka, email balasan kepada semua orang, dan tuduhan yang keji: si pendeta muda sedang berkampanye untuk mendapatkan kekuasaan; si pengerja magang itu sedang memainkan peran sebagai korban; sang gembala itu adalah seorang tiran yang seksis.
Pertempuran terbuka kini berkecamuk di sekeliling kami. Setiap minggu, ada teman-teman yang meninggalkan gereja. Beberapa beralih ke gereja lain. Namun, banyak juga yang meninggalkan kekristenan sama sekali karena sudah sangat kecewa.
Dalam keadaan tak berdaya, saya bertanya kepada Tuhan apa yang bisa saya lakukan. Rasa tanggung jawab terkadang membuat saya bersemangat, tetapi terkadang membuat saya kewalahan juga. Dengan hasrat yang sungguh-sungguh untuk bisa berguna, saya terkadang lupa bahwa Tuhanlah—bukan saya—yang memegang diri kita, bahwa Roh Kudus mengasihi sang mempelai wanita jauh lebih besar daripada saya, dan Roh itu berjuang demi mempelai wanita itu dengan lebih kuat daripada yang saya bisa.
Saya pun mencari hikmat dalam Kitab Suci. Surat Paulus kepada gereja-gereja rumah di Roma menjadi landasan Firman Tuhan bagi saya. Dalam Roma 12, ada dua faksi saling memelototi satu sama lain karena jurang perbedaan. Orang-orang percaya telah terpecah-belah karena status, etnis, kebiasaan keagamaan, dan penafsiran Alkitab. Tanpa mengorbankan doktrin, Paulus memohon, menasihati, dan mengajak mereka—menggunakan segala cara yang ia ketahui—untuk kembali kepada persaudaraan dalam iman.

Saya meminta Tuhan untuk memberikan kepada saya nada kasih sayang yang sama dan kejujuran yang tak tergoyahkan seperti Paulus dalam setiap interaksi.
Saya merasa tidak bisa memproses segala sesuatunya dengan pendeta atau teman-teman gereja saya. Semua orang yang dekat dengan saya terlibat dalam penyelidikan itu atau imbasnya. Rasanya para pemimpin saya seperti berada dalam mode triase, yang hanya memusatkan perhatian pada orang-orang yang paling berperan dalam konflik tersebut. Saya membaca buku-buku, artikel, dan siniar yang ada seputar perundungan agama, tetapi semua tampaknya mengasumsikan yang terburuk, ditulis dengan warna hitam putih yang sangat jelas. Tidak ada yang mencerminkan bagian abu-abu seperti yang sedang saya alami ini.
Putus asa untuk mendapatkan kejelasan, saya merasa lega ketika menemukan terapis lewat Zoom—seseorang yang akhirnya dapat saya ajak bicara tanpa filter. Musik juga membantu. Saya sering memimpin jemaat kami menyanyikan lagu “Prophesy Your Promise”:
Saat aku hanya melihat sebagian
Aku akan menubuatkan janji-Mu…
Karena Engkau menyelesaikan apa yang Kau mulai
Aku akan memercayai-Mu dalam prosesnya.
Sungguh suatu penghiburan untuk menyanyikan seruan kepada Allah yang baik “di tengah kekacauan saya.”
Setelah mewawancarai semua orang yang terlibat dan membaca ratusan email, komite investigasi memutuskan bahwa gembala kami tidak bersalah atas pelecehan rohani.
Namun, mereka mengatakan kepada jemaat bahwa dia telah bertindak tidak dewasa dan gagal menunjukkan hati seorang gembala. Dia telah menunjukkan kelalaian dalam menangani kontrak pengerja magang, membiarkan perasaan tidak enak berlama-lama tanpa penyelesaian. Mereka memberi mandat kepadanya untuk terapi, membentuk dewan penatua, dan memberikan cuti yang dibayar untuknya dan bagi mereka yang mengajukan tuntutan.
Perpecahan tetap ada. Pengerja magang kami, pendeta komisi anak, dan pendeta muda kami akhirnya mengundurkan diri. Yang lainnya juga berhamburan keluar—sebagian memprotes ketidakadilan, sebagian hanya lelah dengan semua cobaan ini. Kami yang tetap tinggal merasa terpanggil untuk membangun kembali sesuatu yang lebih sehat, bertekad untuk menyaksikan semacam penebusan. Segala sesuatunya tampak mulai beres.
Lalu masuklah sebuah panggilan telepon.
“Jeannie,” kata sahabat saya dari gereja, berhenti sejenak untuk mengendalikan napasnya yang tersengal-sengal. “Pengerja magang kita telah terbunuh.” Larut malam sebelumnya, teman sekaligus mantan pengerja magang kami yang telah menjauh dari gereja itu sedang berjalan di seberang jalan ketika seorang pengemudi mabuk menerobos lampu merah dan menabraknya. Saudari kami telah tiada.
Wanita itu masih sangat muda, baru saja memulai pelayanan; dia sangat dicintai, namun sebagai orang asing dia sangat sendirian di negara yang bukan negaranya. Dia dengan penuh semangat memperdebatkan berbagai kebijakan, berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan pengertian, berjuang dengan penuh gairah demi sesuatu yang harus ia perjuangkan, dan akhirnya meninggalkan komunitas yang ia cintai.
Dan sekarang dia telah tiada. Bagi saya, tidak disangka bahwa begitulah akhir dari kisahnya di dunia.
Saya berharap bisa mengatakan bahwa komunitas kami bersatu dalam kesedihan kami. Namun jika Anda pernah terjerumus ke dalam tragedi komunal, Anda pasti tahu betapa setiap anggota mengalaminya secara berbeda. Kematian teman kami tidak membuat kami bersatu. Itu adalah kehancuran terakhir kami. Gereja kami telah terpecah sepenuhnya, dengan kekerasan yang masih membuat saya tercengang.
Perubahan pun terjadi secara perlahan. Sebelum kembali ke Amerika, saya melihat secercah harapan. Gembala kami, yang telah didisiplin, mengaku dan meminta maaf dari mimbar: “Saya telah menjadikan kesuksesan gereja ini sebagai identitas saya, dan saya minta maaf.”
Dewan penatua yang baru dibentuk (di mana suami saya menjadi anggotanya) membuat sebuah konstitusi dengan ketentuan untuk memberhentikan seorang pendeta. Saya dan suami mengkhotbahkan Roma 12 di hari Minggu itu saat kami mengucapkan selamat tinggal. Setelah berbulan-bulan dalam keheningan, saya dan seorang teman minum kopi bersama sambil bertatap muka dan memberikan isyarat pertama dari rekonsiliasi yang penuh air mata.
Saya tidak pernah melihat kebangkitan sepenuhnya. Beban itu terasa seperti bagian permanen dari kisah gereja saya sekarang. Saya menjadi sangat memperhatikan sikap, tanda-tanda kebencian dari staf, para pemimpin gereja yang dianggap lebih penting dari yang lain, dan komunikasi yang terasa menjilat atau tidak tulus.
Kepercayaan akan butuh waktu. Setelah menetap sementara di sebuah komunitas Kristen baru di Amerika, saya bisa merasakan diri saya menjaga jarak dengan orang-orang lain. Untuk pertama kalinya sejak masa remaja, saya tidak memimpin ibadah atau kelompok kecil.
Untuk saat ini, menampakkan diri saja sudah cukup sulit.
Saya masih bertanya-tanya apakah saya berjalan dengan baik. Apakah saya harus memilih satu sisi sungai atau sisi yang lainnya? Atau satu-satunya cara adalah menggelepar-gelepar di antara keduanya?
Seperti yang dikatakan Beth Moore dalam memoarnya, “Sepanjang hidup saya yang penuh dengan simpul-simpul, saya merindukan kewarasan dan kesederhanaan untuk mengetahui siapa yang baik dan siapa yang jahat … Namun Tuhan tetap saja menjauh dari permintaan yang sederhana ini.” Saya sendiri adalah orang yang campur aduk, agak seperti korban, tetapi seperti penjahat juga, meskipun saya percaya Roh Kudus sedang mengerjakan rasio tersebut.
Tidak ada penindas yang jahat atau korban tanpa cela dalam kisah kami. Kami harus berhenti menuntut adanya hal tersebut. Pasti ada cara yang lebih baik untuk menumbuhkan budaya yang harmoni dan kebenaran.
Penulis Scot McKnight dan Laura Barringer menjelaskan cara mengembangkan “lingkaran tov,” atau kebaikan, dengan menetapkan norma-norma pelayanan, kasih karunia, keberanian, dan kebenaran dalam bidang apa pun yang kita pengaruhi. Bagi sebagian besar dari kami, ini adalah cara untuk melangkah maju melewati masa penyelidikan atau sakit hati di gereja.
Alih-alih merapatkan barisan atau memusnahkan siapa pun yang terlibat, kami meratap. Kami berdoa. Dengan sungguh-sungguh mencari Roh Kudus, Kitab Suci, dan nasihat yang bijak, kami menyadari bahwa kami juga berpotensi untuk membuat kesalahan. Kami memperlakukan satu sama lain dengan lemah lembut, meski di bawah tekanan.
Dengan mempertimbangkan tanda-tanda bahaya yang umum dan kasih sayang yang lembut sebagai saudara, kami mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit kepada para pemimpin. Kami mengundang para ahli. Kami tetap berada di dalam situasi yang penuh ambiguitas lebih lama daripada yang nyaman.
Investigasi gereja apa pun merupakan panggilan untuk bertobat, baik secara pribadi maupun institusional. Ketika hal itu terjadi, kiranya Tuhan mengaruniakan para pemimpin yang melayani, sistem akuntabilitas, dan kebiasaan untuk rendah hati kepada kita. Semoga kita melangkah maju menuju keadilan dan perdamaian sejati.
Jeannie Whitlock adalah seorang penulis yang tinggal di pinggiran kota Chicago.
Diterjemahkan oleh George H. Santoso.
–