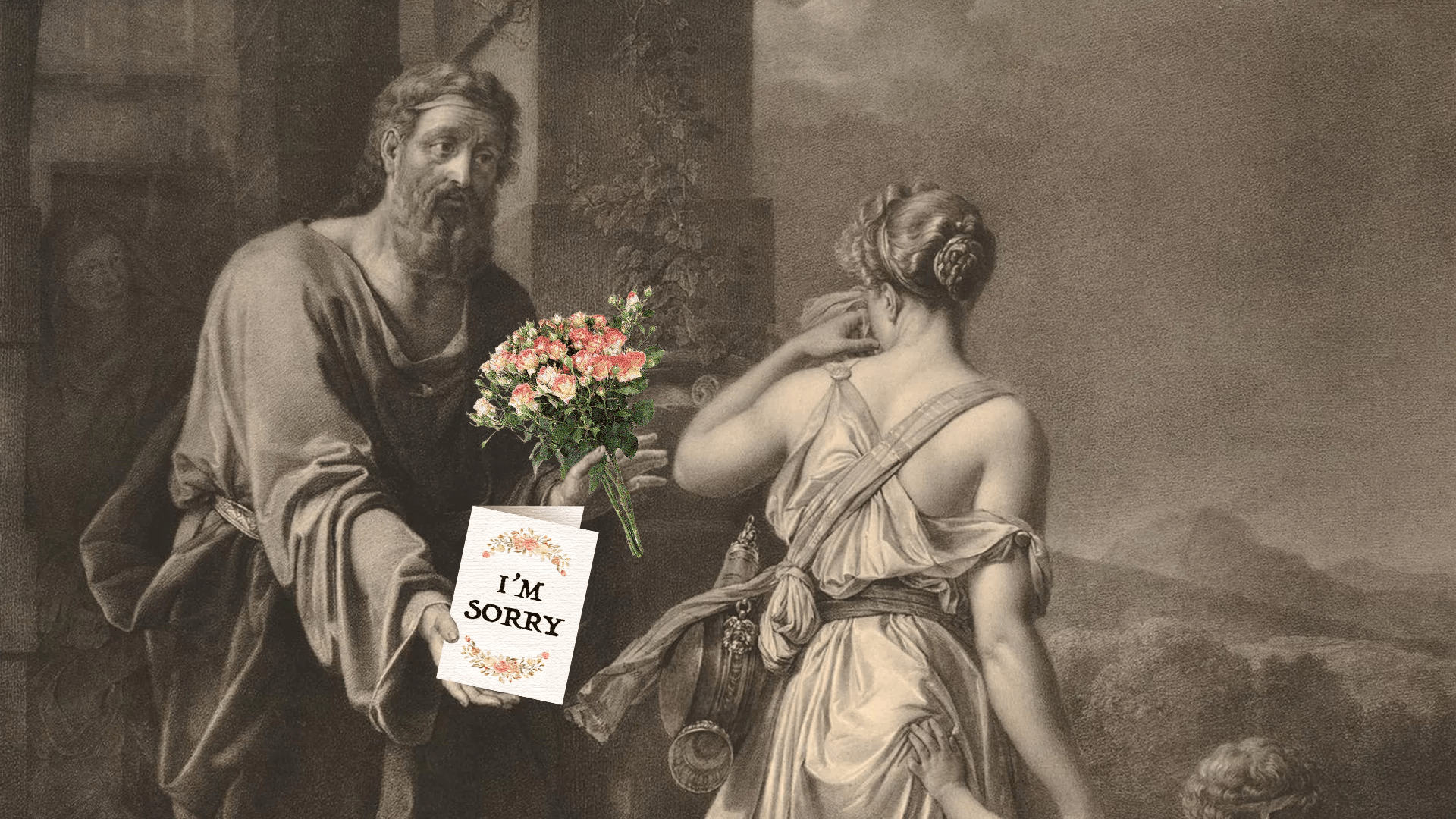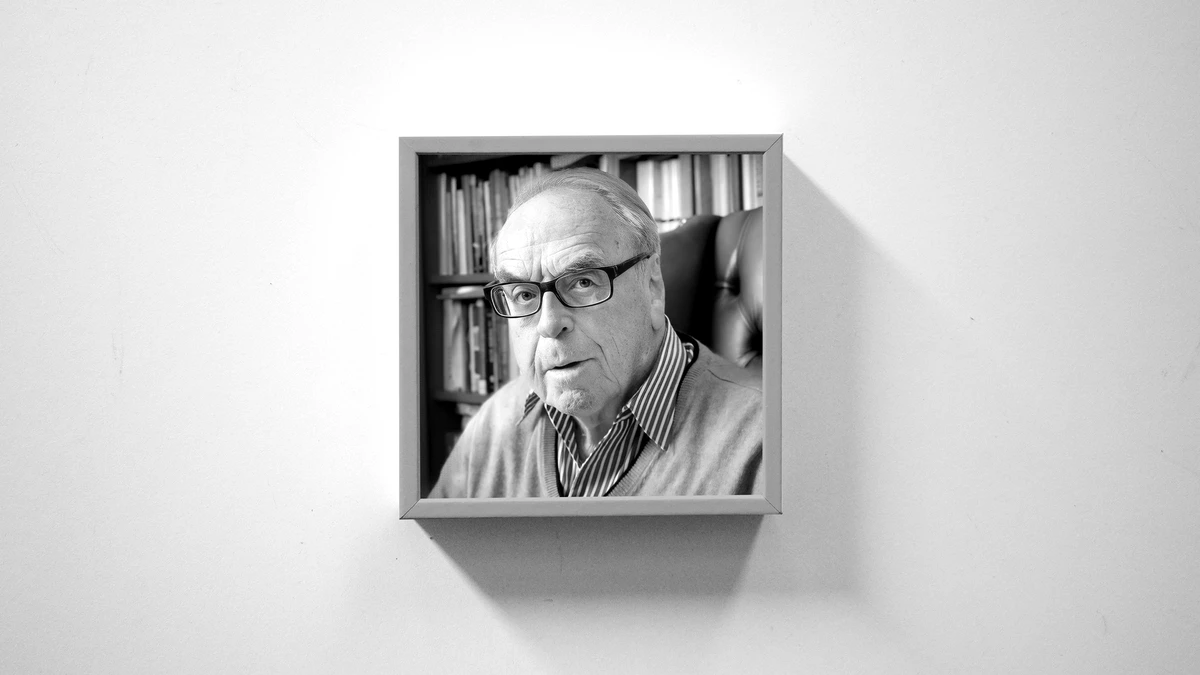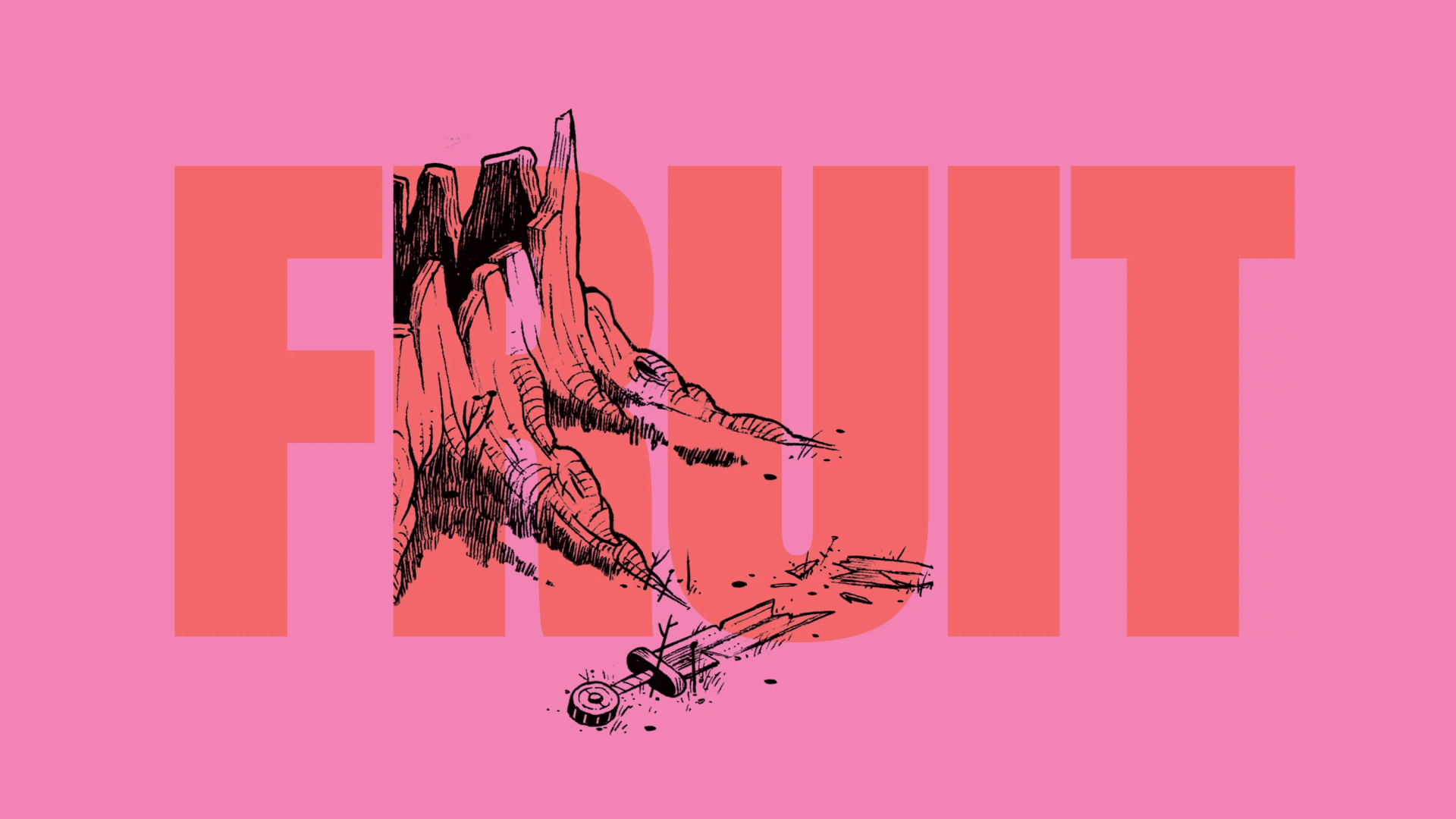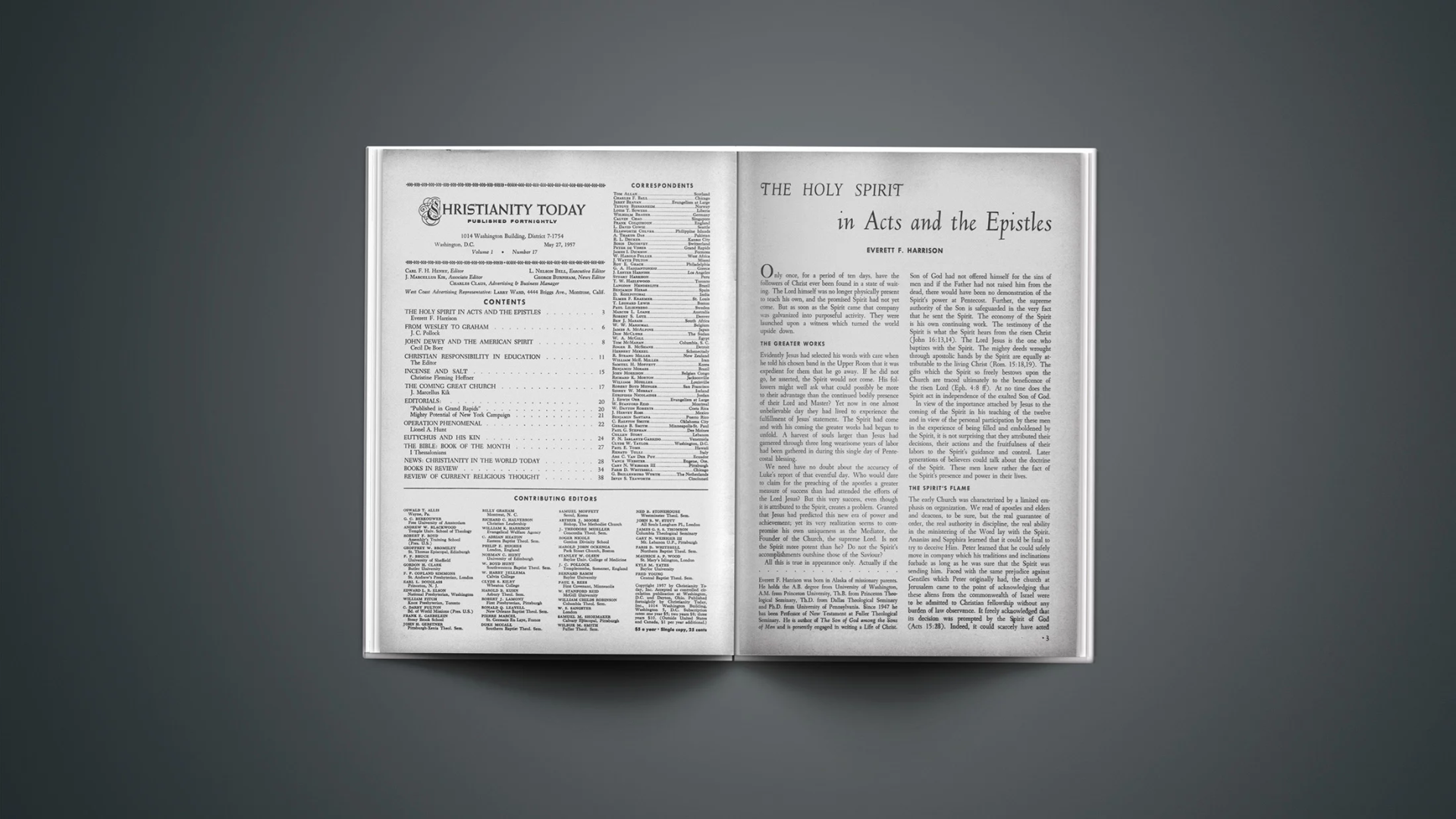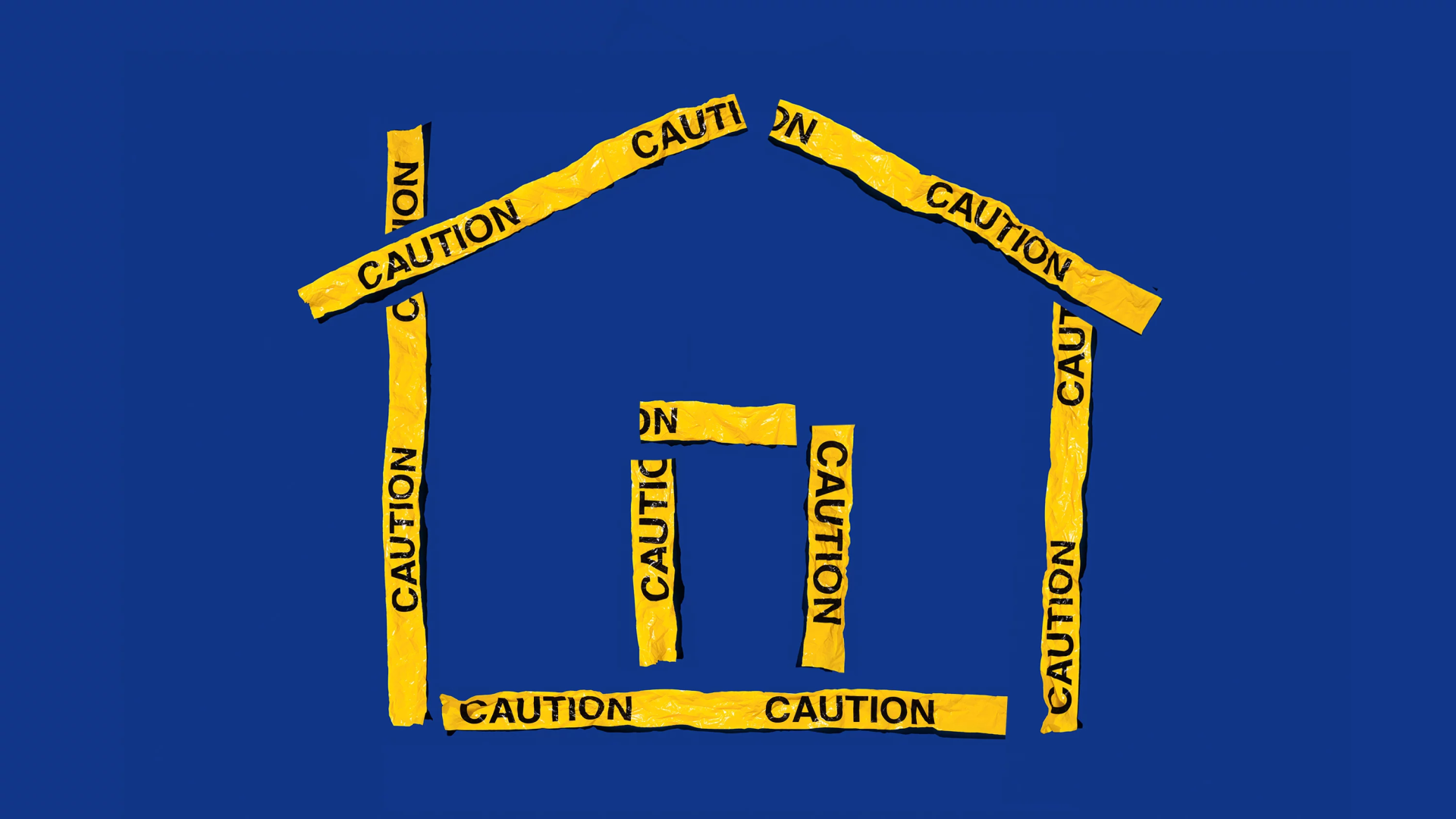Kita memerlukan teologi permintaan maaf.
Meminta maaf terdengar mudah, setidaknya dalam teori. Anda melakukan sesuatu yang salah (dosa); Anda merasa bersalah (penyesalan); Anda mengakuinya dan menerima tanggung jawab (pengakuan); Anda meminta maaf kepada orang-orang yang telah Anda sakiti, termasuk kepada Tuhan (pertobatan); dan Anda mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaikinya (restitusi).
Banyak permintaan maaf berwujud persis seperti ini. Namun sering kali permintaan maaf juga lebih rumit. Anda dapat meminta maaf tanpa mengakui kesalahan atau merasa menyesal. Mungkin saja kita merasa iba (kata 'iba' dan 'maaf' dalam bahasa Inggris sama, yaitu sorry) untuk hal-hal yang bukan merupakan kesalahan kita, seperti ketika kita mengetahui bahwa seorang teman mengidap kanker. Kita juga bisa meminta maaf tanpa berniat untuk mengganti rugi.
Dan mungkin saja—seperti yang semakin sering terjadi—bagi institusi untuk meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian anggotanya saja. Persoalan permintaan maaf ini menjadi semakin rumit ketika menyangkut dosa-dosa leluhur kita. Haruskah kita meminta maaf atas hal-hal yang terjadi sebelum kita lahir? Mengakui hal-hal tersebut? Bertobat dari hal-hal tersebut? Mengganti rugi untuk hal-hal tersebut?
Saat kita mencari jawaban dari Kitab Suci, kita menemukan sesuatu yang mengejutkan: Tidak ada seorang pun di dalam Alkitab yang benar-benar “meminta maaf” atau “mengatakan maaf” atas sesuatu. Kata Yunani apologia merujuk pada suatu jawaban atau pembelaan hukum—dari sanalah kita memperoleh kata apologetika—tetapi kata ini tidak mengandung makna merasa bersalah atau menyesal atas sesuatu.
Kata sorry yang lebih fleksibel dalam bahasa Inggris, sering kali muncul secara tidak terduga; penerjemah mungkin menggunakan kata tersebut untuk menggambarkan rasa iba putri Firaun terhadap Musa (Kel. 2:6) atau kesedihan yang dirasakan Herodes selepas memenggal kepala Yohanes Pembaptis (Mat. 14:9). Namun ini adalah ungkapan belas kasihan atau kesedihan, bukan permintaan maaf atau pertobatan.
Maka, mungkin kelihatannya Alkitab seolah-olah hanya menawarkan sedikit petunjuk untuk menyusun sebuah teologi tentang permintaan maaf. Akan tetapi, dalam banyak hal, yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih menggunakan kata-kata yang agak samar seperti maaf dan meminta maaf, Perjanjian Baru membedakan antara tiga respons yang berbeda tetapi saling tumpang tindih terhadap dosa kita—dan hal ini dapat membantu kita menguraikan apa yang terjadi ketika individu atau institusi “meminta maaf.”
Kata pertama, lupeō, artinya merasakan kesedihan, dukacita, atau rasa sakit. Ini adalah respons yang tepat atas dosa, dan sering kali merupakan langkah pertama, seperti ketika jemaat Korintus “berdukacita” dan membuat mereka bertobat (2Kor. 7:9). Namun hal ini tidak selalu menyiratkan penerimaan atas kesalahan. Herodes merasa tidak enak karena memenggal kepala Yohanes, tetapi ia tetap saja melakukannya. Bukan salah para murid bahwa Yesus akan disalibkan, tetapi mereka “sedih sekali” (Mat. 17:23).
Ini sangat berbeda dengan homologeō atau exomologeō, yang keduanya mengacu pada pengakuan yang disertai rasa bersalah, mengakui kesalahan, atau pengakuan akan sesuatu. Orang-orang “mengakui” kejahatan mereka karena khotbah Yohanes Pembaptis dan Paulus (Mat. 3:6; Kis. 19:18). Yohanes meyakinkan para pembacanya, “Jika kita mengaku dosa kita, maka [Allah] adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan” (1Yoh. 1:9). Ini jelas berbeda dengan dukacita atau penyesalan. Ini melibatkan pengakuan akan kegagalan kita, bertanggung jawab atas kegagalan tersebut, dan meminta pengampunan.
Lalu ada kata metanoeō yang kaya maknanya, yang menunjukkan suatu pola pertobatan, berbalik arah, dan perubahan pikiran serta hidup Anda. Sangat mudah untuk merasa sedih atau menyesal atas kesalahan-kesalahan kita. Banyak dari kita bahkan dengan senang hati akan mengakui kesalahan kita dan mengakuinya dengan penuh rasa bersalah, terutama atas hal-hal yang dapat diterima secara budaya. Namun Kristus memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang lebih: memutar balik, berbalik arah tujuan dan kesetiaan kita secara total, mati bagi diri sendiri dan hidup baru di dalam Dia, dengan segala perubahan perilaku yang menyertainya.
Jika pembalikan arah ini tidak menghasilkan buah yang baik, maka hal itu bukanlah pertobatan yang sejati (Mat. 3:8; 7:16-20). Namun jika pertobatan itu mengubah hidup kita—bahkan sampai pada titik di mana kita membayar ganti rugi kepada semua orang yang telah kita sakiti—maka keselamatan telah terjadi di rumah kita hari ini (Luk. 19:8-10).
Rasa duka, pengakuan dosa, dan pertobatan adalah entitas yang berbeda-beda. Namun, ketika kita melihat kenyataan dan kengerian dari dosa kita serta anugerah Allah yang menawarkan pengampunan, kita mendapati diri kita melakukan ketiga hal tersebut.
Mengikuti teladan Nehemia, kita menangis dan berkabung (Neh. 1:4). Lalu kita mengakui dengan penuh rasa bersalah dan mengakui kesalahan kita (ay. 6–7). Lalu kita berbalik arah dan taat (ay. 8–9). Bergantung pada konteksnya, kita dapat mengidentifikasikan diri kita dengan dosa-dosa leluhur kita hingga pada tingkat di mana kita sendiri juga ikut ambil bagian di dalam dosa-dosa tersebut. Dan kita mengakhirinya dengan memohon belas kasihan Allah, percaya bahwa Ia yang telah memanggil dan menebus kita akan mendengar doa kita (ay. 10–11).
Andrew Wilson adalah rohaniwan bidang pengajaran di King’s Church London dan penulis Remaking the World.
Diterjemahkan oleh Ivan K. Santoso.
–