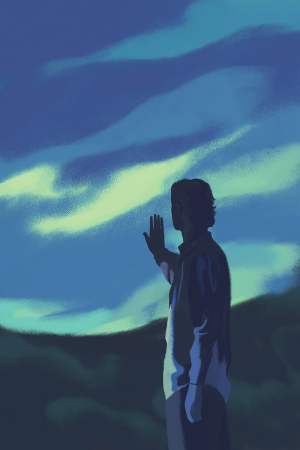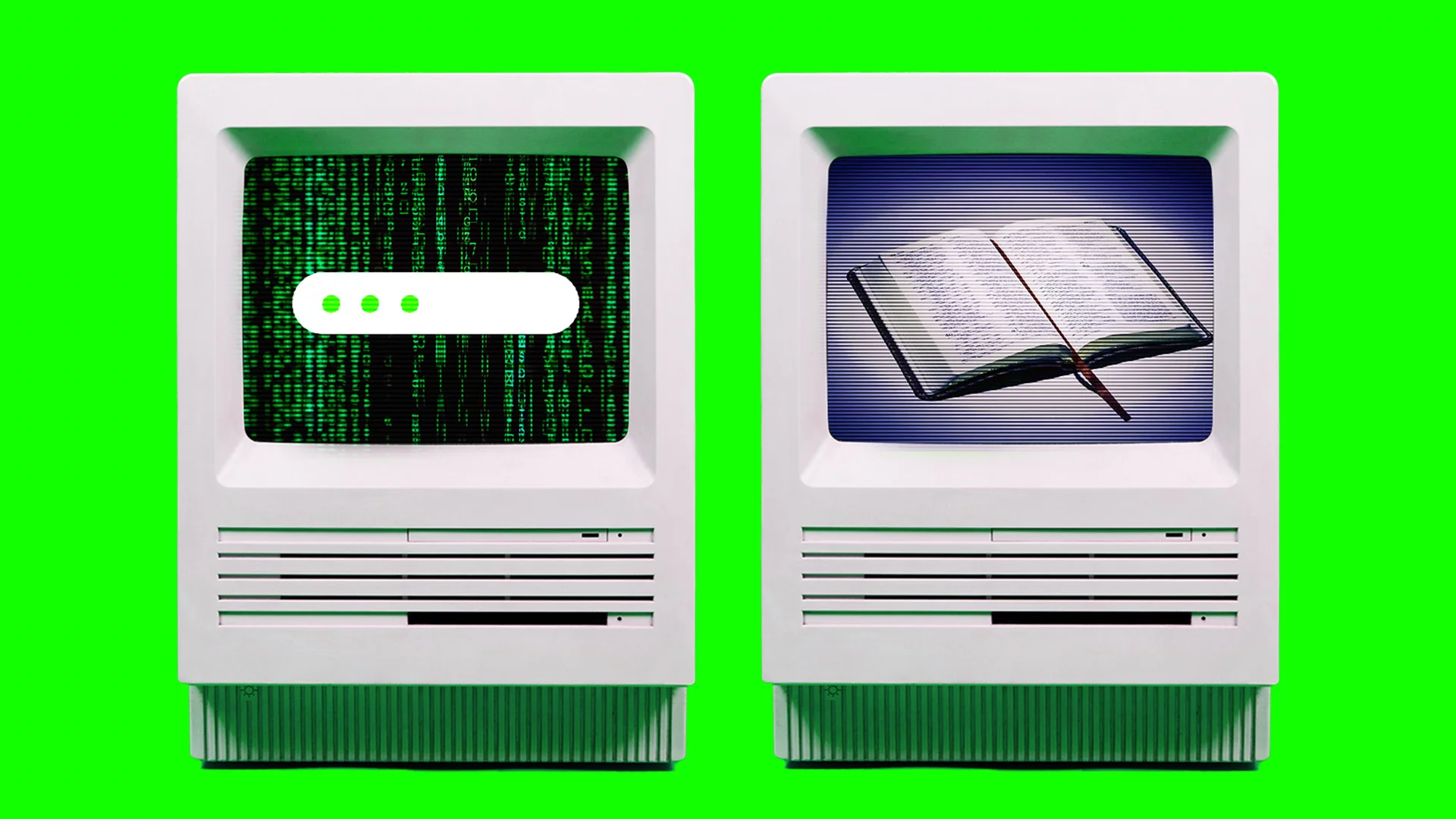Bagi orang Kristen, ketidaknyamanan dengan Perjanjian Lama bukanlah hal baru. Selama abad kedua, Marcion menghindari apa yang dilihatnya sebagai Allah Israel yang murka, alih-alih merangkul sosok Yesus dari Nazaret yang penuh kasih. Dalam buku Bearing God’s Name: Why Sinai Still Matters, profesor Perjanjian Lama dari Prairie College, Carmen Joy Imes, menemukan kembali pentingnya Hukum Tuhan bagi gereja saat ini, menolak ajaran sesat yang populer bahwa kita dapat mengabaikan Perjanjian Lama demi Perjanjian Baru. Penulis Jen Pollock Michel berbicara dengan Imes tentang dimensi pribadi dan komunal untuk masuk ke dalam perjanjian Sinai melalui Yesus, orang Israel sejati.
Saat Anda membayangkan buku ini, tingkat keakraban pada Perjanjian Lama yang seperti apa yang Anda asumsikan dari para pembaca Anda?
Saya sedang memikirkan murid-murid saya ketika saya menulisnya. Beberapa dari mereka tidak tahu apa-apa tentang Alkitab, sementara yang lain telah berada di gereja sepanjang hidup mereka. Namun bahkan di antara para pengunjung gereja yang rutin hadir, saya menemukan banyak orang buta huruf secara alkitabiah dan sebagian orang memahami Kitab Suci dengan cara yang sangat sederhana sekali. Pada umumnya, mereka membaca Perjanjian Lama secara moral, mencari pahlawan, orang-orang yang dapat mereka teladani. Akan tetapi, hal ini sangat membuat frustrasi dan mengecewakan, karena setiap orang yang mereka temui memiliki kekurangan.
Ketika para mahasiswa menghadiri di kelas Taurat yang saya ajar, saya membantu mereka menggali Kitab Suci dengan lebih mendalam. Ada beberapa penggalian yang perlu dilakukan untuk membantu mereka membaca Alkitab sebagaimana yang dimaksudkan.
Godaan untuk melepaskan diri dari Perjanjian Lama sudah ada cukup lama, tetapi adakah sesuatu yang baru tentang cara godaan itu mengekspresikan dirinya di masa kini?
Ada isu-isu klasik yang telah diperjuangkan orang-orang selama berabad-abad, tetapi ini mungkin lebih akut di zaman kita. Saat ini, kita menjumpai pertanyaan seperti: Bagaimana dengan nasib orang Kanaan? Bagaimana dengan etika seksual? Bagaimana dengan kekerasan terhadap perempuan, atau kurangnya pengakuan atas apa yang telah dilakukan perempuan? Ketika kita membuka Perjanjian Lama dan membaca kisah-kisah ini, ada hal-hal yang mengganggu kita yang mungkin tidak mengganggu orang beberapa abad yang lalu, karena secara budaya kita berada di masa yang berbeda.
Bagi sebagian orang, solusinya sudah jelas: Mari kita lepaskan saja. Jika kita ingin orang melihat Yesus, mari tinggalkan semua teks bermasalah ini dan bawa langsung ke Injil. Akan tetapi kita tidak dapat memahami Yesus tanpa Perjanjian Lama. Pendekatan saya adalah kembali ke Perjanjian Lama dan belajar membacanya dengan baik dalam konteksnya, sehingga kita tidak mendapatkan kesan yang salah tentang siapa Tuhan.
Sebagian besar masalah muncul karena kita membaca Perjanjian Lama dengan pemahaman budaya kita kembali ke masa lampau di mana terdapat pandangan dunia dan perhatian yang berbeda. Hal yang paling membantu saat saya mencoba memahami teks-teks bermasalah ini adalah dengan mencoba membacanya dalam konteks zaman dahulu. Saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti: Apa yang dikatakan budaya lain selama periode ini? Retorika apa yang biasanya mereka gunakan? Bagaimana Alkitab berbicara dalam konteks tersebut?
Alkitab memiliki hal-hal yang bersifat penebusan untuk dikatakan dalam konteks kuno yang masih terdengar sangat menyinggung telinga modern, tetapi itu karena kita bukan pendengar utamanya. Saya ingin menjembatani kesenjangan bagi para pembaca, membawa mereka kembali ke dunia Perjanjian Lama dan membantu mereka menghargai apa yang Alkitab coba lakukan. Jika kita melakukannya dengan baik, maka akan lebih mudah untuk menyeberangi jembatan kembali ke zaman kita sendiri dan bertanya: Apa artinya ini bagi saya?
Bagaimana kita bisa melihat kehadiran kasih karunia Allah di dalam Hukum Perjanjian Lama?
Biasanya, orang Kristen menganggap Hukum Perjanjian Lama sebagai bola dan rantai yang telah kita singkirkan dengan senang hati di dalam Kristus. Ketika saya kembali membaca narasi Gunung Sinai, saya tercengang oleh betapa murah hatinya Tuhan untuk turun ke level manusia, menyatakan diri kepada umat-Nya, dan menunjukkan kepada mereka tentang apa yang Dia harapkan. Hal ini sangat mencolok ketika kita membandingkan situasi mereka dengan orang-orang Timur Dekat kuno lainnya, di mana selalu ada kecemasan tentang apa yang diinginkan oleh para dewa.
Alasan lain untuk melihat kasih karunia Tuhan bekerja adalah bahwa hukum di Sinai diberikan setelah Dia menyelamatkan orang Israel dari penindasan. Tuhan tidak memberi mereka hukum agar mereka bisa diselamatkan; Dia sudah membebaskan mereka. Alasan terakhir adalah bahwa ketaatan pada hukum-hukum Allah memungkinkan Dia untuk terus tinggal di antara umat-Nya. Hukum Taurat adalah sarana untuk mengalami kehadiran Tuhan.
Bagaimana pemahaman yang tepat tentang Sinai dapat mengoreksi kepercayaan yang gampangan dan iman orang Kristen yang terlalu individualitis?
Banyak orang Kristen dewasa ini memiliki pandangan yang terpotong-potong tentang apa artinya menjadi seorang Kristen. Jika kita mulai dengan hal ini—bahwa menjadi seorang Kristen adalah meminta Yesus masuk ke dalam hati saya agar saya dapat masuk surga ketika saya meninggal—maka yang terutama dari hal ini adalah tentang setelah saya meninggal daripada tentang hidup saya di sini dan saat ini. Namun, jika kita memahami Sinai dengan serius, kita dapat melihat bahwa Allah menyelamatkan umat-Nya dari Mesir bukan hanya tentang mengamankan kehidupan akhirat mereka. Hal ini berkaitan dengan soal mereka menjadi umatnya secara nyata, ketika mereka berinteraksi satu sama lain dan dengan bangsa-bangsa sekitar mereka. Mereka adalah wakil-Nya bagi bangsa-bangsa.
Jika kita dapat menangkap sekilas tentang hal itu, jika kita dapat melihat bahwa menjadi seorang Kristen berarti memasuki kisah tersebut dan menjadi wakil Tuhan, maka tentang bagaimana kita hidup tentu tiba-tiba akan menjadi penting. Pilihan-pilihan saya bukan hanya antara saya dan Tuhan. Pilihan-pilihan tersebut bukan hanya soal saya memiliki kesejahteraan internal atau jaminan untuk mengetahui ke mana saya akan pergi setelah saya meninggal. Ini lebih umum dari hal itu. Saya sedang disaksikan banyak orang, dan itulah cara Tuhan merancangnya.
Akan tetapi, hal tentang Sinai adalah bahwa itu bukan hanya kisah soal individu; itu adalah seluruh komunitas yang disebut milik Tuhan yang berharga, sebuah kerajaan imam. Mereka bersama-sama harus menjalankan mandat ini untuk menjadi wakil Tuhan dan membawa nama Tuhan di antara bangsa-bangsa. Tidak ada satu orang pun yang dapat melakukan seluruh pelayanan ini secara individual. Hal ini mengingatkan saya bahwa saya tidak menjadi seperti yang Allah kehendaki tanpa menjadi bagian dari komunitas gereja. Secara korporat, kita mencapai sesuatu, mewujudkan sesuatu yang tidak dapat kita lakukan sendiri.
Mengingat banyak orang di luar gereja tergoda untuk mengasosiasikan Injili dengan kefanatikan, bagaimana kita dapat memulihkan reputasi kita dan menyandang nama Tuhan dengan benar di dunia ini?
Penting bagi kita untuk memperhatikan bahwa Allah tidak memberikan Hukum Taurat di Sinai kepada semua bangsa. Ia memberikannya kepada umat-Nya sendiri, yang Ia tebus dari perbudakan. Ini bukan tentang membuat hukum moralitas. Ini tentang menyiapkan kondisi untuk hubungan yang intim dan berkelanjutan dengan Tuhan. Kita belum melakukan pelayanan bagi nama Tuhan dengan dikenal sebagai orang yang berusaha membuat orang lain hidup sesuai dengan aturan kita.
Yesus benar ketika meringkas semua hukum Sinai dengan “Kasihilah Tuhan, Allahmu” dan “Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri” (Mrk. 12:30–31). Ini menyatukan dimensi vertikal dan horizontal dari perjanjian Sinai. Intinya adalah untuk menjadi terang yang bersinar bagi bangsa-bangsa, sehingga kita perlu secara aktif mencari cara agar menjadi berkat, baik dengan cara memelihara lingkungan, bekerja untuk meningkatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan, atau memastikan sistem peradilan kita berjalan sebagaimana mestinya. Semua hal itu memuliakan Tuhan. Prinsip-prinsip yang kita lihat dinyatakan dalam hukum-hukum Perjanjian Lama dapat membentuk prioritas kita sewaktu kita mempertimbangkan bagaimana menolong dunia ini menjadi tempat bagi berkembangnya umat manusia.
Diterjemahkan oleh Imam Daniel.