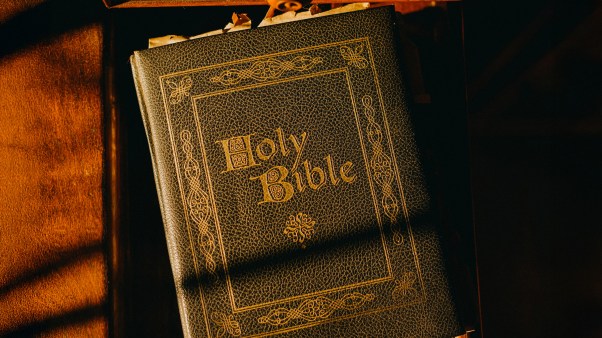Saat remaja, saya memimpin kelompok kecil pertama saya bersama seorang teman, dipandu oleh seorang wanita yang lebih tua dari gereja kami. Selama diskusi tentang iman, saya memutuskan untuk menjadi rentan dan berbagi keraguan saya tentang Allah untuk mendorong orang lain agar lebih terbuka.
Setelah pertemuan selesai, wanita itu menarik saya ke samping untuk memperingatkan saya tentang memberikan contoh yang baik bagi kelompok. Pesannya baik, tetapi jelas: Keraguan tidak pantas bagi seorang pemimpin yang sedang naik daun.
Selama bertahun-tahun, keraguan saya berubah. Meskipun saya tidak lagi mempertanyakan keberadaan atau identitas Allah, saya masih bergulat dengan kedaulatan dan kebaikan-Nya, bertanya-tanya mengapa segala tindakan-Nya—atau saat Ia tidak bertindak—terkadang tampak bertentangan dengan pemahaman saya tentang siapa Dia.
Saya tidak sendirian. Survei Lifeway Research tahun 2023 menemukan bahwa hanya setengah dari orang Amerika yang tidak meragukan keberadaan Tuhan—dan setengah dari mereka yang berlatar belakang Kristen mengatakan bahwa mereka pernah mengalami periode keraguan yang “berkepanjangan” di beberapa titik dalam hidup mereka.
Tentu saja, keraguan bukanlah masalah modern. Manusia telah berjuang untuk memercayai Tuhan sejak Taman Eden. Alkitab menggambarkan keraguan sebagai ciri umum dari kondisi manusia yang telah jatuh dalam dosa—bahkan bagi orang yang dianggap paling suci di antara kita. Dari Abraham dan Sara hingga “Tomas si Peragu,” ketidakpastian telah menjadi ciri kehidupan umat Tuhan selama ribuan tahun. Banyak sekali orang kudus sepanjang sejarah gereja yang bergumul dengan ketidakpercayaan, banyak di antara mereka yang mengalami “malam gelap jiwa,” sebagaimana John of Cross gambarkan.
Namun, munculnya keraguan yang meluas akhir-akhir ini di dunia Barat sebagian tercermin oleh kemunduran yang terus-menerus. Di Amerika Serikat, hal ini disebut sebagai “The Great Dechurching” (Fenomena meninggalkan gereja secara besar-besaran), dengan sekitar 40 juta orang tidak lagi hadir dalam ibadah gereja.
Selain “penderitaan manusia” dan “konflik di dunia,” dua sumber keraguan terbesar di Amerika, menurut Barna, adalah “pengalaman masa lalu dengan lembaga keagamaan” dan “kemunafikan orang-orang beragama.” Krisis pelecehan di gereja mengingatkan kita bahwa keyakinan agama dapat dengan mudah dijadikan senjata, dan banyak pemimpin serta lembaga Kristen telah menggunakannya untuk kejahatan.
Sebagaimana yang saya alami sendiri, gereja dapat menjadi tempat yang tidak ramah bagi mereka yang ragu—reputasi yang banyak orang berusaha perbaiki selama bertahun-tahun. Alih-alih menunjukkan “belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu” (Yud. 1:22), kita justru sering mengutuk mereka.
Sementara ada lebih banyak yang dapat dilakukan untuk mengakomodasi pergumulan iman jemaat, ada baiknya juga untuk memperingatkan terhadap ekstrem lainnya. Artinya, dalam upaya kita untuk menyemangati orang yang ragu dan menghindari menjadikan keyakinan sebagai senjata, kita tidak boleh melupakan panggilan kita untuk menjadi orang yang beriman.
Kita hidup dalam generasi yang meragukan—sebuah zaman ketidakpercayaan dan dekonstruksi agama, di mana kecurigaan merasuki udara yang kita hirup. Pada kedua sisi lorong ideologis, orang-orang yang menaruh kepercayaan penuh mereka pada satu set keyakinan telah dianggap sebagai “domba” naif yang tidak memiliki keterampilan berpikir kritis atau gagal “melakukan penelitian.”
Jika kita tidak berhati-hati, gereja dapat mengikuti isyarat budaya dunia dan ikut serta dalam upaya menumbuhkan skeptisisme dan memupuk sinisme. Beberapa orang Kristen mengatakan bahwa adalah wajar, bahkan sehat, untuk hidup dalam tarik-ulur terus-menerus antara iman dan keraguan. Ada yang berpendapat lebih jauh dengan mengatakan bahwa iman membutuhkan keraguan agar dapat berfungsi dengan baik—menggambarkan keraguan sebagai suatu kebajikan yang perlu dipupuk, bukan ketegangan yang harus terus-menerus diatasi melalui iman.
Pada awalnya, retorika seperti itu mungkin tampak meyakinkan, terutama bagi mereka yang kadang-kadang berjuang untuk mempertahankan iman. Namun bagi mereka, seperti saya, yang mendapati diri mereka terjerumus dalam jurang keraguan kronis yang suram—lebih mirip keputusasaan—ini adalah prognosis yang menyedihkan. Di saat-saat seperti itu, saya berpegang teguh pada secercah harapan bahwa masa keraguan saya hanya sementara, dan bahwa suatu hari saya akan mendapatkan kembali sedikit iman yang tak tergoyahkan yang tampaknya dimiliki sejumlah orang Kristen dalam jumlah besar.
Alkitab memberi tahu kita bahwa iman itu penting. “Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah” (Ibr. 11:6).
Kitab Suci berulang kali memuji kepercayaan yang sederhana, seperti anak kecil, dan bergantung kepada Tuhan, serta mendorong kita untuk menjadi seperti domba yang taat dan bukan seperti kambing yang memberontak (Yoh. 10:27; Mat. 25:32–22). Dan meskipun kita mungkin memiliki kapasitas alami yang berbeda untuk itu, kita semua dipanggil untuk hidup “menurut ukuran iman, yang dikaruniakan Allah” kepada kita masing-masing (Rm. 12:3).
Contohnya suami saya. Dia memiliki karunia rohani berupa iman (seperti tercantum dalam 1 Korintus 12:9). Pola yang sering terjadi dalam pernikahan kami adalah dia dengan tenang menanggapi krisis dengan berkata, “Semuanya akan baik-baik saja.” Yang saya tanyakan, “Akan tetapi bagaimana kamu tahu?” dan dia menjawab, “Ya, tahu saja.”
Alih-alih selalu menganggap hal ini menggembirakan, bagi seseorang seperti saya—yang “dikaruniai” kecemasan dan gelar teologi—imannya yang tak tergoyahkan terkadang bisa menjengkelkan.
Bukan berarti dia tidak pernah mengalami situasi yang mengancam imannya. Kehamilan anak pertama kami berakhir dengan keguguran, dan kelahiran putri kami ditandai dengan momen traumatis ketika suami saya harus berlari menyusuri koridor rumah sakit pada tengah malam, berteriak minta tolong.
Namun, dia terus-menerus menantang saya dengan menjalani definisi iman yang paling ringkas dalam Alkitab: “…dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat” (Ibr. 11:1).
Sebagaimana penulis A.J. Swoboda mengatakan, “Iman tumbuh subur dalam ketegangan misteri, di mana kita percaya bahkan ketika kita tidak sepenuhnya mengerti.” Iman bukanlah tentang memiliki semua jawaban, tetapi tentang memercayai Dia yang memiliki jawaban—yang terkadang berarti memercayai-Nya secara membabi buta.
Ketika Tomas menyentuh Tuhannya yang telah bangkit dan akhirnya percaya, Yesus berkata, “Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya” (Yoh. 20:29). Dia juga berkata kepada murid-murid-Nya, “Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya” (Mat. 21:21–22). Orang yang ragu, kata Kitab Suci, “…sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian ke mari oleh angin…. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya” (Yak. 1:6, 8).
Saya pernah menjadi orang yang diombang-ambingkan ombak dalam musim-musim pergulatan rohani di masa lalu, dan saya dapat mengatakan ayat ini dengan tepat menggambarkan realitas emosional dari keraguan.
Teori psikologi tentang disonansi kognitif memberi tahu kita bahwa otak kita terprogram untuk menginginkan penyelesaian dan bahwa ketidakpastian adalah tempat yang tidak nyaman dan tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Seperti yang ditulis teolog Brad East untuk CT, “Keraguan adalah tangga, bukan rumah.”
Mungkin inilah sebabnya kita telah melihat gelombang budaya mulai bergeser dari keraguan kronis kembali ke keyakinan. Data survei terkini menunjukkan bahwa gerakan dekonstruksi—gelombang orang yang meninggalkan keyakinan atau memikirkan kembali keyakinan mereka—mungkin melambat. Dan peningkatan tajam jumlah “nones” (mereka yang tidak mengaku berafiliasi dengan agama apa pun) dan “dones” (mereka yang keluar dari agama Kristen karena berbagai alasan dan tidak mau lagi berurusan dengan gereja.) telah mencapai titik puncaknya.
Pada saat yang sama, kisah-kisah tentang pertobatan yang tak terduga bermunculan di mana-mana. Dari selebritas dan orang berpengaruh hingga elit budaya dan akademisi, tokoh-tokoh ternama menemukan jalan mereka menuju Yesus, atau setidaknya agama Kristen budaya, dengan cara yang paling tidak diduga. Berkali-kali, iman telah membuktikan bahwa iman dapat bangkit dari abu keraguan.
“Tidak ada penderitaan yang lebih besar daripada penderitaan yang disebabkan oleh keraguan orang-orang yang ingin percaya,” tulis Flannery O’Connor dalam suratnya kepada seorang teman yang sedang mengalami krisis rohani. “Namun, saya hanya bisa melihatnya, dalam diri saya sendiri, sebagai proses pendalaman iman.”
Saya pikir saat ini lebih dari sebelumnya, orang-orang yang ragu dan tidak puas akan mencari orang-orang yang percaya dan berani. Mereka akan mencari orang-orang Kristen yang memiliki iman yang tangguh—bukan iman yang asal-asalan dan tidak relevan, tetapi iman yang telah diuji dan menang, iman yang telah mengintip ke dalam jurang kehidupan tanpa Tuhan dan melangkah mundur dari tepiannya.
Salah satu sumber dorongan seperti itu dapat ditemukan dalam kehidupan rohani orang-orang kudus di masa lalu—mereka yang bertekun dalam iman meskipun bergumul dengan keraguan.
Teolog Søren Kierkegaard, seperti saya, bergulat dengan kesehatan mentalnya, menyebut depresi sebagai “istri yang paling setia.” Dalam karya yang diberi nama samaran itu, dia menulis bahwa “keraguan adalah keputusasaan pikiran” dan bahwa keputusasaan adalah “penyakit yang mematikan.”
Kierkegaard mengakui aspek konstruktif dan destruktif dari keraguan. Dia menulis, “Saya pikir saya punya keberanian untuk meragukan segalanya,” tetapi dia juga menulis, “Salah satu definisi paling penting bagi seluruh kekristenan” adalah bahwa “lawan dari dosa bukanlah kebajikan, melainkan iman.”
Meskipun keraguan kita kadang kala dapat mencerahkan, Yesus memanggil para pengikut-Nya untuk bertindak berdasarkan iman, bukan karena keraguan. Seperti yang dikatakan rasul Paulus, “segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, adalah dosa” (Rm. 14:23). Keraguan itu wajar, ya, tetapi iman itu supranatural. Seperti yang diamati Kierkegaard, iman adalah sebuah “lompatan”—dan “tanpa risiko, tidak ada iman, dan semakin besar risikonya, semakin besar pula imannya.”
Kita juga memiliki orang-orang kudus yang masih hidup saat ini yang imannya menjadi anugerah bagi gereja, bagi mereka yang ragu. Namun, selain berdoa bagi mereka yang sedang bergumul secara rohani (yang merupakan tempat terbaik untuk memulai!), bagaimana orang-orang ini dapat membantu?
Jawabannya bukanlah ketidaksetujuan dan kecaman yang agresif; juga bukan optimisme Pollyanna yang menepis pergumulan spiritual dengan basa-basi yang tidak peka dan senyuman.
Tentunya orang-orang percaya yang teguh, terutama kita yang memiliki bekas luka rohani yang telah disembuhkan, memiliki lebih banyak hal untuk ditawarkan daripada sekadar telinga yang simpatik, kata-kata penyemangat yang umum, dan doa yang sopan.
Ya: Kita mempunyai kesaksian—yaitu kesaksian publik tentang cara Tuhan menyatakan diri-Nya kepada kita. Dan kita tidak perlu berkecil hati untuk membagikannya kepada mereka yang ragu (mungkin karena takut hal itu akan membuat mereka terasing atau malu), karena kesaksian kita bukanlah tindakan memuji diri sendiri; melainkan tali penyelamat.
Kesaksian kita bagaikan “totem” dari film Inception: penanda personal tentang kesetiaan Tuhan di masa lalu yang mengingatkan kita akan kenyataan saat hidup terasa seperti mimpi—atau mimpi buruk. Kisah-kisah seperti itu serupa dengan batu-batu peringatan yang diperintahkan Allah kepada bangsa Israel untuk didirikan sebagai monumen atas segala janji yang telah Ia genapi (Yos. 4:4–9). Kita memerlukan penanda nyata di luar diri kita untuk mengikat kita pada kebenaran.
Saya sangat bersyukur Yesus tidak meninggalkan kita sendirian dalam perjalanan iman ini, melainkan sebaliknya mengutus Roh Kudus untuk melanjutkan karya-Nya di dalam dan melalui gereja sebagai kehadiran diri-Nya yang berkelanjutan di bumi. Kitab Suci memperjelas bahwa setiap tugas dari hidup kristiani, termasuk membangun kembali penopang iman kita, dirancang secara ilahi untuk komunitas.
Seperti yang ditulis Dietrich Bonhoeffer, Allah menghendaki kita mencari dan menemukan Firman-Nya yang hidup dalam kesaksian seorang saudara, dalam mulut seseorang. Oleh karena itu, orang Kristen membutuhkan orang Kristen lainnya yang menyampaikan Firman Tuhan kepadanya. Dia membutuhkannya lagi dan lagi saat dia merasa tidak yakin dan putus asa, karena dia tidak dapat menolong dirinya sendiri.
Keraguan tumbuh subur dalam isolasi. Bahkan, Iblis melakukan pekerjaannya dengan sangat baik ketika tidak ada pembela di sekitar kita yang dapat menyampaikan perkataan yang lebih baik kepada kita atau untuk kita.
Kitab Suci memberi tahu kita bahwa mereka yang tidak memiliki perisai iman tidak akan sanggup menahan serangan musuh (Ef. 6:16), yang membuat mereka rentan terhadap pekerjaan licik yang sama yang telah dilakukan Iblis sejak Taman Eden—untuk membuat kita meragukan kebaikan, kesetiaan, dan kedaulatan Tuhan.
Namun dalam salah satu adegan paling dahsyat dalam Kitab Suci, Rasul Yohanes melihat Iblis (yang namanya berarti “musuh” atau “penuduh”) dikalahkan oleh Yesus dan orang-orang kudus: Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah Anak Domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka (Why. 12:10–11).
Pada akhirnya, keraguan kita tidak sirna melalui argumen atau pengalaman. Hanya darah Yesus dan kesaksian yang dihasilkannya dalam hidup kita yang memiliki kuasa untuk melawan tipu muslihat Iblis—penyerangan, pemangsaan, dan tuduhannya yang tanpa henti (1Ptr. 5:8).
Setiap kali kita meminjamkan iman kita untuk saudara-saudari yang lebih lemah—sampai mereka cukup kuat untuk menanggungnya sendiri—kita sedang berperang melawan kuasa kegelapan.
Pada akhirnya, keselamatan kita tidak didasarkan pada iman kita tetapi pada Yesus. Yesus adalah batu tanda peringatan yang utama. Dia adalah batu penjuru kita. Maka kita mengarahkan pandangan kita kepada Dia “yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan” (Ibr. 12:2). Iman tidak berarti kita tidak pernah ragu. Artinya sederhana, kita cukup percaya kepada Yesus untuk membawa ketidakpastian kita kepada-Nya, dengan mengetahui bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita di saat kita tidak percaya, marah, atau mempertanyakan, melainkan Dia akan mendekat dan mengundang kita untuk melakukan hal yang sama (Yak. 4:8).
Kepercayaan seperti itu sederhana, tetapi bukan berarti itu mudah. “Jauh lebih sulit untuk percaya daripada tidak percaya,” tulis O’Connor kepada temannya yang ragu. Namun bagi siapa pun yang tengah bergumul, saya setuju dengan nasihatnya: “Jika Anda merasa tidak bisa percaya, setidaknya Anda harus melakukan ini: Tetaplah berpikiran terbuka. Tetaplah terbuka terhadap iman, teruslah menginginkannya, teruslah memintanya, dan serahkan sisanya kepada Tuhan.”
Sekalipun saat ini yang dapat Anda lakukan hanyalah berbisik dalam doa, biarlah ini menjadi benih sesawi iman Anda: “Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini!” (Mrk. 9:24). Dengan anugerah Tuhan, itu cukup.
Stefani McDade adalah editor teologi di Christianity Today.
Diterjemahkan oleh Denny Pranolo.