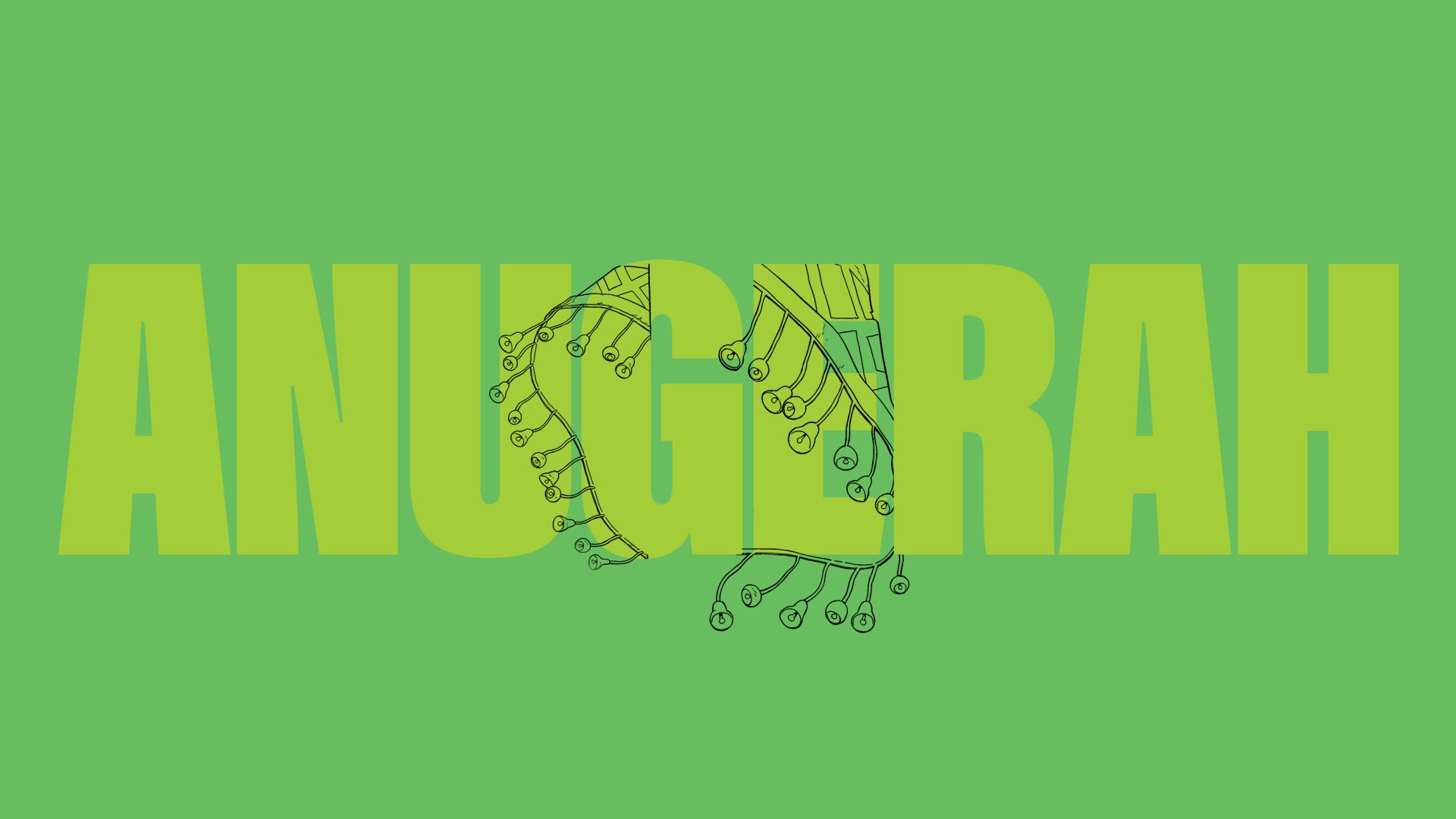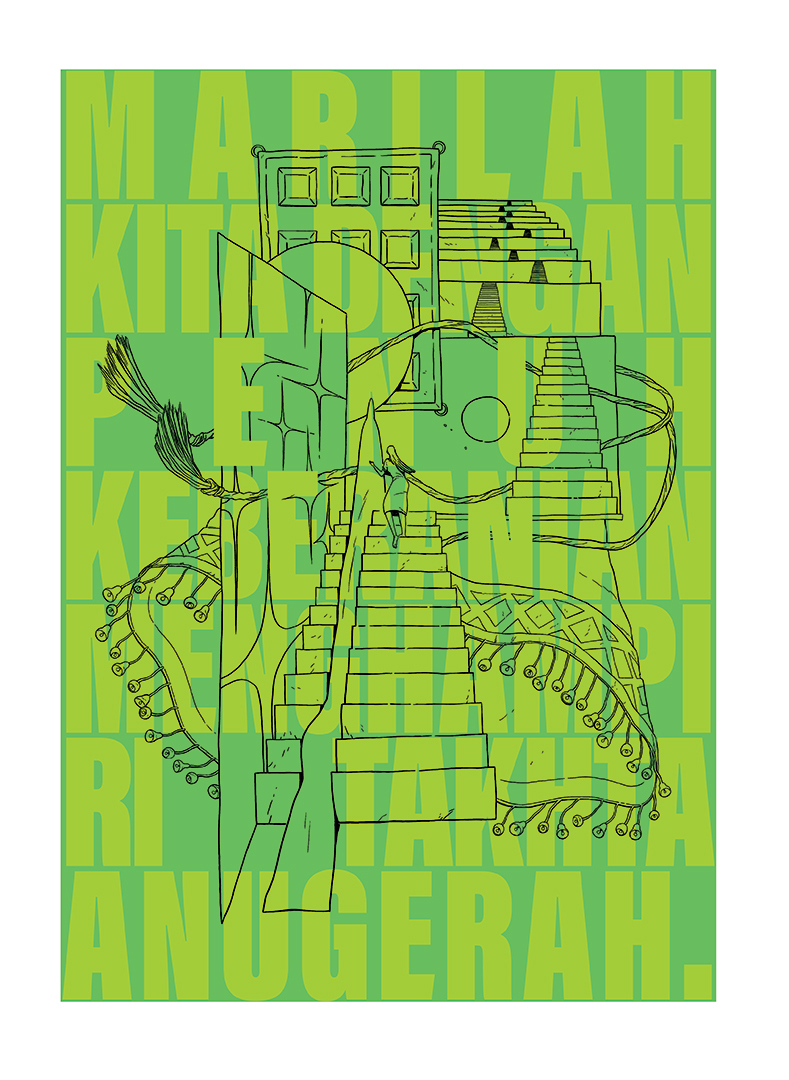Dalam seri CLOSE READING ini, para pakar Alkitab merenungkan suatu bagian Alkitab dalam bidang keahlian mereka yang telah membentuk pemuridan diri mereka dan terus memengaruhi mereka hingga saat ini.
Dalam surat kedua Paulus kepada jemaat di Korintus, ia mendengar Tuhan berkata, “Cukuplah anugerah-Ku bagimu” (2Kor. 12:9 LAI TB 2). Selama tahun-tahun pertama setelah saya membuat pernyataan iman kepada Kristus, kata-kata ini memberi saya penghiburan luar biasa. Mula-mula saya menafsirkannya dalam konteks dosa-dosa dan kekurangan saya sendiri: Ketika saya bersikap kasar kepada orang tua saya atau bergosip tentang seorang teman, anugerah-Nya sudah cukup.
Kemudian, saya mengartikan kata-kata tersebut dalam konteks kesusahan atau kesulitan, seperti ketika saya mengalami cedera lutut yang mengakhiri kemampuan saya untuk berlari, bermain sepak bola, dan football—dan banyak hal lainnya yang saya nikmati untuk dilakukan bersama keluarga dan teman-teman. Melalui tantangan-tantangan itu dan ketidakstabilan apa pun yang tengah saya alami, kemurahan hati Tuhan menjadi benang yang kuat. Dia benar-benar penolong saya yang selalu hadir.
Akan tetapi suatu hari, saya menemukan bahwa segala sesuatunya berbeda. Selama masa sakit kronis dan penyakit yang berkepanjangan, kata-kata yang telah memberi saya obat penenang berubah menjadi batu yang menghancurkan, beban yang menyesakkan yang tidak dapat saya singkirkan atau bersikap pura-pura tidak ada. Dalam gereja, semua teman saya berdiri dengan tangan terangkat penuh sukacita, dan semua orang, kecuali saya, melantunkan bagian reff dari sebuah lagu pujian yang populer: “Your grace is enough.” Saya duduk di kursi saya, diliputi gelombang keputusasaan dan kemarahan yang silih berganti. Orang-orang yang gembira dan sehat mengelilingi saya sambil bernyanyi. Di tengah kerumunan penuh gairah, saya sendirian.
Saat saya mendengar kata-kata itu, saya selalu bertanya pada diri sendiri, anugerah-Mu cukup? Cukup untuk apa, tepatnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menyita perhatian saya.
Saya bukannya tidak percaya lagi pada Tuhan atau bahwa keselamatan akan datang pada akhirnya. Bukan pula karena saya tidak percaya lagi bahwa Tuhan akan menyembuhkan dan menolong orang-orang di sekeliling saya. Saya sungguh percaya bahwa Tuhan dengan murah hati menjawab doa-doa. Namun, setelah satu dekade mengalami rasa sakit, kelelahan, dan penyakit yang membuat saya kehilangan harapan dan merasa sangat kesepian, saya tidak lagi memercayai bahwa itu benar untuk saya. Saya pasrahkan diri saya untuk menanggung penderitaan, untuk sekadar bertahan hidup.
Keputusasaan ini membawa saya ke banyak tempat yang gelap. Ketika orang lain memberi saya nasihat, mereka sering mengemukakan Yesus sebagai model kesetiaan dalam penderitaan, dan meskipun saya menghargai kepedulian mereka (dan setuju dengan landasan berpikir mereka), saya sering memikiran fakta bahwa sebagian besar penderitaan Yesus terjadi dalam waktu satu minggu. Tujuh hari. Saya akui bahwa kadang kala saya merasa iri dengan kematian-Nya yang cepat, meskipun menyakitkan. (Seperti yang saya katakan, saya telah mengalami hari-hari yang gelap.)
Saya didiagnosis dengan penyakit kronis pertama dari sekian banyak penyakit yang saya derita pada tahun 2007, dan setiap tahun, keadaan tampak makin memburuk. Saya menghabiskan sebagian besar tahun 2015 dalam penderitaan, merasakan sakit yang terus-menerus. Rasanya seperti ada yang melilitkan barbel ke tubuh saya dengan lakban. Setiap langkah yang saya ambil terasa sulit, dan ada hari-hari saya menangis ketika harus menaiki tangga ke kamar tidur.
Saya sedang menyelesaikan program Ph.D. dalam Perjanjian Baru, terus-menerus membaca, menulis, menyajikan makalah, mengajar, dan masih merasa khawatir apakah saya sudah melakukan cukup untuk mendapatkan pekerjaan. Saya memaksakan diri sepanjang hari dan kemudian terpuruk begitu melewati ambang pintu rumah kami. Hidup terasa mustahil.
Jika mengingat kembali apa yang saya rasakan, saya tidak mengerti bagaimana saya bisa membuat kemajuan dalam pekerjaan saya—kecuali bahwa penelitian itu dikerjakan dengan tidak banyak bergerak dan suami saya begitu murah hati. Yang saya sadari pada saat itu adalah kemungkinan bahwa saya mungkin melakukan pekerjaan ini dengan sia-sia. Jika saya hampir tidak dapat menyelesaikan penelitian, bagaimana mungkin saya dapat mengajar penuh waktu, seperti yang saya impikan?
Penelitian Ph.D. saya berfokus pada pengutipan lisan dalam bahasa Ibrani. Penulis secara konsisten menggambarkan Bapa, Putra, dan Roh mengucapkan kata-kata dari Kitab Suci. Saya telah menyelesaikan tugas saya mengenai apa yang dikatakan Bapa dalam Ibrani 1:5–13 dan selanjutnya beralih ke Ibrani 2:12–13, perkataan yang diucapkan Anak.
Konteks yang lebih luas dari Ibrani 2:12–13 menyoroti kemanusiaan Yesus, dan ketika saya menulis ini, saya mendapati diri saya merenungkan apa artinya bagi Yesus untuk “menjadi manusia seutuhnya [disamakan dengan saudara-saudara-Nya]” (2:17). Saat saya melihat penekanan pada kemanusiaan Yesus dalam Ibrani 2, saya melihat benang-benang yang saling terkait seperti jaring yang tersebar di setiap halaman. Yesus menjadi manusia merupakan hal yang krusial bagi seluruh argumen di kitab Ibrani.
Ibrani 4:14-16 juga termasuk di antara bagian yang saya teliti. Bagian ini tetap menjadi salah satu favorit saya di seluruh Kitab Suci:
Jadi, karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai dalam segala hal, hanya saja Ia tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. (LAI TB 2)
Bagian ini muncul pada titik yang sangat penting dalam kitab Ibrani. Banyak cendekiawan berpendapat bahwa bagian ini (terkadang diperluas hingga 4:11–16) berfungsi sebagai transisi penulis dari satu bagian utama ke bagian berikutnya. Ketiga ayat ini mengandung beberapa tema penting dari bagian utama berikutnya (4:11–10:25). Misalnya, meskipun penulis telah menyebutkan pelayanan Yesus sebagai imam (1:3; 2:17; 3:1, 6), ia mengisyaratkan bahwa ia akan menjelaskan, dimulai dengan 4:14–16, mengapa hal itu penting bagi para pendengar.
Bagian ini dan konteks sekitarnya sering kali ditafsirkan sebagai penjelasan tentang keunggulan Yesus dibandingkan imam-imam Lewi (yang membangun retorika penulis tentang perjanjian yang lebih agung di mana Yesus melayani, sebagaimana dirujuk dalam 8:6), serta dipandang sebagai kritik yang ditujukan bagi imam-imam Lewi. Banyak penafsir memahami Ibrani 5:1–10 sebagai kritik terhadap orang Lewi juga.
Namun jika Anda perhatikan dengan saksama, bagian ini sebenarnya membahas kualifikasi Yesus sendiri sebagai imam besar. Dengan kata lain, ini bukanlah sebuah kontras; ini adalah sebuah perbandingan. Bagian ini menunjukkan betapa pentingnya bahwa Yesus adalah manusia, karena “setiap imam besar dipilih dari antara manusia” (5:1).
Kembali ke Ibrani 4:14–16, apa yang saya perhatikan adalah fakta bahwa, di tengah argumen tentang apakah Yesus (yang bukan dari suku Lewi) memenuhi syarat untuk melayani sebagai imam, penulis Ibrani menekankan kemampuan Yesus untuk memahami orang-orang yang dilayani-Nya. Ia mampu “merasakan kelemahan-kelemahan kita” dan “sama seperti kita, Ia telah dicobai dalam segala hal” (4:15). Hal ini sesuai dengan gambaran si penulis sebelumnya tentang Dia sebagai “Imam Besar yang menaruh belas kasihan dan setia”, yang “dapat menolong mereka yang sedang dicobai” karena “Ia sendiri telah menderita ketika dicobai” (2:17–18).
Banyak orang tidak menyadari kekayaan kemanusiaan Yesus dalam kitab Ibrani karena kitab tersebut juga menggambarkan Yesus yang perkasa—seseorang yang disebut sebagai “gambar keberadaan Allah” (1:3) dan yang “telah meletakkan dasar bumi” (1:10).
Untuk penggambaran kemanusiaan Yesus, pembaca sering kali beralih ke Injil. Beberapa kalangan bahkan tampak khawatir ketika kemanusiaan Yesus ditekankan—seakan-akan hal itu bertentangan dengan keilahian-Nya.
Dalam Ibrani 4:14–16, penekanan pada Yesus sebagai manusia tidak salah lagi. Namun penulis memadukan gambaran Yesus yang dicobai dalam segala hal dengan kenyataan bahwa Dia adalah Anak Allah yang melintasi semua langit (ay. 14). Yesus sepenuhnya manusia, dan Dia sepenuhnya Allah. Keduanya tercermin dalam Kristologi kitab Ibrani.
 Gambar: Ilustrasi oleh Simon Fletcher
Gambar: Ilustrasi oleh Simon FletcherBegitu konsep-konsep ini menyatu dalam pikiran saya, saya memahami bahwa Minggu Sengsara hanyalah sekilas dari penderitaan Yesus. Meskipun tantangan paling berat yang dihadapi-Nya terjadi di minggu itu, Ia mengalami kelemahan dalam bentuk kelaparan (Mrk. 11:12) dan kelelahan (Yoh. 4:6) serta mungkin juga penderitaan sepanjang hidup-Nya di bumi.
Selain itu, kemahatahuan-Nya yang dipadukan dengan pengalaman-Nya sebagai manusia adalah sesuatu yang layak untuk direnungkan secara teologis lebih lanjut. Lagipula, penderitaan apakah yang tidak dipahami Yesus?
Dengan susah payah saya menaiki tangga, memaksa kaki saya bergerak inci demi inci, saya memusatkan pandangan saya pada Yesus, sebagaimana penulis Ibrani mendorong kita untuk melakukannya (12:2).
Namun ketika saya melihat, Dia tidak duduk dengan nyaman di atas, menunggu. Yesus turut menyeret diri-Nya menaiki tangga. Yesus lelah dan kesakitan. Dan Dia bersama saya.
Gambaran solidaritas ini mengubah saya. Allah tidak meminta saya menanggung sesuatu yang Ia sendiri tidak tanggung. Saat saya menatap-Nya, saya menyadari bahwa saya kini dapat melihat-Nya lebih jelas, tetapi Dia tidak pernah kehilangan pandangan terhadap saya.
Saya tidak yakin apakah saya telah menemukan jawaban yang “tepat” untuk pertanyaan tentang apa saja yang cukup bagi anugerah Allah, tetapi ketika kata-kata itu terasa menyakitkan, saya dapat berkata, “Cukuplah anugerah-Mu bagiku, sebab Engkau besertaku.”
Pemahaman baru tentang Ibrani 4:14–16 ini juga memengaruhi relasi saya. Menyaksikan bahwa Yesus menunjukkan empati dan belas kasihan terhadap orang lain karena Ia hadir bersama mereka, itu mengubah cara saya berbicara kepada mereka yang sedang menderita di sekitar saya. Selama beberapa waktu, saya menghindari berbagai ungkapan klise yang tidak membantu ketika saya berbicara kepada mereka yang sedang sakit atau berduka, karena saya tahu betapa sedikitnya manfaat hal itu bagi saya; tetapi saya belum menemukan kata-kata pengganti.
Pemahaman yang lebih mendalam tentang solidaritas ini telah mengajarkan saya pentingnya kehadiran—dengan mengatakan, “Saya turut prihatin dengan apa yang Anda alami” dan mencoba memahami penderitaan mereka.
Jika kita hendak meneladani Kristus—atau mendekati-Nya, seperti yang diajarkan kitab Ibrani—maka tentu saja empati-Nya adalah bagian dari apa yang harus kita miliki. Kita tidak memiliki kemampuan untuk menanggung pengalaman orang lain, sebagaimana Yesus mengambil rupa manusia, tetapi kita dapat menyelami lebih dalam penderitaan mereka. Bagian-bagian dalam kitab Ibrani ini membuat saya berdoa kepada Allah agar Ia memberikan saya pemahaman yang lebih mendalam mengenai apa yang dialami orang-orang di sekitar saya, sehingga saya dapat merawat mereka dengan baik.
Penulis kitab Ibrani menawarkan penghiburan di sini dan saat ini—anugerah dari Allah bagi masa sekarang ini. Sering kali dalam masa-masa penderitaan saya, orang-orang mendesak saya untuk berharap akan kesembuhan yang mungkin terjadi; mereka berdoa dengan sungguh-sungguh agar saya mengalami kelegaan. Doa-doa itu tidak salah arah. Juga tidak bermaksud jahat. Namun, doa-doa itu tidak memberikan penghiburan yang sama bagi saya.
Ketika saya menemukan solidaritas dengan orang lain yang mengalami penderitaan dan penyakit kronis, saya mendengar mereka menceritakan frustrasi yang sama. Kami tahu bahwa doa-doa untuk kesembuhan itu baik dan mencerminkan kepercayaan terhadap kuasa Allah, tetapi kami tidak tahu apakah kesembuhan adalah kehendak Allah. Kami membutuhkan doa dan harapan untuk keadaan kami saat ini.
Pada akhirnya, harapan tidak datang dalam bentuk kesembuhan bagi saya. Harapan datang melalui seorang teman baik, yang juga berjuang karena penyakit kronis, dan harapan datang melalui teologi Ibrani.
Setahun atau dua tahun setelah saya menyelesaikan penelitian saya tentang Ibrani 4, seorang teman lain meminta saya untuk berbagi tentang iman saya sehubungan dengan penderitaan dan penyakit kronis yang saya derita. Saat saya mempersiapkannya, saya menyadari betapa besar kemurahan Allah kepada saya. Saya jatuh cinta pada kitab Ibrani saat saya masih kuliah karena saya terpesona dengan cara penulis menggunakan Kitab Suci dan gambaran keimamatannya. Saya begitu tertarik pada teks ini, dan kini menghabiskan waktu untuk mempelajarinya adalah pekerjaan saya. Namun, saat saya bekerja, sebagaimana Allah berbicara melalui para nabi (1:1–2), Dia berbicara kepada saya melalui Anak-Nya.
Madison N. Pierce adalah profesor madya Perjanjian Baru di Western Theological Seminary dan penulis Divine Discourse in the Epistle to the Hebrews.
Diterjemahkan oleh Mellie Cynthia.