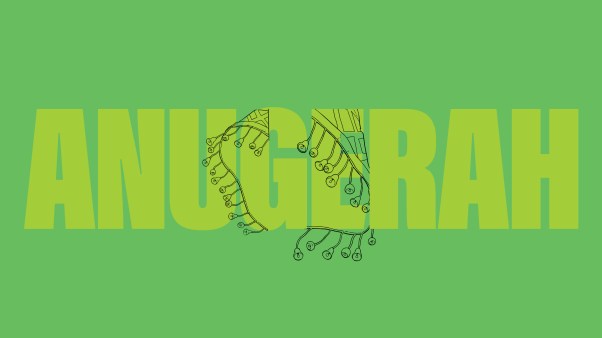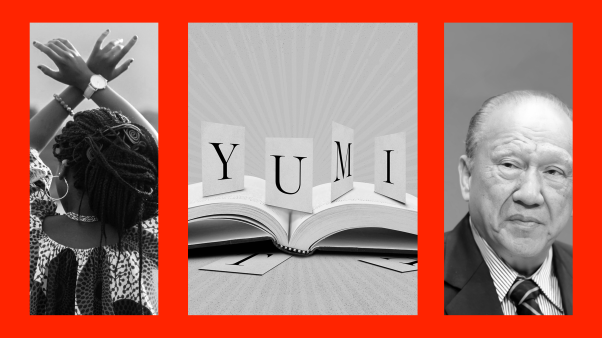Menurut saya, banyak di antara kita membaca kisah tentang orang Samaria yang murah Hati tanpa memahami bahwa pesan utamanya secara tersurat adalah, “Jangan jadi orang yang menyebalkan.”
Cerita sekolah Minggu pun terungkap dalam pikiran kita. Seorang pria malang dan tak bersalah dipukuli secara brutal, dan siapa pun orang yang punya moral akan merasa ngeri. Imam dan orang Lewi melihatnya dan melewatinya, mereka memilih berjalan di seberang jalan. Kita merasa heran dengan perilaku mereka yang tidak berperasaan. Tentu saja ini bukan hal yang akan dilakukan oleh orang yang baik! Bagaimana mungkin mereka tega meninggalkan orang malang itu tergeletak di pinggir jalan? Kita secara tidak imajinatif memasukkan diri kita ke dalam cerita sebagai orang Samaria yang murah hati, dan yakin bahwa jika peristiwa ini terjadi dalam kehidupan nyata, kita tentu akan melakukan hal yang benar.
Saya sedang dalam perjalanan pulang ke rumah saya di daerah pedesaan pedalaman negara Afrika Timur Burundi, tempat saya tinggal dan bekerja sebagai dokter misionaris. Beberapa hari terakhir ini merupakan maraton pertemuan lintas budaya dan multibahasa yang menegangkan mengenai akreditasi internasional untuk sekolah kedokteran kami. Perjalanan pulang memakan waktu tiga jam, saya benar-benar kelelahan. Yang saya inginkan hanyalah bertemu keluarga dan berbagi makanan yang saat ini berada di lantai kursi penumpang.
Mobil saya melaju melewati jalan pegunungan sempit yang dipenuhi pohon pisang dan pohon kelapa. Perjalanan berbahaya ini, dengan turunan curam dan jarak pandang terbatas, merupakan teror selama beberapa tahun pertama saya tinggal di sini, tetapi sekarang hal itu sudah menjadi hal yang lumrah. Saat mengemudi, saya berdoa agar perjalanan pulang ini dapat meringankan sedikit beban yang saya rasakan.
Saat jalan berbelok lagi, saya melihat keributan di depan saya: Kaca pecah, sepeda motor hancur, dan orang-orang berkerumun di pinggir jalan. Dua pemuda menggotong sesosok tubuh menjauh dari sepeda motor yang tergeletak di aspal ke bahu jalan kerikil sempit yang menghadap ke jurang curam, orang yang satu memegang kaki dan yang satu lagi memegang lengan.
Saya menyadari kecelakaan ini baru saja terjadi beberapa saat yang lalu. Tiba-tiba saya dilanda badai keyakinan dan keraguan. Pada satu sisi saya ingin terus mengemudi. Lagipula, tidak seorang pun di tempat kejadian perkara akan tahu betapa besar kewajiban saya untuk membantu. Taruhannya pun tinggi. Saya harus pulang sebelum malam karena berkendara di malam hari tidak aman. Melibatkan diri bisa berarti diperas atau bahkan disalahkan atas kecelakaan itu. Satu-satunya hal yang membuat saya berhenti adalah sumpah yang saya ucapkan saat menjadi dokter, dan terus menyetir akan membuat sumpah itu tak berarti. Saya tahu betul kurangnya layanan darurat di daerah ini dan tidak ada bantuan lain.
Saya menepi dan keluar. “Saya dokter,” kata saya dalam bahasa Kirundi patah-patah. Saya berlutut di samping lelaki yang tak sadarkan diri itu, dengan luka besar di kepala, jejak darah kental mengarah ke tempat dia tergeletak di jalan. Saya perhatikan dia bernapas, pupil matanya bereaksi terhadap cahaya, dan denyut nadinya baik. Dia mungkin baik-baik saja jika dia sampai di rumah sakit.
“Apakah ada yang bisa berbahasa Prancis di sini?” saya bertanya kepada pemuda di sebelah saya. Beberapa detik kemudian, seorang pria berbeda muncul dari kerumunan dan menyapa saya dalam bahasa Prancis. “Apakah ada orang lain lagi yang terluka?” tanya saya.
Saat dia menunjuk ke arah kerumunan kecil yang berjarak 20 meter, saya heran mengapa saya belum menyadari suara ratapan keras yang datang dari arah itu. Saya berjalan ke sana. Seorang wanita muda berteriak saat saya memeriksa fraktur tibianya yang terbuka lebar. Cedera kakinya serius, tetapi dia jelas sadar dan bernapas dengan baik.
Saya sudah melakukan semua yang saya bisa di pinggir jalan. “Apa yang akan kamu lakukan?” tanya saya kepada pemuda yang bisa berbahasa Prancis itu. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketidakberdayaan yang sangat familier—tidak punya kendaraan, tidak punya uang, dan tidak ada orang yang bisa dimintai tolong karena semua orang di sekitarnya mengalami hal yang sama.
Saya menyadari lagi bahwa mereka tidak menunggu layanan darurat apa pun. Mereka mungkin berharap bahwa taksi akan membawa seseorang ke suatu tempat dalam enam jam ke depan, tetapi itu bisa saja terlambat, terutama bagi pria yang tidak sadarkan diri itu.
“Dengar, saya bisa untuk membawa salah satu dari mereka ke rumah sakit di ujung jalan,” saya menawarkan.
“Bawa gadis itu!” jawab lelaki di samping saya segera.
“Pria itu lebih sakit,” bantah saya.
“Dia sudah meninggal.”
Ini jelas-jelas tidak benar dan saya mulai marah. “Dia masih bernapas!” Suara saya meninggi.
Lelaki itu menatap ke arah tubuh yang terbaring di jalan, seakan-akan baru pertama kali melihatnya. Dugaan saya, pengendara sepeda motor itu adalah orang asing bagi orang yang berkerumun dan perempuan yang terluka (tetapi tidak terlalu kritis) itu adalah seorang teman, bahkan mungkin anggota keluarga.
Saya mendesah. “Begini, biar saya coba meratakan jok mobil saya. Mungkin saya bisa mengantar keduanya.” Saya memindahkan tas, meratakan kursi RAV4 saya. Hanya ada cukup ruang bagi kedua orang yang terluka untuk berbaring dan bagi seorang kerabat laki-laki untuk berjongkok di samping wanita yang terluka. Kami berempat siap berangkat.
Saat ini, polisi setempat telah tiba di tempat kejadian. Saya mencoba menjelaskan urgensi membawa orang yang terluka ke rumah sakit. Namun petugas ingin saya tetap berada di tempat kejadian untuk memberikan semacam pernyataan dan menyampaikan informasi kontak saya. Saya benar-benar tidak ingin terlibat dalam urusan polisi setempat. Akhirnya, saya membujuk mereka agar membiarkan saya pergi, dan saya bergegas melanjutkan perjalanan dengan mobil yang penuh dengan orang.
Orang yang bisa bahasa Prancis menghentikan saya. “Jangan pergi ke rumah sakit terdekat. Tolong. Tolong bawa mereka kembali ke kota, ke rumah sakit yang lebih baik.” Kembali ke kota berarti saya tidak akan bisa pulang sebelum matahari terbenam seperti yang direncanakan. Namun, saya tahu dia benar. Saya sudah pernah ke rumah sakit terdekat, dan mereka tidak bisa membantu. Dia memberi tahu saya rumah sakit mana yang harus mereka kunjungi. Saya tahu tempat itu, dan saya setuju.
Saat dalam perjalanan ke sana, saya mulai sadar bahwa kami tengah memerankan kisah orang Samaria yang murah hati. Ada orang-orang yang terluka di pinggir jalan, dan saya dihadapkan pada pilihan, apakah melewatinya seperti orang lain atau membawa mereka ke rumah sakit. Kemiripannya sungguh mencolok, jadi mengapa saya tidak menyadarinya sebelumnya?
Pada satu sisi, rasanya sama sekali tidak seperti yang saya bayangkan. Saya sangat marah, takut, dan lelah. Perempuan yang berada di belakang terus berteriak, “Saya sekarat!” dalam bahasa Kirundi, dan saya ingin berteriak balik padanya bahwa teriakannya tidak membantu apa pun.
Mengapa hari ini? Saya sudah sangat lelah. Dalam pikiran saya, orang Samaria yang murah hati adalah orang yang tidak bernama, tanpa beban, dan tidak ada keperluan mendesak untuk mengurus urusannya sendiri, karena dia tidak menyebutkan semua itu. Saya melihat kemurahan hatinya tetapi berasumsi itu datang dari sudut pandang yang tidak saya miliki. Kalau saja saya punya waktu sebanyak itu, saya akan bereaksi dengan ramah seperti dia. Namun, bagaimana jika orang sungguhan benar-benar berada dalam situasi tersebut?
Mungkin mengikuti orang Samaria yang murah hati berarti menyadari bahwa kita harus menyertakan beban kita, kelelahan kita, dan bahkan kebutuhan kita ke dalam cerita.
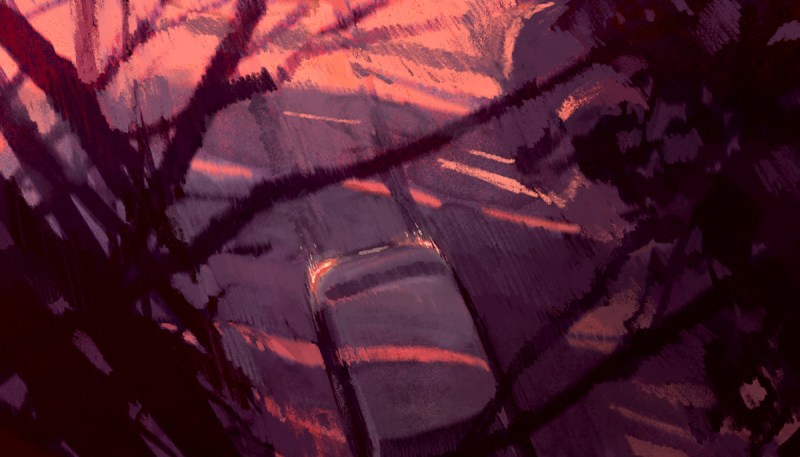
Perjalanan menuruni gunung itu mengerikan. Pada kursi belakang ada orang asing yang terluka parah dan waktunya mungkin tidak lama lagi. Saya juga menghadapi jalan berliku yang berbahaya dengan bahu jalan yang sempit, banyak lubang, pejalan kaki dan pengendara sepeda yang berbagi jalur, serta truk yang melaju menuruni gunung dengan kecepatan sepuluh kilometer per jam. Berusaha untuk terburu-buru di jalan ini membuat perjalanan yang biasanya penuh risiko menjadi gila sehingga saya harus secara sadar melambat. Pada satu titik, saya menginjak rem mendadak, dan kap mobil saya masuk di bagian bawah belakang truk gandeng. Saya menarik napas dalam-dalam dan mulai berdoa dengan suara keras dalam bahasa Inggris untuk meredam teriakan perempuan yang ada di belakang.
Saya berpikir tentang risiko. Mengemudi sambil membawa orang-orang ini di mobil saya bisa saja berarti terlibat dengan polisi setempat, yang pernah terjadi sebelumnya dan benar-benar ingin saya hindari. Turun gunung dengan cepat bisa berarti membahayakan nyawa saya sendiri. Salah seorang teman saya bercerita tentang pengalamannya mengemudi menuju bandara pada malam hari dan melihat sesosok mayat tergeletak di pinggir jalan. Saat dia bertanya-tanya apakah dia harus berhenti, dia teringat cerita bahwa itu adalah jebakan untuk membuat orang berhenti sehingga mereka bisa diserang dan dirampok. Dia terus melaju. Saya benar-benar mengerti.
Setiap implikasi ini mendapat tempat yang tepat dalam perumpamaan tersebut. Apakah orang Samaria itu takut ditipu? Masuk akal kalau dia berpikir demikian. Apakah dia akan terlibat dengan penegak hukum setempat karena berusaha membantu? Saya selalu berasumsi bahwa penginapan itu berada di jalan yang sama, tetapi mungkin orang Samaria itu harus kembali ke jalan yang sama seperti saya dan dengan demikian menempatkan dirinya pada bahaya yang tidak kecil ketika bepergian di malam hari.
Kehidupan saya di Burundi memberi saya banyak informasi untuk menilai situasi. Apa yang mungkin terjadi pada saya atau orang lain jika saya terlibat? Apa manfaatnya jika saya terlibat? Berhati-hati memang bijaksana, tetapi risiko itu sendiri tidak dapat berarti bahwa kita tidak terpanggil untuk masuk ke dalam cerita tersebut. Mungkin meneladani orang Samaria yang murah hati juga berarti menerima bahwa beberapa risiko—bukan sekadar bayar harga atau ketidaknyamanan—pasti akan mengikuti.
Dengan lega, saya tiba di kota dan menuju ke rumah sakit. Saya masuk melalui gerbang dan akhirnya menemukan area darurat. Saya memarkir mobil dan melompat keluar, menghentikan pria pertama yang saya lihat berpakaian seragam perawat.
“Ada dua pasien dengan cedera trauma di mobil saya. Seorang pria pingsan dengan luka di kepala dan seorang wanita dengan fraktur tibia terbuka.”
Dia menatap balik ke arah saya. Saya mencoba lagi, tetapi tidak berhasil. Setelah beberapa menit, dokter yang tampaknya bertugas pun keluar. Saya segera membawanya ke mobil dan membuka pintu belakang. Pria itu masih pingsan. Wanita itu tampak lebih tenang sejenak, bersandar pada kerabatnya yang berjongkok di sebelahnya. Saya sedang mencari tandu atau kursi roda. Saya tidak mengerti mengapa, setelah saya mempertaruhkan nyawa dengan bergegas menuruni gunung, tidak ada seorang pun yang bertindak.
Dokter mulai mengobrol dengan tenang dengan orang-orang yang sadar di mobil saya. Saya mengerti kalau dia bertanya tentang uang. Dia mendecakkan lidahnya dengan penuh penyesalan lalu menoleh pada saya. “Ah, jadi, ada masalah. Mereka tidak punya uang. Jadi kita tidak bisa merawat mereka.”
Ini pada dasarnya adalah rumah sakit swasta, dan saya paham bahwa rumah sakit tidak dapat tetap bertahan tanpa pendapatan untuk menutupi pelayanannya. Terlepas dari apakah pembayaran diharapkan atau tidak, saya tidak pernah membayangkan seorang dokter akan kehilangan motivasi untuk menolong orang dalam situasi darurat seperti ini. Sekarang saya sadar mengapa tak seorang pun mengeluarkan orang-orang yang terluka itu dari mobil saya. Rumah sakit ingin memastikan bahwa saya akan membawa mereka pergi lagi.
Saya mencoba untuk menggunakan posisi saya. Saya menjelaskan peran saya dalam kepemimpinan medis di daerah tersebut dan bertanya apakah dia setuju jika saya menelepon atasannya dan menceritakan apa katanya. Dia menatap saya dengan tatapan yang terlalu tenang, seperti seseorang yang melakukan percakapan ini setiap hari. “Tentu saja,” katanya.
“Baiklah, ke mana saya bisa membawanya?”
“Saya tidak tahu.”
“Bisakah saya membawa mereka ke rumah sakit lain di ujung jalan?”
“Saya tidak tahu.”
Saya membanting pintu bagasi, masuk ke mobil, dan melaju keluar gerbang tanpa berkata apa-apa lagi.
Ini bukan yang saya harapkan. Tugas saya adalah membawa orang-orang ini ke rumah sakit, di mana kemurahan hati saya akan dihargai dan orang lain akan meneruskan sisanya. Namun, yang terjadi kebalikannya—dan itu bukan karena saya memilih seperti itu, saya terjebak di dalamnya.
Mungkinkah hal ini terjadi pada orang Samaria yang murah hati? Saya selalu membayangkan pemilik penginapan tersenym menyambutnya, tetapi waktu melihat orang tidak dikenal dalam keadaan kritis, siapa yang mau menerimanya, walaupun dia membayar biaya pengobatannya? Apakah itu penginapan yang pertama kali dicoba oleh orang Samaria yang murah hati itu, atau dia harus berkeliling dan mengemis selama beberapa saat? Bagaimana jika ia mencoba penginapan lain dan ternyata mereka tidak menginginkan pria yang berdarah dan tidak sadarkan diri yang mungkin akan membuat tamu-tamu mereka takut (seperti imam dan orang Lewi)? Bagaimana jika tidak ada seorang pun kecuali orang Samaria yang peduli apakah orang yang terluka itu hidup atau mati?
Saat kompleksitas menjalani kisah tersebut terungkap, saya makin menyadari bahwa meneladani orang Samaria yang murah hati berarti menyelami lebih dalam dan merasa lebih sendirian daripada yang saya bayangkan.
Pada ujung jalan, saya tiba di rumah sakit lainnya. Saya bahkan tidak dapat menemukan ruang gawat darurat kalau tidak dibantu. Itu adalah bangunan kecil di belakang kampus, seperti bangunan yang sudah berusia 30 tahun. Begitu sampai, saya bertanya-tanya seperti apa sambutannya nanti. Saya berjalan ke IGD, meminta perawat untuk keluar ke mobil saya. Saya menjelaskan situasinya saat sekelompok kecil orang berkumpul. Perawat itu melihat ke belakang mobil dan menghilang ke UGD tanpa berkata apa-apa lagi. Saya tidak yakin apa yang sedang terjadi.
Setidaknya 10 menit kemudian, sebuah tandu muncul, dan wanita yang terluka itu naik ke atasnya. Dia menghilang ke dalam rumah sakit bersama anggota keluarga yang datang bersamanya. Satu-satunya yang tersisa adalah lelaki yang masih pingsan. Dia masih bernapas, dan saya senang melihat dia mulai mengerang sedikit. Malu rasanya, saya terus berpikir saya hampir bebas dari beban ini.
Seorang wanita yang berdiri di dekatnya bertanya, “Apa hubungan Anda dengan orang-orang ini?”
“Saya tidak kenal. Saya hanya sedang lewat, dan mereka harus pergi ke rumah sakit.”
“Tuhan memberkati Anda.”
Saya hanya ingin menangis.
Setelah tandu kembali dan pria itu dinaikkan ke atasnya, saya meminta untuk bertemu dengan anggota keluarga yang ikut bersama saya. Saya ingin memberinya sedikit uang secara diam-diam untuk menutupi sejumlah biaya awal, tetapi saya khawatir dia akan menggunakan semuanya untuk kerabatnya dan mengabaikan laki-laki itu.
Akhirnya saya memutuskan untuk memberi bantuan secara terang-terangan dan menghindari diskusi panjang tentang berapa banyak uang yang dia butuhkan. Pertama-tama saya masuk ke kursi pengemudi supaya tidak ditanya-tanya, kemudian saya menurunkan kaca jendela. Saya mengeluarkan sejumlah uang supaya orang itu dan orang banyak yang ada di sekitar dapat melihatnya. “Separuhnya untuk kerabat perempuanmu, separuhnya lagi untuk pria itu.” Seseorang yang tidak dikenal di antara kerumunan itu angkat bicara dan mengatakan bahwa dia mengerti dan semua orang di sini melihat bahwa pria ini perlu menghabiskan setengah uang tersebut untuk pengendara sepeda motor itu. Saya mengangguk sebentar, menyerahkan uang kepada saudara korban itu, lalu pergi.
Saya berpikir tentang bagaimana orang Samaria yang murah hati berjanji untuk kembali dan menanggung semua biaya tambahan. Rumah saya tiga jam perjalanan dari sana dan saya juga punya pasien yang harus diurus. Saya kira orang Samaria yang murah hati mungkin juga memiliki tanggung jawab sebesar itu. Bagaimana pun, saya tidak punya niat untuk kembali.

Perjalanan pulang terasa menegangkan saat malam tiba, tetapi untungnya tidak terjadi apa-apa. Saat saya melewati lokasi kecelakaan, saya mencoba melindungi wajah saya. Saya pikir orang banyak (yang masih ada di sana) mungkin mengenali saya, tetapi saya terus melaju.
Saya baru tiba di rumah larut malam, menjatuhkan diri ke sofa, ingin menangis tetapi merasa terlalu terbebani. Apa yang baru saja terjadi? Saya tidak begitu yakin. Penilaian medis saya adalah bahwa kehidupan beberapa orang mungkin telah berubah, tetapi mencoba meneladani orang Samaria yang murah hati benar-benar berbeda dari apa yang saya bayangkan.
“Siapakah sesamaku manusia?” tanya orang itu kepada Yesus yang memicu seluruh cerita. Pergilah dan jadilah sesama manusia, demikian Yesus menyimpulkan (Luk. 10:25–37).
Cerita ini menyakitkan. Sumur emosional saya nyaris kosong ketika seluruh masalah itu dimulai, dan saya akhirnya mengerti maknanya. Saya akan memutuskan untuk terlibat hingga titik tertentu, dan setiap kali saya mencapai titik itu, saya diminta untuk melangkah lebih jauh, lagi dan lagi.
Namun, seperti yang dinyatakan Martin Luther King Jr. dalam pidatonya “Saya Telah ke Puncak Gunung,” imam dan orang Lewi bertanya, “Jika saya berhenti untuk menolong orang ini, apa yang akan terjadi pada saya?” Orang Samaria bertanya, “Jika saya tidak berhenti untuk menolong orang ini, apa yang akan terjadi padanya?” Perumpamaan ini mengajak kita untuk berhenti berfokus pada diri sendiri dan berkorban bagi orang lain. Mengasihi berarti berkorban, dan pengorbanan itu menyakitkan.
Itu bukan sesuatu yang heroik. Sebaliknya, itu adalah kekacauan. Campur aduk antara beban saya sendiri dan beban tak terduga dari orang lain. Risiko yang tidak dapat dikurangi yang muncul ketika memasuki situasi yang penuh kekerasan dan membutuhkan. Pengalaman sepi yang merenggut lebih banyak hal dari yang saya harapkan.
Namun itulah gambaran sebenarnya dari perumpamaan tersebut. Sebelum pengalaman ini, jika Anda bertanya seandainya saya dihadapkan pada situasi yang sama seperti orang Samaria yang murah hati, saya kira saya akan melakukan hal yang sama, meski dengan ragu-ragu.
Namun sekarang saya bisa melihat kalau sebelumnya itu asumsi yang keliru. Saya berasumsi kesempatan untuk berkorban seperti itu akan datang di saat yang, jika tidak sempurna, mungkin optimal atau setidaknya tidak terlalu merepotkan. Saya berasumsi bahwa pemilik penginapan akan menyambut saya dengan senyuman dan orang lain akan bersatu untuk bekerja sama. Saya berasumsi biayanya akan lebih bersifat finansial daripada emosional. Saya berasumsi bahwa melangkah dalam ketaatan, meskipun sulit, akan berakhir dengan perasaan puas, seperti napas berat dan keringat yang keluar di akhir latihan yang baik.
Akan tetapi yang terjadi tidak seperti itu. Sebagai seorang dosen kedokteran di salah satu negara termiskin di dunia, saya dapat katakan bahwa biaya emosional itu tinggi, entah Anda berupaya menolong satu atau dua orang di pinggir jalan atau menangani masalah sistemik yang mengakibatkan orang-orang terluka di pinggir jalan. Berusaha keras untuk melakukan perubahan sistem dari hulu seperti itu merupakan hal yang bijaksana tetapi juga berantakan.
Krisis datang saat kita berdoa agar hal itu tidak terjadi, dan risiko serta dampaknya mungkin meningkat jauh melampaui perkiraan kita saat kita semakin terseret ke dalam kekacauan.
Saya sering teringat akan dampak-dampak ini, saat saya melihat darah kering yang tidak bisa saya bersihkan dari jok RAV4 kami. Namun kekacauan dan sakit hati inilah yang sebenarnya menjadi inti cerita.
Jika saya dapat kembali dan melakukannya lagi, saya akan mengingatkan diri sendiri tentang beberapa perkataan Yesus lainnya yang tidak pernah terlintas dalam pikiran saya di hari itu. Yesus memberi tahu kita dalam Matius 25:40 bahwa melayani orang yang membutuhkan berarti melayani Dia. Dia ada di bagasi saya, tak sadarkan diri. Dia hadir saat perempuan itu berteriak.
Pengorbanan saya sebenarnya adalah kesempatan untuk membopong Tuhan berkeliling kota sampai menemukan tempat yang cocok.
Jangan kita menunggu momen imajiner ketika keadaan dan suasana hati bertemu. Marilah kita menerima cedera yang tak terelakkan di dunia kita yang jatuh ini sebagai kesempatan yang menyakitkan tetapi penuh berkat.
Marilah kita bersama-sama mengevaluasi risiko kasih Kristen dan saling mendukung dalam penderitaan kita. Marilah kita mengingat bahwa Tuhan kita hadir di tengah mereka yang membutuhkan—dan di dalam diri kita, meskipun kita sendiri tidak mampu.
Eric McLaughlin adalah seorang dokter misionaris di Burundi dan penulis Promises in the Dark: Walking with Those in Need Without Losing Heart.
Diterjemahkan oleh Denny Pranolo.