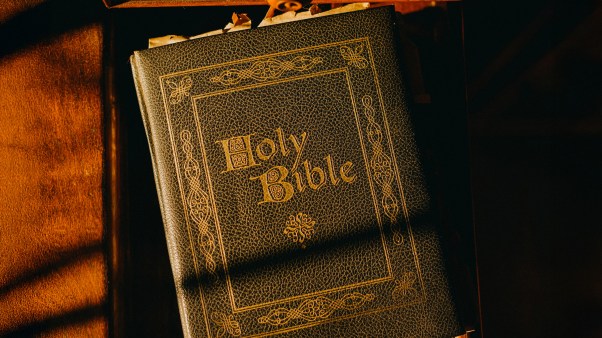Saya dibesarkan di sebuah kota kecil di Texas Selatan. Sebagai seorang anak imigran, saya dibesarkan untuk menghargai pendidikan sebagai tiket menuju kehidupan yang baik dan penerimaan sosial. Kami adalah keluarga sekuler, tetapi kesadaran rohani saya tumbuh ketika saya berhadapan dengan kekurangan saya sendiri.
Saya berusia lima tahun ketika, setelah saya berperilaku buruk, ayah saya memukul saya dan saya membalas dengan menggigit punggungnya. Namun saat itu juga, saya merasa sangat menyesal. Orang tua saya segera mengusir saya dari rumah, dan saya menghabiskan malam itu dengan meringkuk di dalam mobil keluarga sambil menangis. Saya berdoa kepada Tuhan untuk memohon pengampunan. Setelah beberapa waktu, saya masuk ke dalam dan memberi tahu ayah saya bahwa saya menyesal.
Saya memiliki naluri untuk berdoa karena orang tua saya, meskipun tidak religius, telah mendaftarkan saya di sekolah dasar Katolik, yang mereka pilih karena kualitas pendidikannya. Di sekolah inilah saya mengembangkan rasa kagum terhadap ruang-ruang suci, seperti katedral, dan terhadap tokoh-tokoh suci seperti Yesus, yang tergantung di kayu salib di sana. Saya sering duduk di bangku gereja dan membayangkan apa yang akan Dia katakan kepada saya. Namun jika tidak, saya lebih sering mengabaikan Tuhan.
Imajinasi saya teralihkan seiring bertambahnya usia. Saya berprestasi sangat baik di sekolah, terutama dalam bidang matematika. Matematika menyulut rasa kagum dan takjub dalam diri saya. Ada tatanan mempesona di alam semesta yang bisa dibuka melalui matematika. Saya semakin menghargai betapa kebenaran matematika itu nyata, meski tidak bersifat fisik, dan bagaimana kebenaran tersebut memengaruhi dunia, meski ada di luar dunia. Semua ini terasa seperti wawasan spiritual.
 Fotografi oleh Abigail Erickson untuk Christianity Today
Fotografi oleh Abigail Erickson untuk Christianity TodayNamun, kegembiraan saya dalam belajar terjerat oleh godaan kesuksesan. Berjuang tanpa henti untuk berprestasi, saya pun mulai membingkai identitas saya pada kepintaran daripada belajar demi memperoleh manfaat intrinsiknya. Pencarian akan prestasi mendorong setiap upaya saya, mulai dari mendapatkan nilai bagus hingga memenangkan kompetisi matematika. Saya sangat ingin membuktikan diri saya layak atas sesuatu dan menjadi seseorang.
Saya masuk perguruan tinggi pada tahun 1985 di tengah meningkatnya ketegangan Perang Dingin dan ketakutan akan perang nuklir. Saya mengerjakan kumpulan soal matematika dan fisika dengan teman sekelas saya, William, yang memiliki pengetahuan ilmiah yang sangat luas. Pada dinding kamar asramanya terdapat peta Amerika Serikat yang mengerikan, yang dia warnai berdasarkan penelitiannya sendiri. Setengah lebih dari kota-kota besar ditutupi oleh bulatan hitam, dikelilingi dengan lingkaran-lingkaran konsentris berwarna merah, oranye, dan kuning. Hanya beberapa wilayah tak berpenghuni di bagian Barat yang dibiarkan tanpa kerusakan.
“Apa yang diwakili oleh warna-warna itu?” Saya bertanya pada William dengan kagum. “Tingkat kehancuran jika terjadi perang nuklir,” jawabnya. Jawabannya yang lembut membuat saya sangat terkejut dengan kengerian yang ada di peta tersebut. Ketakutan yang saya rasakan atas bencana seperti itu hanya memperkuat rasa keterpurukan pribadi yang sedang saya alami.
Kedua orang tua saya baru saja didiagnosis mengidap penyakit serius—ayah saya menderita kanker usus besar dan ibu saya menderita ALS, atau penyakit Lou Gehrig. Meskipun prognosis ayah saya tidak pasti, tetapi penyakit ibu saya sudah pasti—ALS belum diketahui obatnya. Tak lama lagi dia akan lumpuh, pikirannya yang jernih akan terperangkap dalam tubuh yang tidak responsif.
Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya terpaksa menghadapi kesia-siaan hidup yang dibenturkan pada kenyataan buruk akan kematian. Ramalan William memaksa saya untuk bergulat dengan absurditas itu dalam skala besar. Untuk mencari kepastian, saya bertanya kepadanya, “Apakah masih ada harapan?”
“Tidak, kecuali kamu percaya kepada Tuhan,” katanya, hampir tanpa suara. William adalah orang yang lemah lembut yang mungkin tidak berniat memulai percakapan ini, tetapi dia menjawab pertanyaan saya yang sungguh-sungguh itu dengan sebaik mungkin. Saya terkejut saat mengetahui bahwa dia adalah seorang Kristen, dan saya penasaran bagaimana seorang intelektual seperti dia dapat merasionalkan keyakinan agamanya. Dia adalah orang Kristen pertama dari beberapa orang Kristen cerdas yang saya temui di perguruan tinggi, tetapi tampaknya ia hidup menurut ukuran kesuksesan yang berbeda.
“Jiwa tidak akan menyerah pada keputusasaan sampai ia menghabiskan semua ilusinya,” tulis Victor Hugo, salah satu penulis favorit saya, di kisah Les Misérables. Begitulah keputusasaan menguasai saya. Saya pun mulai melihat janji yang kosong akan prestasi. Dunia bisa diledakkan oleh ribuan hulu ledak nuklir, atau keluarga saya bisa hancur karena penderitaan dan patah hati. Mendapatkan nilai bagus tidak ada artinya dalam skenario ini. Pekerjaan dan relasi tampak tidak berarti. Prestasi, kesuksesan, kebahagiaan—untuk apa semua itu?
Keputusasaan saya mencapai titik puncaknya menjelang akhir tahun pertama saya. Suatu malam ketika saya merasa sangat tertekan, saya berkeliaran di sekitar kampus selama berjam-jam, dengan rasa penuh beban yang menyesakkan dalam jiwa saya. Ketika kembali ke asrama, saya masuk ke dalam lift bersama dua orang lainnya yang memulai percakapan dengan saya tentang Yesus. Biasanya saya mungkin akan mundur, tetapi di malam itu saya bisa menerima.
Kami makan siang dua hari kemudian, dan saya mencurahkan semua pertanyaan saya tentang Tuhan. Mereka mempresentasikan iman Kristen bukan sebagai seperangkat keyakinan agama yang dirancang untuk memaksakan moralitas, melainkan sebagai suatu relasi dengan Yesus. Itu merupakan hal baru bagi saya. Mereka menunjukkan kepada saya bahwa Yesus adalah Pribadi yang penuh penderitaan, yang akrab dengan kesedihan. Dia menderita, yang berarti Dia bisa memahami penderitaan keluarga saya.
Untuk pertama kalinya, saya memahami pentingnya anugerah. Kita berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan diri kita benar, untuk mendapatkan martabat kita melalui moralitas dan prestasi, namun tidak satu pun dari upaya ini yang dapat menyembuhkan kita, karena tidak ada yang benar, seorang pun tidak (Rm. 3:10). Pesan tersebut mungkin mengejutkan saya sebagai seorang mahasiswa yang ingin memiliki semuanya secara moral dan intelektual, tetapi pesan itu beresonansi dengan diri saya yang dahulu masih berusia lima tahun, yang meringkuk di dalam mobil karena malu dan menyadari betapa dalamnya dosa saya.
Kerangka ajaran Kristen tiba-tiba menjadi masuk akal. Yesus menawarkan kelegaan dari rasa kesepian yang saya rasakan dan sebuah jaminan hidup yang lebih dari apa yang bisa saya lihat dari sudut pandang saya yang terbatas. Tentu saja, saya tahu bahwa jika saya menempuh jalan ini, saya tidak akan membuang pikiran saya—saya harus benar-benar membaca Alkitab dan menyelidiki segala ajarannya. Namun saya mengambil sebuah lompatan dan memutuskan untuk menyerahkan hidup saya kepada Yesus.
Malam harinya, saya memberi tahu William. Dengan senang hati, dia mengungkapkan bahwa dia telah mendoakan saya sepanjang tahun.
Mengikuti Yesus secara radikal mengubah tempat saya mencari makna dan pengharapan, meskipun masalah-masalah hidup saya tidak serta merta hilang. Penderitaan terus melanda keluarga saya. Dan saya memerlukan lebih banyak waktu untuk menghadapi penyembahan berhala saya terhadap kinerja sebagai ukuran harga diri, terutama saat saya mengejar gelar doktor matematika di Harvard. Namun menjalani perjalanan rohani ini membawa saya menuju jalan untuk memahami mengapa beberapa hal dalam hidup ini begitu buruk dan yang lainnya begitu mulia.
Sekarang saya mengerti mengapa mempelajari keindahan itu penting, meskipun hal tersebut tidak ada penerapan secara langsung. Keindahan penalaran dan keteraturan yang kita lihat dalam berbagai pola mencerminkan sesuatu yang ilahi dan karenanya layak dipelajari demi kepentingan pola-pola itu sendiri, bukan untuk kemuliaan pribadi.
Sekarang saya mengerti mengapa penderitaan memiliki makna. “Orang berhikmat senang berada di rumah duka” (Pkh. 7:4), karena penderitaan mempertajam indra kita untuk melihat kehidupan dengan lebih kaya.
Dan sekarang saya mengerti mengapa relasi-relasi memiliki makna. Ketika saya meratapi bagaimana saya menyakiti hati ayah saya, ketika saya menikmati persahabatan yang erat, atau ketika saya menangis bersama mereka yang menderita, saya menghargai gambar Allah dalam diri orang lain. Menyadari hal ini telah mengilhami saya untuk memperdalam hubungan saya dan membuat saya lebih perhatian untuk melayani mereka yang terpinggirkan, yang diidentifikasi dan diprioritaskan oleh Yesus.
Di dalam Tuhan, saya telah menemukan kelegaan dari perjuangan saya yang sia-sia demi menjadi pribadi yang berarti. Yesus yang figurnya tergantung di kayu salib di katedral, kini berbicara kepada saya di dalam lubuk hati saya, mengingatkan saya bahwa kasih Tuhan, sebagai sumber martabat saya, adalah cukup.
Francis Su adalah penulis Mathematics for Human Flourishing dan seorang profesor matematika di Harvey Mudd College. Dia dan keluarganya tinggal di Pasadena, California.
Diterjemahkan oleh Maria Fennita S.