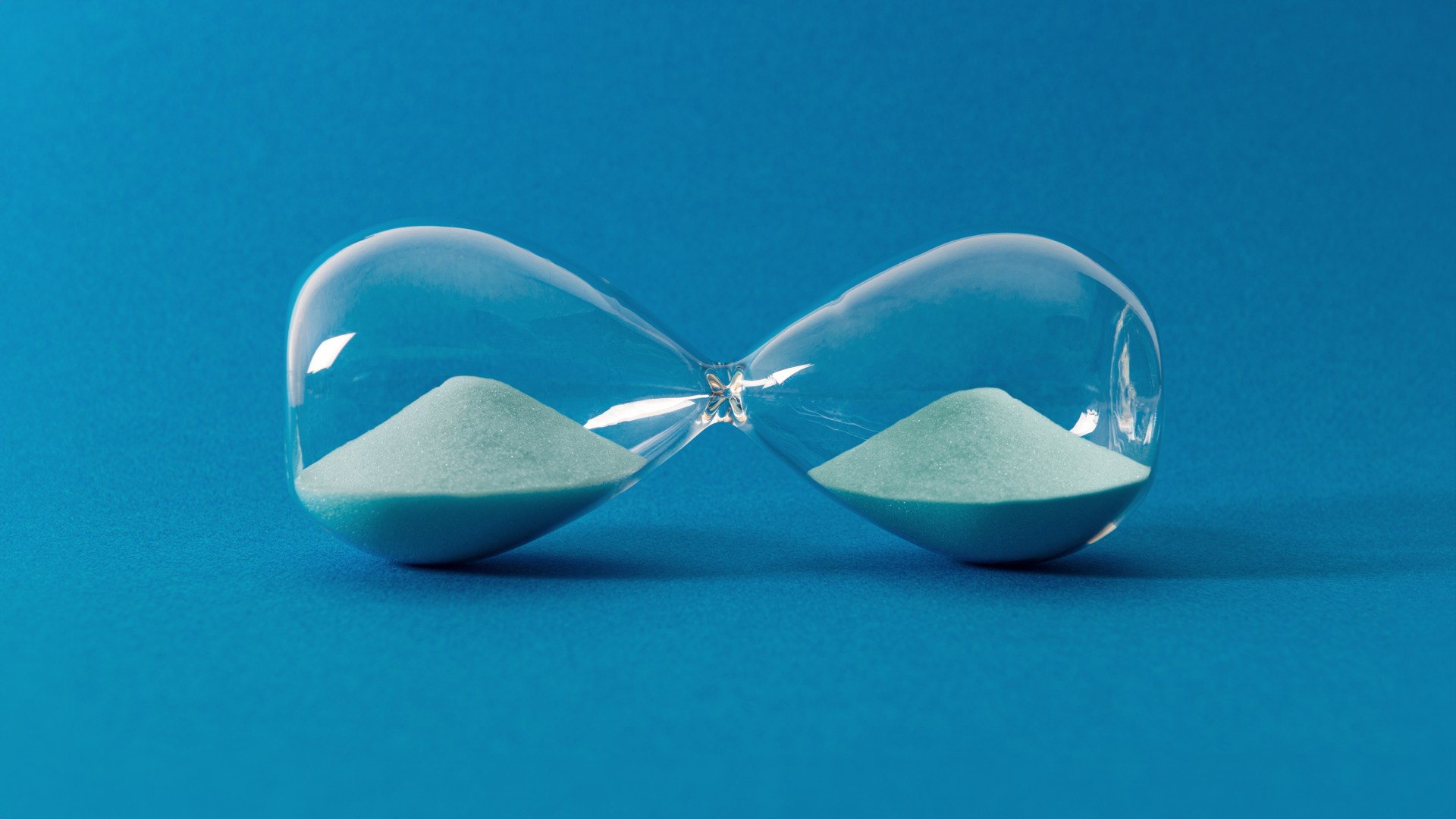Jika Musa mengeluarkan ponselnya untuk merekam semak yang menyala, alih-alih memberi perhatian sepenuhnya, mungkinkah ia melewatkan suara Tuhan?
Jika Maria sedang menggulir ponselnya di waktu istirahat dari rutinitas hariannya, mungkinkah pikirannya akan terlalu terdistraksi untuk memperhatikan kedatangan malaikat?
Musa dan Maria adalah saksi atas masuknya yang abadi ke dalam yang fana, masuknya keajaiban yang mengganggu yang biasa-biasa saja. Mereka sepenuhnya hadir dalam waktu.
Dapatkah kita mengatakan hal yang sama tentang diri kita? Kita khawatir waktu menjadi semakin langka dan ingin melarikan diri dari hal-hal yang terasa membuang waktu: TV dan berita, pesan teks dan surel. Namun paradoksnya, kita justru beralih ke teknologi yang sama untuk mempercepat waktu ketika merasa bosan atau ingin mengalihkan perhatian. Video dan foto yang kita ambil dengan ponsel, menarik kita menjauh dari pengalaman penuh dari momen tersebut.
Upaya menimbun atau menyia-nyiakan waktu justru hanya membuat hari-hari berlalu semakin cepat. Seperti jam pasir yang bocor di bagian bawahnya, waktu mengalir perlahan tanpa kita sadari hingga tiba-tiba kita terkejut saat kita menyadari bahwa pasirnya sudah hampir habis. Bagaimana kita bisa menambal jam pasir itu dan mulai memulihkan, satu per satu, butiran-butiran waktu yang hilang?
Selama enam tahun saya tinggal di Washington, DC, waktu selalu menjadi sumber ketegangan. Saya ingin waktu berjalan lebih cepat, tetapi juga ingin melambat. Saya menghitung menit dengan obsesif setiap kali berada di perjalanan—berjalan kaki, bersepeda, atau naik kereta bawah tanah. Jika saya terhenti—misalnya menunggu di antrean toko atau di bus umum—saya langsung mengeluarkan ponsel dan menggulir tanpa henti, berusaha melarikan diri dari waktu, berharap menit-menitnya berlalu lebih cepat. Saya mungkin akan melewatkan semak yang menyala itu, atau kembali menatap layar ponsel ketika malaikat datang mengganggu rutinitas saya.
Pertarungan saya dengan waktu membuat saya bereksperimen. Saya dengan sungguh-sungguh mencoba berbagai praktik, misalnya menerapkan Sabat, retret di tempat sunyi, berjalan jauh tanpa ponsel, membaca Book of Common Prayer, dan berpuasa dari media sosial. Semua itu tidak pernah terasa cukup.
Praktik-praktik ini sering kali terasa seperti tuntutan tambahan—upaya lain untuk memeras lebih banyak menit dari jadwal yang sudah padat. Semuanya cenderung bersifat pribadi. Hidup terasa seperti pertarungan seorang diri yang bergulat melawan budaya yang selalu ingin mengonsumsi lebih banyak waktu—lebih banyak dari diri saya—entah itu tekanan untuk bekerja, menonton Netflix, menggulir media sosial, atau membaca berita. Saya berjuang agar tidak tertinggal, agar tetap seirama, sambil tetap menyisihkan waktu untuk teman, keluarga, gereja, dan istirahat—yang pada akhirnya semua itu juga mulai terasa seperti kewajiban.
Saya telah cukup banyak membaca untuk tahu bahwa hubungan yang tidak sehat dengan waktu bukanlah masalah pribadi semata, melainkan masalah budaya, dan terutama memicu kecemasan pada generasi muda. Namun, saya belum banyak memikirkan tentang bagaimana komunitas iman dapat menolong. Ternyata, mengubah cara saya memperlakukan waktu seorang diri bukanlah hal yang berkelanjutan—bahkan tidak mungkin. Itu semua membutuhkan gereja.
Gereja Anglikan tempat saya beribadah di DC memulai sebuah program baru bernama Christian Formation Cohort. Saat pertama kali membaca formulir komitmennya, saya langsung berpikir, “Tidak mungkin.” Persyaratannya tampak luar biasa berat untuk ukuran kota seperti DC. Akan tetapi saya tidak bisa mengabaikan dorongan dalam hati yang berkata bahwa saya perlu ikut berpartisipasi.
Program enam minggu itu mencakup daftar panjang praktik rohani yang dirancang untuk “penanggalan” (detachment) dan “pertautan” (attachment), yang dilakukan secara bertahap. Praktik penanggalan mencakup tidak menggunakan media sosial, tidak menonton tayangan visual sendirian (diperbolehkan maksimal tiga jam seminggu bersama orang lain), tidak mendengarkan audio selain Alkitab dan musik rohani, serta tidak membaca selain Alkitab dan bahan bacaan yang sesuai dengan Filipi 4:8.
Praktik pertautan mencakup menghadiri sesi kelompok mingguan, doa 30 menit setiap hari dalam sikap penyerahan diri, pembacaan Alkitab yang mendalam setiap hari, pelayanan sukarela mingguan, puasa mingguan, praktik keramahtamahan dan “persahabatan rohani” mingguan, Sabat mingguan, satu retret selama 10 jam, serta menghadiri satu perjamuan makan setiap bulan selama empat bulan setelah program enam minggu berakhir.
Saya langsung terkesan dengan bagaimana semua praktik ini sangat berkaitan dengan waktu. Praktik penanggalan menuntun kita untuk menghabiskan lebih sedikit waktu (atau tidak sama sekali) dengan gangguan yang tidak disadari. Sementara praktik pertautan mendorong kita untuk meluangkan lebih banyak waktu bersekutu dengan orang lain, dengan Firman Tuhan, dan dengan Bapa, Anak, serta Roh Kudus.
Bagi kami, pertanyaan cemas yang muncul pada minggu pertama cukup sederhana: Apa yang akan saya lakukan saat pulang kerja setelah hari yang panjang? Menatap dinding? Kami diminta untuk mempersiapkan diri dengan membuat daftar aktivitas alternatif serta daftar orang atau situasi yang akan kami doakan selama waktu yang telah ditentukan.
Dalam bukunya The Congregation in a Secular Age, Andrew Root mengemukakan bahwa pengalaman manusia modern terhadap waktu adalah seperti jenis kelaparan—hasrat yang tak terpuaskan, bukan hanya untuk memiliki lebih banyak jam dalam sehari, tetapi untuk mengalami pengalaman yang lebih penuh dan bermakna dari setiap momen yang berlalu. Silicon Valley mendorong kita untuk berinovasi, mempercepat, dan memaksimalkan, sehingga memungkinkan kita terus-menerus melakukan banyak hal sekaligus, melakukan lebih banyak hal dengan lebih cepat. Ironisnya, perangkat yang katanya dibuat untuk menghemat waktu justru membuat kita merasa tidak pernah memiliki cukup waktu. Kita tidak bisa melambat cukup lama untuk mendengarkan pikiran kita sendiri, apalagi mendengarkan bisikan Roh Kudus.
Kekacauan yang konstan ini membuat gereja semakin sulit untuk membimbing jemaat masuk ke dalam waktu yang kudus. Sebaliknya, “waktu dikosongkan demi kecepatan”; tujuan gereja pun bergeser menjadi perubahan dan pertumbuhan yang dipaksakan, bukan lagi “transformasi di dalam Roh.” Kita membutuhkan gereja yang berani melawan arus budaya percepatan dan menjadi tempat di mana kita belajar untuk tinggal dalam hal-hal yang kudus, misterius, dan kekal.
Seiring saya menyesuaikan diri dengan program itu, waktu seolah berubah. Perjalanan dengan kereta bawah tanah terasa lebih panjang, malam di rumah terasa lebih lapang, dan doa 30 menit setiap pagi menjadi penghiburan, bukan lagi kewajiban. Beberapa praktik penanggalan terasa mudah bagi saya. Namun praktik-praktik pertautan seperti menghafal ayat Alkitab, pelayanan sukarela, dan berpuasa terasa sangat sulit untuk dimasukkan ke dalam jadwal saya yang sudah penuh. Beberapa minggu, saya benar-benar gagal melakukannya, dan rasa lapar karena melewatkan makan justru membuat saya semakin gelisah.
Praktik yang paling mengejutkan bagi saya adalah mendengarkan Alkitab dalam bentuk audio. Saya mendengarkannya saat memasak, saat mencuci piring. Perlahan, suara-suara di pikiran saya berubah. Alih-alih kekacauan dan kebisingan, saya merasakan ketenangan dan kedamaian yang menghidupkan jiwa.
Dampak kumulatif dari mengonsumsi lebih sedikit hal, dengan hanya mengonsumsi “semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, dan patut dipuji,” ternyata sangat membebaskan. Alih-alih menjejali diri dengan lebih banyak konten selama perjalanan saya di kereta bawah tanah atau di rumah, saya justru diberi ruang untuk diam bersama pikiran saya, dan untuk berdoa ketika hati digerakkan—suatu dorongan yang mungkin akan saya lewatkan jika sibuk menatap layar ponsel atau menonton Netflix.
Namun komunitaslah yang paling membawa perubahan nyata. Pada hari-hari kami bertemu sebagai kelompok, waktu seolah sepenuhnya kehilangan strukturnya ketika kami larut dalam kisah-kisah satu sama lain. Kami saling berempati hanya dengan mengetahui betapa sulitnya mempraktikkan semua ini, dan saling menguatkan satu sama lain dalam ketulusan bersama untuk belajar menghuni waktu dengan cara yang baru.
Berbagi pengalaman dengan orang lain—dengan air mata, tawa, dan kata-kata penuh hikmat yang mengalir bebas—menciptakan momen-momen yang oleh Root disebut sebagai “resonansi,” solusi atas kelaparan waktu kita. Resonansi, menurut Root, adalah waktu yang dikumpulkan kembali, dipenuhi dengan makna dan tujuan. Untuk menciptakan resonansi, kita harus keluar dari diri sendiri dan meletakkan ponsel kita. Dalam perjumpaan dengan Allah atau sesama, pada momen saat kita memperluas diri, kita membuka diri kita, menjadi rentan untuk menerima momen kasih karunia yang ditetapkan secara ilahi. Resonansi mengisi kembali jam pasir kehidupan, mencukupi kita alih-alih memeras kita.
Ketika saya berbicara dengan salah satu pendeta yang memimpin kelompok kami, ia mengatakan bahwa yang membuat kelompok ini efektif adalah kesederhanaannya—merujuk kembali pada “dasar-dasar” iman Kristen. Irama penanggalan dan pertautan yang berfokus pada komitmen, bukan hasil, terasa segar di zaman di mana kita terus-menerus dituntut untuk mengoptimalkan waktu kita. Puasa dan doa mungkin tidak “produktif” dengan cara yang dapat kita lihat secara langsung.
Namun pada kenyataannya, berkumpul bersama dan membaca Alkitab serta berdiam dalam keheningan adalah praktik-praktik sederhana dan historis, segar di setiap zaman sepanjang sejarah. Di DC, yang menduduki posisi kota paling kesepian di Amerika, pendeta saya berkata bahwa kita juga perlu memandang komunitas sebagai disiplin rohani. Kita tidak dapat merebut kembali waktu yang kudus sebagai individu-individu yang terisolasi, apalagi dengan hadirnya teknologi yang begitu kuat dan adiktif. Ini adalah tugas yang terlalu berat untuk dilakukan sendirian.
Program yang bersifat kontra budaya tersebut mengubah relasi saya dengan waktu—melihat waktu sebagai sesuatu yang melimpah, bukan langka; waktu sebagai kesempatan, bukan beban; waktu sebagai ruang untuk dijalani bersama orang lain, bukan untuk dihabiskan bagi diri sendiri.Seperti yang diingatkan dalam Mazmur 90, kita harus diajarkan untuk menghitung hari-hari kita dan memperhatikan bagaimana kita menggunakan waktu dalam terang kekekalan; sebab “di mata-Mu seribu tahun sama seperti hari kemarin” (ay. 4).
Beberapa bulan setelah program itu selesai, alih-alih melawan arus budaya sendirian, saya mulai ikut memfasilitasi retret akhir pekan dalam keheningan dan berpartisipasi dalam makan malam mingguan. Saya juga berkomitmen untuk berdoa dan membaca Alkitab setiap pagi, kali ini bersama seorang teman. Waktu yang dihabiskan bersama dalam pujian dan permohonan terasa berlipat ganda dan melambat. Waktu terisi penuh, namun tidak menyesakkan; waktu menjadi beresonansi. Semak yang menyala itu kembali berkilauan, dan Tuhan berbicara.
Gereja yang dikenal karena kemampuannya membawa orang masuk ke dalam waktu yang transenden dan kudus adalah tempat peristirahatan sejati di tengah budaya konsumsi dan percepatan yang tidak pernah puas. Ini adalah tempat yang menarik untuk tinggal di dalamnya—di masa lalu, masa kini, dan masa depan.
Aryana Petrosky adalah mahasiswa pascasarjana di The University of Edinburgh yang meneliti persinggungan antara monastisisme ekumenis, disiplin rohani, dan iman di ruang publik. Ia turut meluncurkan The After Party: Toward Better Christian Politics dan sebelumnya bekerja di American Enterprise Institute’s Initiative on Faith & Public Life.