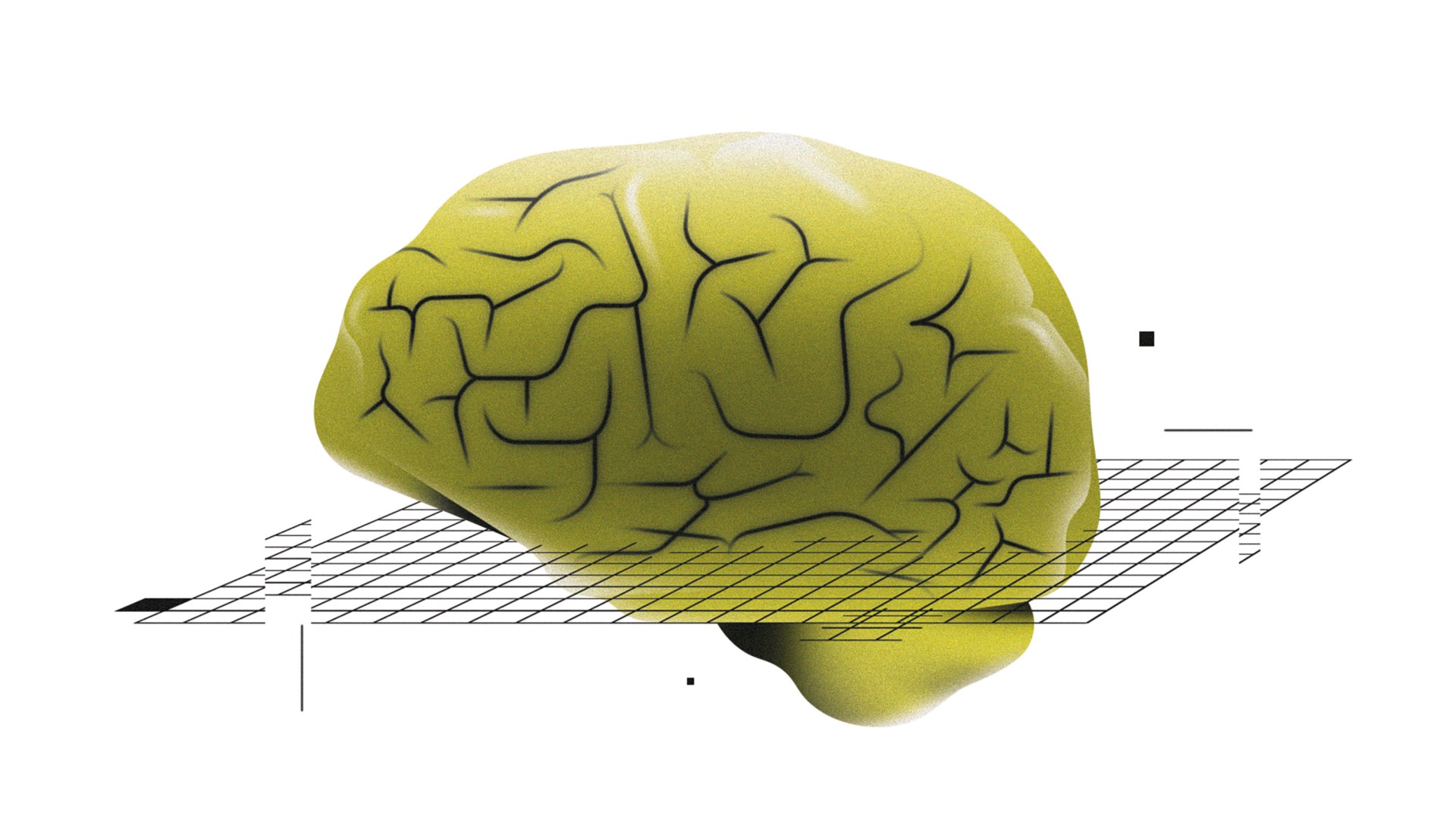Lima bulan sebelum peluncuran ChatGPT pada November 2022, peneliti AI dan wakil presiden Google, Blaise Agüera y Arcas, [menggambarkan] di The Economist percakapannya dengan LaMDA (Language Model for Dialog Applications – Model Bahasa untuk Aplikasi Dialog) Google, pendahulu Gemini. Dia menulis, “Saya merasakan tanah bergeser di bawah kaki saya. Saya semakin merasa seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang cerdas.” Sekitar seminggu kemudian, insinyur Google, Blake Lemoine, secara terbuka mengklaim bahwa LaMDA telah menjadi kecerdasan buatan yang memiliki akal.
Saat kita berinteraksi dengan AI, tanpa sadar kita menganggap adanya kecerdasan alami di sistem tersebut, padahal sebenarnya tidak ada. Ketika model-model AI ini terus diintegrasikan ke dalam teknologi dan perangkat kita, bagaimana kita seharusnya memandang AI, terutama dalam konteks kecerdasan alami kita sendiri?
Kecerdasan alami merupakan anugerah yang diberikan Allah untuk memahami dan bernalar tentang realitas, satu sama lain, dan diri kita sendiri. Sebaliknya, kecerdasan buatan adalah sub-disiplin ilmu komputer yang berkaitan dengan pembangunan model untuk melakukan tugas yang sering dikaitkan dengan kecerdasan alami, seperti memecahkan teka-teki atau meringkas teks. Kesenjangan antara kecerdasan alami dan buatan terkadang digambarkan kecil tetapi sebenarnya itu adalah jurang yang lebar.
Walaupun beberapa teknik AI terinspirasi oleh gagasan-gagasan dalam ilmu saraf dan psikologi perilaku, tetapi sebagian besar model AI hanya memiliki sedikit kemiripan dengan sistem biologis. Metode AI lainnya diambil dari disiplin ilmu seperti pemrosesan sinyal, biologi evolusioner, dan mekanika Newton. Misalnya, algoritma genetika adalah sebuah kelas teknik pengoptimalan yang terinspirasi oleh prinsip evolusi seleksi alam, mutasi, dan spesiasi. Para peneliti AI menyatakan bahwa “plausibilitas biologis merupakan panduan, bukan persyaratan ketat” dalam merancang model AI. Meskipun suatu tugas tampaknya memerlukan mesin biologis dari kecerdasan alami, AI tidak perlu meniru mesin ini agar berhasil.
Kecerdasan alami dan buatan tidak dapat dibandingkan. Meyakini bahwa keduanya setara merupakan penghinaan terhadap mereka yang memiliki kecerdasan alami dan merugikan mereka yang mengembangkan kecerdasan buatan.
Mengukur kecerdasan alami berbeda dengan mengukur kinerja AI. Para psikolog telah lama mengetahui bahwa kecerdasan alami tidak dapat diringkas menjadi satu skor tunggal, seperti IQ. Banyak teori yang dibuat untuk mengukur kecerdasan alami memiliki akar yang “tidak baik.” Teori-teori tersebut didasarkan pada gagasan-gagasan pseudosains seperti eugenika, frenologi, dan Darwinisme sosial. Dan banyak skor tingkat kecerdasan dirancang untuk memberi keistimewaan pada individu tertentu dibandingkan yang lain.
Meski demikian, mengukur kecerdasan alami tetaplah sulit, terutama jika kecerdasan non-manusia juga ikut diperhitungkan. Mengevaluasi performa AI pada tugas tertentu relatif mudah: Kita menguji AI dengan serangkaian input dan membandingkan keluarannya dengan ekspektasi kita. Makin banyak tolok ukur untuk model bahasa besar yang dibuat. Tujuannya adalah mengukur kinerja tugas mode-model bahasa itu, mulai dari lulus ujian pengacara hingga menerjemahkan teks secara akurat sampai membuat keputusan moral.
Karena model AI terus meningkat menurut tolok ukur yang ditetapkan industri, kita harus belajar dari kesalahan kita saat mengukur kecerdasan alami. Menilai kecerdasan seseorang dengan satu angka saja dapat sangat berbahaya dan bersifat reduktif, terlepas apakah perbandingannya dilakukan antara dua orang atau antara dua model AI.
Kebutuhan untuk mengukur kecerdasan model AI dan diri kita sendiri mencerminkan seberapa penting (secara sosial dan moneter) penilaian kecerdasan bagi kita. Setidaknya satu surat terbuka yang ditulis oleh Future of Life Institute dan ditandatangani oleh banyak pakar AI memuat frasa penting yang sama: “Segala sesuatu yang ditawarkan peradaban adalah produk kecerdasan manusia.”
Memprioritaskan kecerdasan sebagai satu-satunya sumber kemajuan sama saja mengabaikan sifat-sifat pemberian Allah lainnya seperti kreativitas dan kebijaksanaan. Mengidolakan kecerdasan berarti mengabaikan nila-nilai Kristen yang telah lama dipegang seperti kesalehan, kerendahan hati, dan pengorbanan diri. Pemujaan masyarakat kita terhadap kecerdasan di tengah model AI yang canggih telah menyebabkan banyak orang takut akan devaluasi yang akan segera terjadi. Kisah-kisah fiksi ilmiah yang kita ceritakan tentang kecerdasan umum buatan (AGI) hipotetis—di mana mesin superintelijen menaklukkan mereka yang dianggapnya lebih rendah intelektualnya—cenderung mencerminkan sejarah kita sendiri. Para pendahulu kita, para penjajah, telah melakukan hal itu di masa lalu.
Orang Kristen dapat menempuh jalan antara dua ekstrem, mengidolakan dan menolak kecerdasan. Kita tahu bahwa kita dituntut untuk “berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah [kita]” (Mi. 6:8). Kecerdasan saja tidak cukup untuk melaksanakan kehendak Allah bagi hidup kita. Kita dipanggil untuk tidak “menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi [kita]” (Rm. 12:2). Maka marilah kita dengan rela menyerahkan kecerdasan alami kita kepada Tuhan agar Dia pakai dan bentuk.
Mengenai kecerdasan buatan, kita tidak boleh mencampuradukkan sarana yang kita buat dengan pikiran yang kita miliki. Marilah kita gunakan semua sarana yang diberikan kepada kita untuk memajukan kerajaan Allah.
Marcus Schwarting adalah editor senior di AI dan Faith. Dia juga seorang peneliti yang menerapkan kecerdasan buatan untuk masalah-masalah dalam kimia dan ilmu material.
Diterjemahkan oleh Denny Pranolo.